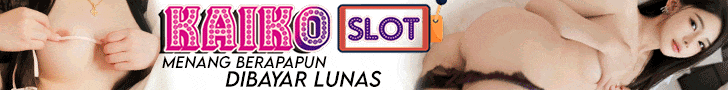Ruang tamu rumah Bu Vita tampil seperti etalase kenyamanan kelas menengah atas. Sofa krem berlapis kain impor tersusun rapi, bantal-bantalnya terlalu bersih untuk benar-benar dipeluk. AC berdengung lembut, parfum mahal saling bertabrakan, entah mawar, entah vanilla—mencipta aroma campuran yang sulit dikenali.
“Silakan duduk, Bu… eh Bu Rina ya?” suara Bu Vita lembut tapi presisi, seperti tahu persis siapa duduk di mana.
“Iya, Bu. Aduh dingin banget AC-nya,” jawab Bu Rina sambil terkekeh, meski tangannya tak bergerak sedikit pun untuk mencari remote.
Meja panjang di sudut ruangan penuh penganan cantik yang tampak lebih siap difoto daripada dimakan. Kue-kue kecil berjajar rapi, salad buah dalam mangkuk bening, dan termos bermerek yang sengaja diletakkan menghadap pintu.
“Termos barunya ya, Bu Vita?” celetuk seseorang.
Bu Vita tersenyum tipis. “Ah, biasa aja. Anak saya yang maksa.”
Para ibu duduk berkelompok, tas-tas berbaris di samping kursi seperti piala sunyi. Obrolan mengalir ringan namun berkilau.
“Kemarin ke Jepang dingin banget, lho,” kata Bu Maya, nada suaranya seolah menahan detail agar tak terdengar pamer.
“Ih, enak ya… aku mah ke Bandung aja udah bersyukur,” sahut yang lain, tertawa kecil.
“Aduh, sopir baru saya tuh,” lanjut Bu Maya tanpa diminta, “jalannya muter-muter. Katanya GPS-nya ngaco, padahal rumah saya kan tinggal masuk dikit.”
Tawa terdengar terukur, dijaga rapi sesuai citra. Bu Vita bergerak anggun dari satu kelompok ke kelompok lain.
“Makanannya kurang nggak, Bu?”
“Cukup, Bu, lengkap banget.”
“Kalau kurang bilang ya.”
Retno datang belakangan. Begitu ia melangkah masuk, ritme ruangan seperti bergeser satu ketukan. Kursi khusus sudah menunggunya, strategis dan mencolok.
“Oh, Bu Gofur datang,” kata seseorang agak terlalu keras.
“Iya, Bu, sini duduk. Ini memang disiapkan buat Bu Gofur,” sambung yang lain dengan senyum dilebihkan.
Retno membalas dengan anggukan kecil. “Maaf telat, tadi ada sedikit urusan.”
Tasnya sederhana. Justru itu yang membuat beberapa mata tertahan lebih lama. Nama suaminya, dari lingkungan Departemen Agama, melayang-layang tanpa perlu disebut.
“Pak Gofur sehat, Bu?” tanya Bu Vita ramah.
“Alhamdulillah,” jawab Retno singkat.
Percakapan di sekitarnya menyesuaikan arah, topik-topik kecil mendadak digeser ke arah yang lebih “aman”. Tanpa diumumkan, semua paham: arisan hari itu bukan sekadar undian, tapi panggung kecil tempat status dan cerita saling berkilau.
Setelah pengocokan selesai, tepuk tangan menggema.
“Alhamdulillah, rezekinya lancar,” seru seseorang.
“Wah, giliran saya masih lama ya,” sahut yang lain setengah mengeluh, setengah berharap.
Beberapa ibu langsung meraih ponsel.
“Foto dulu, dong.”
“Kirim ke grup ya.”
“Biar update.”
Makan siang datang seperti aba-aba tak tertulis. Para ibu bergerak membentuk gerombolan-gerombolan kecil.
“Eh kita sini aja.”
“Jangan situ, penuh.”
“Ayo gabung.”
Meja makan panjang berubah jadi peta sosial.
Di satu sisi, tawa meledak-ledak.
“Dokter itu mahal, tapi hasilnya kelihatan.”
“Skincare ini katanya dipakai artis, lho.”
“Ih, artis yang mana? Aku nggak kenal.”
Di sisi lain, suara lebih rendah tapi tajam.
“Katanya sih…”
“Ya, tapi jangan bilang-bilang.”
Retno memilih duduk bersama empat ibu senior di pojok dekat jendela.
“Ambil sedikit aja ya, Tante,” kata Bu Ida.
“Iya, Bu,” jawab Retno sambil tersenyum.
“Harga tanah sekarang aneh,” ujar Bu Lela sambil mengaduk sup.
“Naiknya cepat banget, nggak jelas sebabnya.”
“Namanya juga sekarang,” sahut yang lain.
“Anak bungsuku tuh,” lanjut Bu Ida, “terlalu pintar. Malah susah dapat jodoh.”
“Waduh, kebanyakan mikir kali,” timpal Bu Lela.
Tawa kecil terdengar, lalu obrolan meloncat lagi.
“Rumah dinas lama itu masih sering ‘ngingetin’,” kata Bu Ida, suaranya diturunkan.
“Masa sih?”
“Serius. Penghuninya suka dengar suara langkah.”
Retno ikut mencondongkan badan, meski wajahnya tetap netral. Ia lebih banyak mengangguk, tertawa kecil di tempat yang dirasa tepat, tangannya sibuk dengan sendok dan air putih. Ia merasa seperti tamu di negeri asing—paham bahasanya, tapi belum berani bercakap bebas.
Lalu suasana berubah.
Bu Ida mencondongkan badan lebih jauh. “Ngomong-ngomong soal keluarga harmonis,” katanya pelan, “kalian dengar kabar Bu Vivin?” Ngocoks.com
Nama itu jatuh ke meja.
Retno membeku sejenak.
“Bu Vivin? Yang selalu bareng Pak Martin?” tanya seseorang.
“Iya,” jawab Bu Lela cepat. “Katanya sudah masuk gugatan cerai.”
Sendok Retno berhenti di udara.
“Loh, kenapa?”
“Pak Martin itu, katanya sudah loyo,” bisik Bu Lela.
“Bukan cuma capek, benar-benar… ya gitu deh.”
Nada suara mereka campur aduk antara iba dan rasa ingin tahu.
“Yang bikin heboh,” Bu Ida menutup mulut dengan punggung tangan, “Bu Vivin sekarang malah ketagihan… mainan dildo yang dipesan online itu.”
Waktu seperti tersandung. Retno terbatuk kecil. “Uhuk….maaf,” katanya cepat sambil meraih air. Dadanya berdebar tidak sopan.
Para ibu saling pandang. Ada yang menggeleng pelan, ada pula yang mengangkat alis tinggi-tinggi.
“Zaman sekarang ya, aneh-aneh saja padahal mereka kan udah sepuh, Bu Vivin udah mau 55 kan?” gumam seseorang.
“Kasihan juga sebenarnya.”
Retno menunduk, berpura-pura sibuk dengan mangkuknya. Ia tak tahu mana yang lebih mengejutkan: kabar itu sendiri, atau betapa mudahnya cerita sebesar itu diucapkan di meja makan yang masih berbau kuah kaldu.
Arisan bubar tanpa penutup resmi.
“Duluan ya, Bu.”
“Iya, hati-hati.”
“Nanti kita WA-an lagi.”
Para ibu pulang bergelombang. Ada yang masih tertawa di teras, ada yang sudah berbisik di balik pintu mobil. Rumah Bu Vita kembali rapi, tapi sisa-sisa cerita tertinggal di udara, lengket, dan sulit diusir.
Di rumahnya, Retno duduk sendirian lebih lama dari biasanya. Tas arisan masih tergeletak di kursi, belum ia sentuh. Kepalanya penuh. Gosip tentang Bu Vivin berputar-putar tanpa izin, terlalu jelas, terlalu dekat. Setiap potongan cerita terasa seperti cermin buram yang memantulkan sesuatu dari hidupnya sendiri.
Ia menarik napas panjang. Apa yang dialami Bu Vivin, hampir saja menjadi kisahnya. Atau mungkin, sebagian darinya sedang ia jalani. Ingatannya melayang pada sebuah hadiah dari suaminya dulu, diberikan dengan niat baik, mungkin juga dengan rasa bersalah yang tak diucapkan. Benda itu sempat mengisi ruang sunyi yang tak pernah benar-benar ia akui. Nyaris membuatnya lupa diri. Nyaris.
Ia bersyukur sudah membuangnya. Benar-benar membuang dan membakarnya, tanpa menoleh lagi yang tersisa hanya abu. Namun rasa waswas itu tetap ada, tipis tapi tajam, seperti benang halus yang menjerat pikiran. Ia takut pada dirinya sendiri, pada kemungkinan tergoda kembali. Terlebih kini, ketika usia suaminya semakin sepuh, jarak yang dulu hanya samar terasa kian nyata.
Retno menatap ruang tamu yang hening. Tidak ada gosip di sana, tidak ada bisik-bisik, hanya detak jam dinding yang jujur dan tak peduli. Ia menyadari satu hal yang membuat dadanya menghangat sekaligus ciut. Bebas dari benda itu bukan akhir cerita.
Justru mungkin awal dari kewaspadaan baru. Dan di balik ketenangan sore itu, Retno tahu, godaan tak selalu datang dengan wajah asing. Kadang, ia datang membawa nama orang lain, lewat gosip di meja makan, dan menetap diam-diam di hati.
Yang paling membuat Retno heran, sekaligus takut, justru bukan isi gosip itu sendiri, melainkan jalurnya. Bagaimana sesuatu yang sedemikian pribadi, sedemikian tertutup, bisa mengalir mulus dari ruang tidur seseorang hingga mendarat rapi di meja arisan ibu-ibu kompleks. Tanpa tersangkut. Tanpa rem. Seolah dinding rumah tak pernah benar-benar ada.
Ia memejamkan mata, mencoba menelusuri kemungkinan-kemungkinan yang membuat tengkuknya meremang. Apakah dari asisten rumah tangga yang terlalu lama tinggal lalu terlalu banyak bercerita. Atau dari sopir yang menunggu terlalu sabar di garasi sambil mendengar pertengkaran yang tak sengaja bocor.
Bisa juga dari sahabat yang awalnya hanya tempat curhat, lalu satu kalimat itu terlepas, berpindah mulut, membelah diri, beranak-pinak, sampai akhirnya tiba dalam versi yang lebih berani, lebih liar.
Retno menggigit bibir. Di lingkungan ini, reputasi berjalan lebih cepat daripada kebenaran. Yang privat tidak benar-benar privat. Yang rahasia hanya menunggu waktu untuk menemukan panggungnya. Dan ia sadar, gosip Bu Vivin bukan sekadar cerita orang lain. Itu peringatan sunyi. Bahwa hidup yang tampak rapi dari luar bisa saja berlubang di dalam, dan lubang itu, entah bagaimana caranya, selalu berhasil ditemukan orang lain.
Ia menatap sekeliling rumahnya sendiri. Dinding-dindingnya terasa lebih tipis dari biasanya. Retno mendadak berhati-hati pada siapa pun yang pernah ia ajak bicara terlalu jujur, pada kalimat-kalimat yang mungkin dulu ia ucapkan tanpa beban. Ketakutannya kini bergeser. Bukan hanya takut tergoda lagi, tetapi takut suatu hari namanya disebut dalam gosip serupa.
Gosip Bu Vivin tak berhenti di arisan. Ia bocor ke warung, ke kerumunan tukang sayur, diucapkan sambil tertawa ringan seolah tak membawa beban. Retno mendengarnya sekilas demi sekilas, dan setiap kali dadanya mengencang.
Ia mulai menarik diri, rapi dan pelan. Pergaulan dipersempit hanya pada kegiatan resmi kemasyarakatan. Undangan kecil dihindari. Bahkan senam bersama ia tinggalkan, memilih bergerak sendiri di belakang rumah, ditemani tembok dan jemuran.
Namun ketakutannya tak menyusut. Justru mengental. Semakin gosip itu beredar, semakin Retno merasa cerita itu bukan tentang Bu Vivin. Terlalu dekat. Terlalu pas. Seolah gosip itu hanya menumpang nama orang lain, menunggu waktu untuk menyebut namanya sendiri.
Bersambung…