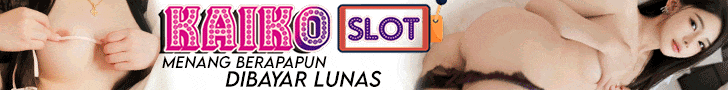Retno duduk sendirian di taman belakang rumahnya. Angin malam mengusap kulitnya pelan, daun jambu bergerak lirih seolah ikut menghela napas panjang bersamanya. Daster tipis yang ia kenakan bergerak ringan terkena angin, jauh dari pakaian yang biasa ia pakai saat di luar rumah atau di acara-acara kantor suaminya.
Di kursi rotan itu, di halaman belakang… ia bisa jadi dirinya sendiri, tanpa topeng, tanpa tuntutan. Ia menatap langit yang bertabur bintang. Dari luar, hidupnya tampak lengkap. Tapi dari dalam… ada kekosongan yang menggigit. Ia mengusap lengan sendiri, berdesir perasaan yang tidak punya nama: campuran kesepian, lelah, dan semacam rindu yang bahkan ia sendiri tak tahu ditujukan untuk siapa.
Di tengah keheningan itu, terdengar suara ranting kecil patah dari arah samping, cukup membuyarkan lamunannya. Retno menoleh. Dari balik pagar tanaman, muncul sosok Egar, pemuda tetangga yang baru pulang main. Egar berusia 20an, tampak setengah lelah, setengah kaget melihat Retno duduk sendirian di luar.
“Oh… malem, Tante,” sapanya pelan sambil mengangguk.
Retno tersenyum tipis. “Malam juga, Gar. Baru pulang kerja?”
“Hmm… iya, Tante ada lembur dikit.” Egar hendak masuk, tapi langkahnya berhenti. Ia menatap Retno sebentar, sekadar satu detik terlalu lama dibanding biasanya.
Retno menegakkan duduknya. Ada sesuatu dalam cara pemuda itu menatapnya. Bukan kurang ajar, bukan iseng, tapi mungkin agak kaget dengan pakaiannya. Sebuah perhatian khusus yang sudah lama tidak Retno terima dari siapa pun.
“Tante nggak kedingina? Dingin loh malam ini?” tanya Egar hati-hati.
Retno mengulas senyum kecil, lembut tapi letih. “Lagi butuh angin segar, sebentar.”
“Pak Haji belum pulang ya, Tante.”
“Biasa dinas luar, Gar.”
Egar mengangguk. Ia tampak ragu, tapi akhirnya berkata, “Kalau Tante… butuh teman duduk sebentar, aku bisa temenin, kok.” Ada jeda lima detik. Lima detik di mana Retno merasa dadanya terasa hangat aneh. Bukan menggoda, tapi hangat… dihargai. Lantas dia menepuk bangku di sebelahnya.
“Sini temenin Tante. Anginnya enak, Gar.” Egar mendekat pelan, duduk dengan sopan, menjaga jarak. Tapi kehadirannya saja sudah cukup untuk mengubah suasana.
“Gimana, Tan… hari ini capek?” tanya Egar, ragu-ragu. Retno menatap gelap taman. “Capek… tapi bukan capek badan.”
“Capek hati?” tanya Egar pelan, tapi tepat sasaran.
Retno terkesiap sedikit. Lalu menarik napas panjang, melepaskan beban. “Kamu tahu, Gar…” ucapnya lirih, “rumah ini besar. Tapi kadang rasanya… sesempit-sesempitnya ruang.”
Egar menunduk, suaranya rendah. “Sepi itu gitu, Tan. Kalau datang, nggak lihat umur, nggak lihat rumah, nggak lihat siapa kita.”
Perkataan sederhana itu mengenai di hati Retno. Ia tersenyum getir. Senyum seseorang yang akhirnya ada yang mendengar. “Kamu kok bisa ngomong gitu, Gar?”
Egar mengangkat pundaknya. “Ya… soalnya aku sering sepi juga, Tan.”
Egar terdiam sejenak, lalu menoleh lagi, ragu namun jujur. “Tante… boleh aku nanya sesuatu nggak?”
Retno menoleh, mengangguk pelan. “Nanya apa?”
“Sudah lama sekali, aku ngerasa Tante itu… kayak menarik diri,” katanya memilih kata dengan hati-hati, seolah berjalan di lantai licin. “Maksudku, Tante jarang kelihatan ikut kumpul, jarang keluar, kayak selalu jaga jarak dengan semua warga. Maaf ya kalau salah.”
Retno memejamkan mata sesaat. Pertanyaan itu seperti mengetuk pintu yang sudah lama ia ganjal dengan kursi dari dalam. Ia menarik napas panjang, terasa berat di dada.
“Bukan salah,” katanya pelan. “Kamu nggak salah lihat.” Ia menatap tangannya sendiri. “Tante capek, Gar. Capek harus selalu hati-hati. Capek mikirin omongan orang. Capek nimbang-nimbang mana yang pantas, mana yang bisa bikin salah paham.”
Retno tersenyum kecil, senyum yang lebih mirip kelelahan daripada bahagia. “Lama-lama… Tante belajar membatasi. Bukan karena mau, tapi karena takut. Takut dibilang macam-macam. Takut nyusahin suami. Takut jadi bahan cerita yang berputar-putar di belakang.”
Ia menelan ludah. “Dan tanpa sadar, batas itu makin sempit. Sampai akhirnya Tante sendiri yang terkurung.”
Egar mendengarkan tanpa menyela. Matanya tidak menghakimi, hanya penuh perhatian. “Berat ya, Tan,” katanya lirih. Ngocoks.com
Retno mengangguk. “Kadang Tante kangen versi diri Tante yang dulu. Yang bisa ketawa keras, yang nggak kebanyakan mikir. Tapi sekarang… rasanya harus selalu rapi, selalu benar. Kalau sendirian begini baru Tante berani bernapas.”
Malam semakin larut dan Retno merasa… tidak sendirian. Angin malam makin pelan, seperti ikut mendengarkan percakapan dua manusia yang jarang benar-benar didengar.
“Gar…” katanya perlahan, “Tante ini kadang merasa… gagal jadi ibu.”
Egar menoleh sedikit. “Kenapa ngomong gitu, Tan?” Retno menarik napas panjang. “Karena anak-anak Tante ikut ayahnya. Orang bilang ibu itu tempat pulang… tapi dua anak Tante pulangnya bukan ke sini, ke ayahnya. Sementara anak-anak Pak Haji juga pulangnya gak ke sini,” ucapnya diikuti tawa sumbang.
“Kadang Tante iri sama ibu yang bisa bangun pagi lihat anaknya sarapan. Kangen suara berantem kecil di rumah. Rumah besar gini… kok sunyi banget, Gar.”
Egar tidak buru-buru menjawab. Dari samping, wajah pemuda itu terlihat lembut, jauh dari kesan cuek yang sering muncul ketika ia mengobrol dengan teman-teman seusianya.
“Tante…” ucapnya hati-hati, “Tante bukan gagal. Kadang hidup… ya muter aja gitu. Ada yang kita mau, tapi nggak bisa kita pegang.”
Retno menatap matanya. Ada sesuatu di tatapan Egar, ketulusan yang membuatnya merasa lebih ringan. “Terima kasih ya… kamu ngomongnya selalu pas.”
Egar tersenyum kecil. “Aku cuma ngomong apa yang aku lihat, Tan. Dan yang aku lihat… Tante tuh orang baik.”
Retno menunduk. Ucapan sederhana itu terasa seperti obat.
“Aku ini, Tan… nggak pernah tahu siapa ibu kandungku.” Retno refleks menoleh.
“Ibuku katanya orang Banglades, aku dilahirkan ketika ayah menjadi TKI di Malaysia,” lanjutnya, “Katanya sempat nikah sama ibuku itu. Tapi ya gitu… nggak pernah jelas. Nggak ada dokumen apa-apa. Waktu aku lahir, dia lamgsung ninggalin ayah karena gak mau dibawa ke Indonesia.”
Egar menarik napas kecil. Tangannya meremas ujung celananya, gugup tapi jujur.
“Aku tumbuh sama ayah dan istri barunya. Ibu tiriku baik sih… tapi ya tetap aja… beda. Ada tembok yang nggak bisa ditembus. Kadang aku bantu mereka jaga toko di pasar kalau bengkel lagi sepi.”
Egar menunduk, tersenyum miris. “Orang-orang suka nanya aku orang India mana. Padahal ya… aku sendiri nggak tahu sebenarnya aku ini siapa.”
Retno merasakan sesuatu bergerak halus di dadanya, bukan iba, tapi semacam rasa ingin merangkul seseorang yang sudah terlalu lama bertahan sendirian dan merindukan ibunya.
“Gar…” katanya pelan, “kamu nggak harus ketawa waktu cerita hal kayak gitu.”
Egar menatapnya sebentar, mata hitamnya jujur. “Kalau aku nggak ketawa, aku pasti nangis, Tan,” katanya ringan namun menyayat. Retno terdiam.
Hening yang jatuh di antara mereka bukan hening asing, lebih seperti dua jiwa yang sama-sama membuka pintu kecil di hatinya dan menemukan seseorang di seberang sana sedang melakukan hal yang sama. Ia mengulurkan tangan, menyentuh punggung tangan Egar sebentar, singkat, sopan, tidak berlebihan, sebuah sentuhan yang lebih seperti “aku dengar kamu” daripada apa pun.
“Kamu kuat, Gar,” katanya. “Dan kamu berhak bahagia.” Pemuda itu tersenyum lebih dalam, kali ini tanpa getir.
“Tante juga.” balas Egar.
Untuk pertama kalinya malam itu, keduanya sama-sama merasa tidak sedang berada di dunia yang melawan mereka. Untuk satu momen kecil, yang tersisa hanyalah kehangatan dua manusia yang saling memahami tanpa perlu membuktikan apa-apa.
Percakapan mereka akhirnya mereda ketika jarum jam sudah melewati angka sepuluh. Angin mulai menusuk kulit, dan lampu-lampu rumah tetangga satu per satu padam. Egar menghela napas pelan, lalu berdiri sambil mengambil tas kecilnya.
“Tan, aku balik dulu ya. Besok subuh harus ke pasar dulu, bantu ayah,” katanya sambil tersenyum.
Retno ikut berdiri, meski sebagian hatinya terasa berat. “Iya, Gar. Hati-hati ya.”
“Terima kasih, Tan.” Ia melangkah pergi melalui jalan samping yang memisahkan halaman rumah mereka. Sesekali ia menoleh sekilas sambil tersenyum canggung… lalu menghilang ke arah rumah orang tuanya.
Orang memanggilnya Bu Gofur, Bu Haji, Bu Retno. Tapi yang paling sering dan paling pas di telinganya tetap ‘Tante Retno.’ Ia bahkan suka geli sendiri kalau ada yang memanggilnya ‘Bu Haji’ karena yang berhaji sebenarnya hanya suaminya, jauh sebelum menikah dengannya. Hidup Retno sendiri bukan jalan lurus.
Di usia 35, ia sudah dua kali menjadi pengantin. Pernikahan pertamanya memberinya dua anak sekaligus luka yang tak singkat, suaminya tak pernah bisa setia. Ketika akhirnya berpisah, anak-anak ikut ayahnya karena kondisi ekonomi. Itu bagian paling menyakitkan yang masih terasa sampai sekarang.
Setahun setelah perceraian, ia menikah dengan Haji Gofur, duda 60 tahun dengan empat anak: Ghea, Ganjar, Gerald, dan Gifar. Hanya Gerald yang benar-benar dekat dengannya, bahkan memanggilnya ‘Mama’; sisanya sopan, tapi tetap menjaga jarak, memanggilnya pun ‘Tante.’
Retno bukan perempuan yang terlalu taat dalam beragama, tapi setelah menjadi istri Haji Gofur, ia belajar menyesuaikan diri demi menjaga kehormatan suaminya yang dihormati kolega di Departemen Agama. Hidupnya kini tenang, stabil, dan berkecukupan, sesuatu yang dulu tak pernah ia rasakan. Namun di balik ketenangan itu, ada ruang kosong yang semakin terasa.
Ia berusaha maklum; ia merasa tak pantas menuntut apa-apa lagi. Tapi kebutuhan batin tetap ada, dan semakin hari semakin sulit ia abaikan. Suaminya pun jujur soal kelemahannya, bahkan pernah melontarkan candaan getir tentang dirinya mencari “pelampiasan” asalkan ia tahu.
Kalimat itu justru terasa seperti jebakan, bukan izin.
Bagi Retno, kesetiaan adalah harga diri. Apalagi sebagai istri seorang tokoh bergelar Haji, ia tak mau jadi bahan omongan orang sekompleks atau sekantor suaminya.
Dan begitulah keseharian Retno, hidup di rumah besar yang serba cukup, tapi di dalam dirinya ada kesunyian yang sulit ia isi, sebuah kekosongan yang terus menggaung, tak peduli seberapa keras ia mencoba menahannya.
Bersambung…