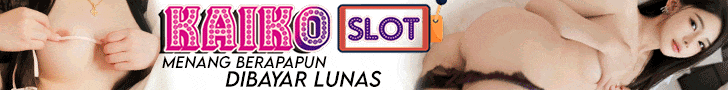Sisa hujan masih membekas di aspal, genangan air ada di mana-mana. Jam sudah bergeser dua puluh menit dari angka dua belas, tapi berbagai jenis kendaraan masih memadati jalanan. Saat mobil berhenti di lampu merah, Ceysa melihat Vale senyam-senyum tidak jelas.
“Kamu kenapa?” tanya Ceysa dengan alis bertaut. Ekspresi Vale ini sangat menggemaskan, mengundang rasa penasaran.
“Aku lagi seneng banget,” sahut Vale.
“Karena?” Ceysa masih menatap Vale lekat. Dari samping, kenapa pria itu makin tampan? Hidungnya mancung, bulu matanya panjang, bibirnya … sangat cipokable.
“Malam ini pacar aku keren banget.” Vale mencium punggung tangan Ceysa berkali-kali sebagai ungkapan rasa gemasnya. “Aku puas banget lihat ekspresi mereka tadi. Dua kali ditampar oleh kenyataan, pasti rasanya sakit banget.”
“Dua kali?”
“Pertama, pas mereka tau kamu pacar aku. Padahal Aldo udah pede banget ngajak kamu kenalan.” Vale tertawa.
“Sok ganteng tuh orang,” cibir Ceysa. “Eh, emang kamu tau tadi dia deketin aku?”
“Tau lah. Aku lihat semuanya dari CCTV. Aku hampir aja nyamperin dia dan nonjok mukanya andai kamu merespons. Tapi pacar aku yang cantik ini udah permaluin si songong itu tanpa harus capek-capek buang tenaga.” Vale riang gembira.
“Pede banget mau ngedeketin aku, muka udah pas-pasan, kelakuan minus.” Ceysa berdecak sembari menggeleng.
Vale terbahak. “Kalau yang kayak Aldo kamu bilang pas-pasan, berarti aku ganteng banget ya?” tanyanya begitu percaya diri.
Ceysa mencebik, namun akhirnya tertawa. Dia tidak perlu menjawab, Vale pasti tahu standarnya untuk tipe seorang laki-laki. Saat prinsipnya soal usia saja telah dilanggar, itu artinya Vale lebih dari sekadar ganteng.
“Terus yang kedua?” tanya Ceysa lagi.
“Pas kamu bayarin pesanan mereka atas nama aku, itu pecah banget. Aku berasa lihat kesombongan mereka tuh runtuh,” ucap Vale antusias. “Aku aja sampai kaget tau nggak pas denger, apalagi mereka coba?”
Ceysa tersenyum tipis dan mengangguk.
“Tapi Cey, kamu ngapain sih bayarin mereka segala? Habisin uang aja, kan mahal,” protes Vale. Dia rasanya tidak rela Ceysa mengeluarkan uang sebanyak itu hanya untuk mengenyangkan kelima orang tadi.
“Kita butuh uang untuk menampar mulut sampah seseorang. Dengan begitu mereka nggak akan mandang rendah kamu lagi. Sumpah, aku nggak suka mereka bersikap gitu ke kamu tadi.” Bila ingat, Ceysa ingin menampar kelima pemuda itu satu persatu rasanya.
Vale menciumi tangan Ceysa kembali. “Makasih ya, berkat kamu harga diri aku terselamatkan,” kekehnya.
“Iya, sama-sama.” Ceysa tersenyum. Gantian dia yang mencium punggung tangan Vale. “Emm, bau …”
“Masa?” Vale menarik tangannya dan menciumnya. Melihat Ceysa tertawa, dia pun tahu sudah dibohongi. “Sini, aku kasih yang bau beneran.”
Ceysa menjerit disertai tawa saat Vale mengapit kepalanya ke bawah ketiak pria itu. Tidak bau sama sekali, malah aroma maskulinnya sangat enak. Dia mendongak, Vale mencium bibirnya.
Saat sedang becanda seperti itu, perut Ceysa tiba-tiba diserang nyeri yang begitu hebat. Dia refleks menekannya sembari setengah membungkuk.
“Kenapa?” tanya Vale cemas. Dia harus membagi fokusnya antara jalan dan Ceysa.
“Perut aku sakit banget,” rintih Ceysa.
Saat menemukan celah, Vale langsung menepikan mobil. Dia ikut memegang perut wanita itu, “mau dapet?”
Ceysa menggeleng.
Vale makin cemas saat melihat wajah Ceysa begitu pucat. “Kita ke rumah sakit,” ucapnya yang langsung menjalankan mobil kembali.
Ceysa sebenarnya anti dengan rumah sakit, tapi kali ini sakitnya tidak bisa dia tahan lagi. Tak hanya perut, tapi ulu hati hingga dadanya pun terasa panas dan nyeri.
“Tahan ya, kita hampir sampe,” ujar Vale sembari menambah kecepatan.
Sesampainya di depan pintu IGD, Vale bergegas turun. Dia membuka pintu di sebelah Ceysa, membantu wanita itu turun. Melihat Ceysa makin lemah dia pun menggendongnya ke dalam.
“Dokter! Suster!” panggil Vale dengan wajah panik.
Seorang perawat langsung mendekati dan memberikan arahan pada Vale untuk membaringkan Ceysa ke salah satu ranjang kosong. Tirai pun ditutup mengelilingi ranjang itu, dan seorang dokter datang untuk memeriksa.
“Keluhannya apa, Mbak?” tanya dokter itu.
“Perut saya rasanya melilit, dok. Terus dada juga nyeri sampai panas ke tenggorokan,” beritahu Ceysa dengan suara yang mulai serak.
“Saya periksa dulu ya.”
Vale menunggu dengan cemas, sambil mengusap kening Ceysa yang banjir oleh keringat. Melihat kekasihnya itu kesakitan, hatinya bagai diremas.
“Mbak punya riwayat mag kronis?” Dokter menekan ulu hati Ceysa dan melihat wanita itu meringis.
“Iya, dok.” Ceysa mengakuinya.
“Sekarang lagi sesak napas?”
“Sedikit, dok.” Dada Ceysa turun naik akibat rasa sesak yang dideritanya.
“Sepertinya ini gejala gerd,” beritahu dokter itu setelah memeriksa secara menyeluruh.
“Gerd, dok?” ulang Vale.
Dokter mengangguk. “Asam lambung yang naik ke kerongkongan, memang biasanya akan terasa panas seperti terbakar di dada. Bila terus menerus terjadi, maka akan berdampak buruk bagi kesehatan,” jelasnya.
“Biasanya dikarenakan apa ya, dok?” tanya Vale.
“Makan tidak teratur dan minum kopi secara berlebihan bisa jadi faktor dari naiknya asam lambung.”
Vale sontak menatap Ceysa, terkesan menyalahkannya. “Dia emang sering telat makan siang, ditambah minum kopi berlebihan dok,” beritahunya.
Dokter menyuruh perawat memberi beberapa obat pada Ceysa untuk meredakan nyeri. “Kita pasang infus ya, nginap dulu beberapa hari,” ujarnya.
“Opname, dok?” Ceysa tersentak. Dia hendak menolak, tapi Vale dengan tegas berkata, “baik, dok.”
“Aku nggak mau di-opname,” minta Ceysa pada Vale.
“Kamu harus ikuti anjuran dokter,” paksa Vale, tidak bisa negosiasi lagi.
“Baik kalau begitu saya permisi dulu.”
“Makasih, dok.”
“Mas, bisa dibantu untuk administrasi rawat inapnya dulu?” ajak seorang perawat.
“Kamu tunggu ya,” ucap Vale dengan lembut. Lalu dia mengikuti perawat itu.
Ceysa benar-benar pasrah kali ini.
***
Ceysa tidak bisa tidur, suasana rumah sakit masih tidak nyaman untuknya. Meski Vale menjaganya di sana, tetap saja ada rasa takut yang mengganggu. Ingatan tentang bagaimana Mamanya dulu meninggal, menghantui pikiran. Dia pun memilih untuk duduk.
“Kamu kenapa belum tidur?” tanya Vale. Dia mengusap puncak kepala Ceysa dengan lembut.
“Aku nggak pernah bisa tidur kalau di rumah sakit gini,” jujur Ceysa.
“Ada yang ganggu pikiran kamu?”
“Cuma … ada sedikit trauma di masa lalu aja,” jawabnya.
“Aku boleh tau detailnya?” tanya Vale, namun tidak terkesan memaksa.
“Dulu, waktu aku masih empat belas tahun, Mami didiagnosis terkena usus buntu dan harus di-operasi. Menurut dokter itu operasi sederhana, nggak berbahaya sama sekali. Aku sendirian nungguin di depan ruang operasinya, karena Papi nggak bisa dihubungi. Aku nunggu sampe dua jam, padahal dokter bilang cuma tiga puluh menit.” Ceysa memberi jeda agar kenangan buruk itu tidak membuatnya sesak.
Vale mengusap lengan Ceysa, dengan sabar menunggu kelanjutannya.
“Setelah tiga jam nunggu, operasi pun selesai. Aku seneng banget. tapi pas dokter ke luar, terus bilang Mami udah meninggal, dunia aku rasanya bener-bener hancur. Aku langsung lari ke dalem, terus lihat Mami udah ditutupin kain putih. Mukanya pucet banget, nggak bergerak …”
“Udah … Udah nggak usah dilanjutin.” Vale mengusap air mata Ceysa yang jatuh. Hatinya ikut tersayat.
“Dokter bilang itu cuma operasi yang sederhana, nggak perlu anestesi total karena diameternya kecil. Tapi yang aku heran kenapa Mami bisa meninggal?” Ceysa sedikit emosi. Dia bagai berada di hari itu kembali dan menyaksikan maminya terbujur. “Lantaran dianggap masih kecil, jadi dokter nggak ngejelasin apapun mengenai kondisi Mami. Aku marah, tapi nggak punya kekuatan apa-apa.”
Vale langsung memeluk Ceysa.
“Mami masih baik-baik aja sebelum ke rumah sakit, Val. Mami bahkan nggak ngeluh sakit berlebihan. Mami masih ngajak aku becanda di mobil, terus bilang kalau udah sembuh kita bakalan makan ice cream sepuasnya. Tapi kenapa Mami nggak bangun lagi setelah itu …” Ceysa menangis dengan keras. Tubuhnya bergetar hebat.
Vale tidak mengatakan sepatah kata pun, karena dia tahu seseorang dalam kondisi seperti ini tidak membutuhkan kata-kata manis yang hanya bertujuan untuk menghibur. Ceysa lebih membutuhkan pelukan, sebagai ungkapan kalau Vale sangat mengerti apa yang dirasakannya.
Setelah puas menangis dan lebih tenang, Ceysa akhirnya tertidur juga. Vale menatap wanita itu tanpa sedetik pun berpaling. Ceysa yang selama ini selalu kuat, dingin dan seperti tidak punya hati, tapi ternyata menyimpan banyak luka di hatinya.
“Aku nggak akan ninggalin kamu. Aku bakal selalu di samping kamu dalam keadaan apapun,” janjinya sembari mengusap kepala Ceysa.
Vale membungkuk, lalu mencium kening Ceysa. “I love you, Cey. Until my breath stops,” bisiknya.
“Selamat pagi.”
Vale terbangun saat seorang perawat datang dan menyapa dengan lembut. Dia meregangkan tubuhnya, terasa pegal semua akibat terlalu lama tidur dengan posisi duduk. Matanya masih mengantuk, namun tidak mungkin untuk tidur lagi. Melihat Ceysa masih tidur, dia pun pergi ke kamar mandi untuk mencuci muka.
Ceysa juga terbangun saat perawat itu menyentuh tangannya. Ditolehnya ke samping, Vale tidak ada. “Sus, tadi ada temen saya di sini?” tanyanya.
“Ada Mbak, lagi ke kamar mandi,” jawab perawat itu sembari mengganti infus yang hampir habis dengan yang baru.
“Oh.” Ceysa mengangguk.
“Temen apa pacar, Mbak? Saya tebak pasti pacar, soalnya perhatian banget. Sampai tidurnya duduk loh padahal ada sofa di situ,” goda perawat itu.
“Suster bisa aja.” Ceysa terkekeh. Meski sedang mengobrol, Perawat itu tetap cekatan bekerja memeriksanya.
“Pacarnya ganteng banget Mbak, jadi idola suster-suster di sini,” beritahu perawat itu sembari cekikikan.
“Ah, masa sih Sus?” Ceysa tentu saja bangga, tapi tidak menunjukkannya.
“Beneran, Mbak. Ini aja mereka pada rebutan pengen dapet jaga di kamar ini.”
Ceysa tertawa mendengarnya.
Vale sudah ke luar dari kamar mandi, langsung mendekati Ceysa. “Good morning,” ucapnya yang kemudian mencium kening wanita itu. Tetesan di rambutnya membasahi pipi Ceysa, lantas diusapnya dengan lembut.
Ceysa melihat bagaimana perawat itu terpesona pada pacarnya. Vale, saat rambutnya sedang setengah basah seperti ini, damage-nya memang luar biasa.
“Saya mau ambil sample darah untuk dicek di lab ya Mbak.” izin perawat itu meminta izin lebih dulu.
Ceysa mengangguk dan menjawab semua pertanyaan dasar yang perawan itu tanyakan.
Perawat itu melakukan inspeksi pada fossa antecubiti, lengan bawah, dan tangan. Lalu mencari letak vena yang jelas, setelah itu memasang torniket. “Saya ambil darahnya ya Mbak,” ujar perawat itu dengan ramah.
“Iya, Sus.” Ceysa sebenarnya takut jarum, sehingga dia menghadapkan wajahnya ke dada Vale. Rasa dingin menyentuh kulitnya saat perawat itu melakukan asepsis dengan alcohol swab.
Ceysa meringis ketika jarum mulai menusuk kulitnya. Vale memeluknya dengan erat sembari berbisik, “nggak usah dirasain.”
“Gimana keadaan pacar saya, Sus?” tanya Vale.
“Untuk pemeriksaan dasar, semuanya normal. Untuk pemeriksaan secara menyeluruh nanti langsung sama dokternya, Mas. Sekalian dokternya juga yang akan menjelaskan hasil tes lab-nya.” jelasnya.
Vale mengangguk.
“Udah selesai ya Mbak,” ucap perawat itu sembari melepas torniket, menekan kapas pada area yang disuntik dan mencabut jarum. Ketiga tahap ini dilakukan sangat cepat, bahkan sudah selesai sebelum Ceysa menoleh.
Perawat itu memasang plester pada bekas suntikan. “Perutnya masih terasa sakit nggak, Mbak?” tanyanya.
“Udah nggak Sus,” jawab Ceysa.
“Baik kalau begitu, saya permisi dulu. Nanti jangan lupa sarapan, lalu obatnya diminum.”
“Iya Sus.”
“Makasih Sus,” ucap Vale.
Perawat itu tersipu, lalu mengangguk.
Tak lama setelah itu, petugas lainnya datang membawakan obat pagi Ceysa. “Obat yang ini diminum tiga puluh menit hingga satu jam sebelum sarapan. Sisanya diminum setelah sarapan. ”
“Terima kasih Sus,” ucap Vale.
“Permisi ya.”
Ceysa dan Vale mengangguk.
“Ayo makan obatnya dulu.” Vale lalu mengambilkan minum untuk Ceysa.
“Banyak banget,” keluh Ceysa begitu melihat berapa butir obat yang harus dia telan setelah makan nanti.
“Harus diminum semua kalau pengen sembuh,” tegas Vale. “Ayo diminum.”
Ceysa merapatkan mulutnya sambil menggeleng. “Aku nggak suka obat mag, bikin mual.” Dia bicara sambil menutupi mulut dengan tangan.
“Ini, kan, ada rasa mint. Sama kayak kita makan permen mint,” bujuk Vale. “Yuk, kalau nggak bisa dikunyah langsung telan aja.”
“Nggak suka tetep aja.” Ceysa tetap menggeleng. “Lagian perut aku udah nggak sakit, nggak perlu minum obat lagi.”
Vale mendesah, Ceysa bukan tipe yang bisa dipaksa. Dia pun menaruh gelas ke atas lemari. “Manja banget sih,” ucapnya sembari memindahkan anak rambut yang bertengger nakal di kening wanita itu.
Melihat Vale tidak memaksa, Ceysa pun menurunkan tangannya dari mulut. Dia tersenyum senang karena Vale begitu pengertian.
“Aku belum dapet morning kiss hari ini,” ucap Vale sembari mengusap bibir Ceysa.
Ceysa mulai berdebar.
Vale mendekati bibir Ceysa, mengecup dengan lembut. Wanita itu mulai memejamkan mata dan membalas. Hal ini dia manfaatkan untuk memasukkan obat yang tadi diam-diam disimpan di mulutnya ke mulut Ceysa.
Ceysa membuka matanya lebar-lebar. Vale berhasil membuatnya minum obat yang paling dibencinya itu. Dia mendorong pria itu. “Licik,” desisnya.
Vale terkekeh. Diberinya Ceysa minum agar segera menelan obat itu.
Ceysa dengan cepat meminum setengah gelas air untuk menghilangkan rasa mint dari obat itu. Sungguh, dia tidak suka rasanya. Orang-orang bilang rasanya sama seperti permen mint, tapi baginya sangat jauh berbeda.
“Sini, aku aku bikin kamu lupa sama rasa obatnya.” Vale mencium kembali bibir Ceysa, dan kali ini melumatnya dalam-dalam.
***
“Ehm!”
Vale dan Ceysa refleks memisahkan diri. Keduanya tengah bermesraan di ranjang rumah sakit yang kecil itu, saat Allura dan tiga lainnya datang.
“Ini kalian nggak lagi shooting bokep, kan?” tanya Onyx terang-terangan.
“Heh!” Ceysa melotot.
Semuanya tertawa.
“Habisnya enak banget bermesraan di rumah sakit,” sindir Onyx.
Vale turun dari ranjang, menggaruk kepalanya yang tidak gatal akibat malu. Padahal dia dan Ceysa tadi hanya berciuman, tapi memang tidak pantas karena ini rumah sakit.
Jevan dan Blaire yang pernah berada di posisi itu, memilih bungkam saja daripada kena juga. Dulu, mereka juga pernah berciuman saat Ceysa dirawat di rumah sakit.
“Cey, gue mau marah sama Lo!” tukas Allura setelahnya.
“Loh, kenapa?” tanya Ceysa bingung.
“Lo masuk rumah sakit tadi malem, tapi kenapa baru ngabarin sekarang? Jahat ya Lo jadi temen,” protes Allura.
“Bener.” Blaire ikutan.
“Bukannya nggak mau ngabarin, tapi gue masuknya udah tengah malem.” Ceysa membela diri. “Gue nggak mau bikin kalian panik terus buru-buru dateng.”
“Cey, mau jam berapapun kita nggak peduli, pokoknya lain kali kita harus dikabarin lebih dulu,” tegas Blaire.
“Iya-iya, maaf.”
“Lo juga Val, kenapa nggak nelepon kita-kita coba?” cecar Allura.
“Ceysa yang larang.” Vale menunjuk Ceysa, lebih baik cuci tangan daripada diomeli Allura.
Allura mendengkus, “Bilang aja kalian mau berduaan, jadi sengaja nggak ngabarin biar nggak keganggu, kan?”
Blaire dan dua lainnya tertawa geli.
“Enak aja,” tepis Ceysa.
Vale menggaruk kepalanya, bingung mau ngomong apa kalau Allura terus mengoceh.
“Val, kamu pulang dulu aja. Istirahat di rumah. Ada mereka yang jagain aku,” suruh Ceysa.
Vale benar-benar ragu meninggalkan Ceysa yang sedang sakit. Dia tidak peduli soal istirahat, tapi masalahnya ada pada pekerjaan yang tidak bisa libur begitu saja. Peraturan di cafe sangat ketat, libur tanpa alasan yang darurat bisa membuatnya kehilangan poin mempertahankan pekerjaannya.
“Iya Val, Lo pulang aja nggak papa. Kita bakal gantian jagain Ceysa, kok.” Allura ikut bicara, yang lain hanya mengangguk.
Vale pun mengangguk. Lebih dulu dia mendekati Ceysa. “Aku pulang bukan untuk istirahat, tapi kerja. Nanti aku ke sini lagi setelah selesai,” ucapnya.
“Kamu nggak libur aja? Tadi malem kurang tidur loh, nanti sakit kalau maksa kerja,” ucap Ceysa cemas.
“Nggak papa, aku masih kuat kok.” Vale tersenyum.
Ceysa tidak tega, tapi keputusan Vale tentu ada alasan. Sebagai bawahan, Vale punya tanggung jawab terhadap pekerjaannya. “Ya udah kalau gitu, tapi jangan terlalu diforsir. Kalau udah capek banget, kamu minta izin pulang aja. Kalau butuh bantuan aku buat ngomong sama Adam, kasih tau aja,” ucapnya.
“Iya.” Vale mengangguk. Dia mencium kening Ceysa dengan lembut. “Jangan nakal,” bisiknya.
“Ehm! Jangan bikin gue baper dong,” sindir Allura.
Vale terkekeh. “Guys, bantu gue jagain Ceysa dulu, ya? Tolong pastiin dia makan tepat waktu dan minum obatnya,” minta Vale sepenuh hati.
“Gampang,” sahut Onyx.
Vale menatap Ceysa cukup lama, ada keraguan yang menahannya untuk pergi. Namun akhirnya dia melangkah meninggalkan kamar itu.
“Lo kenapa bisa masuk rumah sakit sih Cey?” tanya Blaire sembari duduk di kursi samping ranjang.
“Gerd,” jawab Ceysa.
“Apa gue bilang, Lo itu terlalu gila kerja, Cey. Udah tau punya mag, malah selalu telat makan, sok diet, terus pasti kopinya gila-gilaan, kan?” omel Blaire.
“Sorry, gue lagi cuti sakit. Jadi, nggak nerima omelan,” cengir Ceysa.
Blaire dan Allura mendengkus.
“Gimana keadaan Lo sekarang?” tanya Jevan.
“Udah lebih enak,” jawab Blaire.
Onyx melihat arlojinya. “Berhubung cuma gue yang kuli di sini, sorry gue harus ke kantor sekarang,” pamitnya.
“Nanti sempetin ke sini ya, Sayang,” sahut Allura.
Onyx mengangguk. “Cey, cepet sembuh ya,” ucapnya buru-buru.
Ceysa mengangguk.
Bersambung…