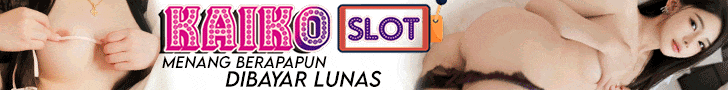TAWARAN MENDADAK
Pagi menyingsing di Pesantren Darul Hikmah dengan lembutnya, azan Subuh menggema dari masjid utama, membangunkan para santri dari tidur lelap mereka. Suara takbir yang samar-samar terdengar dari kejauhan, bercampur dengan hembusan angin pagi yang membawa aroma embun dan daun basah.
Alya terbangun dengan perasaan segar, meski bayangan malam sebelumnya masih menempel di benaknya – tatapan misterius para santri, senyum tipis Ustadzah Rani yang seolah menyimpan rahasia, dan aura Aula Serbaguna yang terasa seperti undangan halus ke dunia tak dikenal.
Ia bangun dari ranjang sederhana di kamarnya, menegakkan tubuh semampai yang masih terbungkus gamis tidur. Rambut hitam panjangnya tergerai sebentar sebelum ia ikat rapi di balik jilbab segar yang baru ia ambil dari koper.
Gerakannya lambat, penuh kehati-hatian – tangannya yang halus menyentuh kain sutra jilbabnya, menyesuaikannya hingga menutupi setiap lekuk tubuh idealnya dengan sempurna. Kulit putih bersihnya terasa dingin disentuh udara pagi, membuatnya menggigil samar.
“Alhamdulillah,” gumamnya pelan, sambil menatap cermin kecil di dinding kayu.
Wajah cantiknya memantul di balik cermin – sorot mata teduh yang polos, bibir tipis yang selalu tersenyum sopan, tapi hari ini ada kilatan penasaran yang tak bisa ia sembunyikan sepenuhnya.
Setelah wudhu singkat di kamar mandi, Alya melangkah keluar menuju masjid untuk sholat berjamaah. Lorong pesantren masih remang-remang, hanya diterangi lampu temaram yang bergantung di langit-langit.
Langkahnya ringan, tapi ia merasakan getaran halus di udara – seolah setiap dinding kayu itu menyimpan bisik-bisik tak terdengar.
Sesekali, ia bertemu beberapa santri yang bergegas ke masjid, tatapan mereka menyapa dengan anggukan sopan, tapi ada yang lebih – pandangan sekilas ke arah lekuk pinggangnya yang tersembunyi di balik gamis, atau senyum yang bertahan sedetik terlalu lama.
Alya menundukkan pandangan, hatinya berdegup sedikit lebih cepat. “Ini cuma perasaanku saja,” batinnya pada diri sendiri, tapi rasa penasaran itu justru tumbuh, seperti benih yang disiram embun pagi.
Di masjid, ia sholat di saf wanita, suara imam yang tegas membawa ketenangan sementara. Setelah sholat, Alya bergabung dengan Maya untuk sarapan di ruang makan santri perempuan. Meja-meja kayu panjang dipenuhi piring sederhana – nasi goreng hangat, telur rebus, dan teh manis yang mengepul. Maya duduk di sebelahnya, wajahnya ceria seperti biasa, rambutnya yang pendek terikat rapi di balik jilbab.
“Kak, tidurnya nyenyak? Kamarnya oke kan?” tanya Maya sambil menyendok nasi goreng, matanya berbinar.
Alya tersenyum, menuang teh ke cangkirnya. “Alhamdulillah, nyenyak kok. Cuma… suasananya agak bikin penasaran aja. Kayak ada yang beda dari pesantren biasa.”
Maya terkekeh pelan, suaranya riang tapi ada nada menggoda yang samar. “Ah, kakak emang terlalu serius. Nanti juga terbiasa. Malah, kakak bakal suka banget di sini. Banyak kegiatan seru, loh – terutama yang… rahasia.” Ia mengedipkan mata, tapi cepat menutupinya dengan suapan nasi.
Alya mengerutkan dahi, ingin bertanya lebih lanjut, tapi sebelum kata-katanya keluar, pintu ruang makan terbuka lebar. Seorang pria paruh baya masuk dengan langkah mantap, diikuti dua pengajar muda.
Itu Khalid Syaifuddin, ketua pen9urus pesantren yang Alya dengar dari Kyai Ahmad kemarin. Tubuhnya gemuk tapi berwibawa, gamis putihnya rapi, jenggotnya terpotong pendek, dan wajah ramahnya menyiratkan senyum yang terlalu lebar – seolah menyembunyikan gigi tajam di baliknya.
Di belakangnya, Ridwan Ahmad, 9uru muda berbadan atletis dengan kulit hitam manis, tatapannya liar seperti serigala yang mengintai mangsa. Dan yang ketiga, seorang pria tampan berusia sekitar 27 tahun, tinggi menjulang dengan tubuh atletis yang terlihat dari balik baju koko ketat – Dia Reza Pratama.
“Assalamu’alaikum, para santri dan pengajar,” sapa Khalid dengan suara menggelegar tapi hangat, matanya menyapu ruangan sebelum berhenti di Alya.
Tatapannya berlama-lama, menelusuri garis leher jilbabnya yang tertutup rapat, seolah bisa melihat lebih dalam. “Pagi yang indah, Alhamdulillah. Saya dengar ada tamu istimewa hari ini – Ibu Alya Ramadhani, lulusan berprestasi dari Kairo.”
Semua mata tertuju padanya. Alya merasa pipinya memanas, tapi ia bangkit sopan, membalas salam. “Wa’alaikumsalam, Pak Khalid. Alhamdulillah, terima kasih atas sambutannya.”
Khalid melangkah mendekat, tangannya terulur untuk bersalaman sopan – hanya sentuhan jari, tapi Alya merasakan kehangatan yang aneh, seperti arus listrik kecil yang membuat telapak tangannya bergetar.
“Sungguh beruntung kami bisa menyambut putri hebat seperti Ibu Alya. Kami sudah mendengar banyak tentang pendidikan Ibu di Al-Azhar – tafsir mendalam, hadis shahih, dan pengajaran akhlak yang luar biasa. Pesantren kami butuh orang seperti Ibu.”
Alya tersenyum malu-malu, menarik tangannya pelan. “Ah, jangan terlalu dipuji, Pak. Saya hanya datang untuk menjenguk Maya. InsyaAllah, kalau ada kesempatan bermanfaat, saya siap membantu.”
Ridwan tersenyum lebar, tatapannya kentara sekali – langsung ke mata Alya, lalu turun sekilas ke lekuk dadanya yang tersembunyi. “Justru itu, Bu Alya. Kami sedang kekurangan pengajar untuk kelas Tafsir Lanjutan. Santri-santri kami haus akan ilmu mendalam seperti yang Ibu bawa dari Kairo. Satu atau dua sesi saja, ya? Mereka akan senang sekali diajari oleh akhwat secerdas Ibu.”
Reza, yang selama ini diam, akhirnya angkat bicara. Suaranya dalam, penuh pesona seperti madu yang mengalir lambat. Ngocoks.com
“Benar, Bu. Saya sendiri mengajar kelas Hadis di sini, tapi pengalaman Ibu di Mesir pasti lebih banyak. Bayangkan, santri-santri yang biasanya belajar dari buku lama, tiba-tiba diajari oleh seseorang yang pernah merasakan hembusan angin Nil sambil mengkaji Sahih Bukhari.”
Matanya bertemu dengan Alya, tatapan maskulinnya penuh gairah tersembunyi – seolah undangan untuk berbagi lebih dari sekadar ilmu. Tubuh atletisnya condong sedikit, membuat aroma maskulin samar tercium, bercampur bau sabun pagi yang segar.
Alya merasakan jantungnya berdegup lebih kencang. Ada sesuatu yang berbeda dalam cara Reza berbicara – berani, penuh pesona, seperti angin panas yang menyusup di balik jilbabnya.
“Saya… tersanjung, Ustadz. InsyaAllah, kalau jadwalnya memungkinkan, saya bisa isi satu kelas percobaan. Tapi saya takut belum familiar dengan kurikulum di sini.”
Khalid tertawa ringan, tangannya menepuk bahu Ridwan seperti isyarat. “Jangan khawatir, Bu Alya. Kami akan dampingi. Bahkan, Kyai Ahmad sudah setuju. Ini kesempatan bagus untuk Ibu berbagi ilmu – dan siapa tahu, Ibu malah betah ingin tinggal lebih lama.” Matanya berkedip, senyumnya melebar, seolah kata-kata itu punya makna ganda – ilmu di permukaan, tapi janji kenikmatan tersembunyi di baliknya.
Maya menyikut Alya pelan dari samping, bisiknya ceria. “Ayo, Kak. Pasti seru! Santri-santri bakal pada antusias, apalagi yang senior.”
Alya mengangguk ragu, tapi rasa tanggung jawabnya menang. “Baiklah, Pak Khalid. Saya setuju untuk mengajar kelas Tafsir. Semoga bermanfaat.”
Khalid mengangguk puas, matanya tak lepas dari Alya. “Alhamdulillah! Ridwan, tolong siapkan ruangannya. Dan Reza, kau dampingi Bu Alya nanti untuk diskusi materi.” Ia berpaling ke Alya lagi, suaranya lebih rendah, hampir intim. “Kami tunggu kehadiran Ibu. Pasti… memuaskan.”
*
Setelah sarapan usai, Alya berpisah dari Maya untuk kembali ke kamarnya, tapi langkahnya terhenti di lorong saat mendengar suara langkah mendekat. Itu Reza, yang entah bagaimana muncul di belakangnya. “Alya, maaf mengganggu. Boleh saya antar ke ruang baca sebentar? Kita bisa bahas materi kelas lebih detail.”
Alya berbalik, hatinya berdegup. Tubuh Reza begitu dekat di lorong sempit itu – otot lengan yang menonjol di balik baju koko, tatapan penuh gairah yang membuat udara terasa lebih tebal. “Ah, baik, Ustadz Reza. Terima kasih.”
Mereka berjalan berdampingan, bahu hampir bersentuhan. Reza berbicara pelan tentang hadis-hadis favoritnya dari Bukhari, suaranya seperti belaian – dalam, menggoda. “Di Kairo, pasti Ibu sering diskusi malam-malam dengan teman-teman, ya? Di bawah bintang-bintang Nil… suasananya pasti berbeda.”
Alya tersipu, menunduk. “Iya, Ustadz. Banyak diskusi mendalam, tapi tetap dalam batas adab.” Tapi dalam hati, ia merasakan panas samar di perutnya – rasa penasaran yang mulai berubah menjadi getaran aneh, seperti dorongan untuk mendekat lebih jauh.
Di ruang baca, rak-rak kitab menjulang tinggi, aroma kertas tua memenuhi udara. Reza membuka sebuah mushaf, jarinya yang panjang menyentuh kertas dengan lembut, hampir erotis. “Ini ayat yang sering saya ajar. Tapi dengan Ibu… pasti lebih hidup.” Tatapannya bertemu lagi, kali ini lebih lama, seolah menjanjikan pelajaran yang tak tertulis di kitab mana pun.
Alya duduk di seberangnya, kakinya bersilang sopan, tapi ia merasakan keringat tipis di punggungnya. Suasana ruang itu tenang, tapi penuh ketegangan – seperti benang halus yang menariknya ke arah Reza, ke arah rahasia pesantren yang mulai tercium baunya. “InsyaAllah, Ustadz. Saya akan usahakan yang terbaik.”
Reza tersenyum, bibirnya melengkung nakal. “Saya yakin, Alya. Dan saya… siap membantu apa pun yang kamu butuhkan.” Kata-kata itu menggantung, penuh arti lain, membuat Alya menelan ludah pelan.
Saat Alya akhirnya bangkit untuk meninggalkan ruang baca, pintu kayu itu terbuka pelan, dan seorang pria lain melangkah masuk dengan langkah tenang yang penuh wibawa. Ia tinggi, sekitar 178 cm, dengan wajah tampan yang dikelilingi jenggot tipis rapi, mata coklatnya teduh seperti danau pagi yang tenang.
Baju koko putihnya sederhana, tapi cara ia memakainya membuatnya terlihat seperti pemimpin bersahaja – bukan sombong, tapi penuh karisma yang menenangkan. Itu Ustadz Fahri Fadhlurrahman, meski Alya belum tahu namanya. Aroma buku lama dan sedikit wewangian kayu cendana menyertai kehadirannya, kontras dengan panas maskulin Reza yang masih menempel di udara.
“Assalamu’alaikum,” sapa Fahri dengan suara lembut tapi tegas, matanya langsung bertemu dengan Alya sebelum menyapa Reza sekilas. Tatapannya ke Alya penuh hormat – tak ada gairah liar seperti Reza, hanya kehangatan tulus yang membuat Alya merasa dilindungi, seperti pelukan seorang ayah yang jarang ia rasakan.
“Maaf mengganggu. Saya Ustadz Fahri, pengajar Fiqih di sini. Saya dengar ada tamu baru yang akan mengisi kelas Tafsir besok. Selamat datang, Bu Alya.”
Alya membalas salam dengan cepat, hatinya yang tadi berdegup kencang kini melambat, digantikan rasa aman yang aneh. “Wa’alaikumsalam, Ustadz Fahri. Terima kasih. Saya baru saja diskusi dengan Ustadz Reza soal materi.”
Reza bangkit, tersenyum lebar tapi ada kilatan kompetitif di matanya. “Benar, Ustadz. Bu Alya ini luar biasa – ilmunya dari Kairo pasti bikin kelas besok jadi seru. Saya yang akan dampingi dia.”
Fahri mengangguk sopan ke Reza, tapi tatapannya kembali ke Alya, penuh perhatian. “Alhamdulillah. Saya yakin santri-santri akan banyak dapat manfaat. Kalau Bu Alya butuh bantuan apa pun – entah referensi kitab atau sekadar diskusi – saya siap.
Pesantren ini kadang… rumit, tapi saya harap Bu Alya bisa menjaga hati di tengah hiruk-pikuknya.” Kata-katanya sederhana, tapi ada nada pelindung di sana, seperti peringatan halus yang tak memaksa. Matanya menelusuri wajah Alya dengan lembut, melihat polosnya yang masih utuh, seolah ingin menjaganya dari badai yang belum terlihat.
Alya tersenyum, merasakan kontras tajam antara dua pria ini – Reza dengan pesonanya yang membara seperti api liar, Fahri dengan keteduhannya seperti angin sepoi yang menenangkan. “Terima kasih, Ustadz Fahri. Saya akan ingat itu. InsyaAllah, semuanya lancar.”
Fahri mengangguk, tangannya terulur untuk salam perpisahan – sentuhan jari yang singkat, tapi penuh kehangatan murni, tanpa arus listrik aneh seperti saat dengan Khalid.
“Semoga Allah mudahkan. Sampai jumpa di kelas besok, Bu.” Ia melangkah ke rak buku, membiarkan Alya dan Reza keluar, tapi Alya merasakan tatapannya mengikuti punggungnya sebentar – bukan menggoda, tapi seperti doa yang melindunginya.
Saat meninggalkan ruang baca, Alya merasakan langkahnya lebih berat, hatinya campur aduk antara tugas mulia, dorongan penasaran yang semakin kuat dari Reza, dan rasa aman tak terduga dari Fahri.
Tapi rasa penasaran itu tak berhenti di sana – ia teringat Aula Serbaguna dari tur kemarin, ruangan yang penuh misteri dengan kanvas kaligrafi dan suara rebana lembut.
“Mungkin… aku harus lihat lagi,” gumamnya pelan, langkahnya berbelok ke arah timur gedung utama tanpa sadar. Siang itu, matahari tegak di langit biru tanpa awan, menyinari halaman dengan cahaya terik yang membuat udara terasa lengket. Pintu kayu berukir ayat-ayat Al-Qur’an terbuka lebar, mengundangnya masuk.
Alya ragu sejenak di ambang pintu, tapi rasa penasarannya menang. Ia melangkah masuk, aroma tinta kaligrafi dan kayu tua langsung menyambutnya, bercampur bau samar keringat segar dari latihan hadrah yang baru usai.
Ruangan luas itu sepi tapi tidak kosong – beberapa santri perempuan duduk bersila di tikar anyaman, berbisik-bisik sambil memegang pena bulu, tapi suara mereka tak lagi tentang seni – ada nada rendah, seperti rahasia yang dibagikan di balik pintu tertutup.
Di sudut ruangan, Ustadzah Rani sedang berdiri di dekat rak alat musik, tangannya menyentuh rebana dengan gerakan lambat yang hampir menggoda, jarinya menelusuri kulit ketat instrumen itu seperti belaian pada kulit manusia.
Ia menoleh saat Alya masuk, senyumnya melebar – bukan senyum ramah biasa, tapi ada lengkungan licik di ujung bibir. “Alya! Kok ke sini lagi? Aku kira kamu masih sibuk mikirin kelas besok sama Reza.” Nada suaranya ringan, tapi ada godaan halus di sana, seperti bisikan angin yang menyusup ke telinga.
Alya tersipu, pipinya memanas di bawah jilbab. “Ah, iya… cuma penasaran aja, Rani. Kemarin suasananya… beda. Kayak ada yang nggak biasa di sini.” Ia melangkah lebih dalam, matanya menyapu ruangan.
Santri-santri itu – Laila dan Nadia, yang ia kenali sekilas dari kemarin – sedang duduk berdekatan, kaki mereka bersentuhan samar di bawah gamis longgar.
Laila, yang lebih blak-blakan dengan wajah cantik berbibir tebal, tertawa pelan saat Nadia membisikkan sesuatu, tangan Nadia menyentuh paha Laila sekilas, gerakan yang terlalu akrab untuk sekadar teman santri.
Tatapan mereka tertuju pada Alya, bukan dengan rasa ingin tahu yang murni, tapi seperti menakar – seperti serigala betina yang menilai mangsa baru di kawanannya.
Rani mendekat, bahunya hampir menyentuh Alya, aroma parfumnya yang manis – campuran mawar dan rempah – membuat udara terasa lebih pekat. “Beda? Oh, iya… Aula ini emang punya cerita sendiri. Di siang bolong kayak gini, santri-santri memang suka ‘eksplorasi’.
Bukan cuma kaligrafi atau hadrah, tapi… hal-hal yang bikin hati deg-degan.” Ia mencondongkan tubuh, bibirnya dekat telinga Alya, napas hangatnya menyentuh kulit leher yang terlindung jilbab. “Kamu pernah penasaran nggak, Alya? Soal apa yang sebenarnya terjadi di balik pintu-pintu tertutup pesantren ini?”
Alya menelan ludah, jantungnya berdegup kencang. Tubuhnya bereaksi tanpa izin – putingnya mengeras samar di balik bra, panas tipis menyebar di perut bawahnya seperti api kecil yang baru dinyalakan. “Rani… maksudmu apa? Ini kan tempat belajar agama. Harusnya nggak ada yang aneh.” Tapi suaranya goyah, polosnya mulai retak di bawah tatapan Rani yang penuh misteri.
Rani tertawa pelan, suaranya seperti lonceng kecil yang bergema di dada Alya. “Agama? Iya, tapi agama juga ngajarin kita buat kenal sesama manusia, kan? Santri-santri di sini… mereka pintar banget adaptasi. Lihat aja Laila sama Nadia. Mereka santri senior, udah biasa ‘berbagi ilmu’ di sudut-sudut kayak gini.” Ia menarik tangan Alya pelan, membawanya ke dekat dua santri itu.
Laila menoleh, matanya yang gelap berkilau nakal, bibirnya melengkung seperti undangan. “Halo, Ustadzah Alya. Mau ikut? Kami lagi diskusi soal… teknik relaksasi setelah latihan hadrah. Tubuh kita kadang capek, butuh pelepasan.”
Nadia, yang lebih pendiam dengan wajah manis dan kulit kuning langsat, tersipu tapi tak mundur. Tangannya masih di paha Laila, jarinya menggambar lingkaran kecil di kain gamis, gerakan yang membuat Alya membayangkan apa yang tersembunyi di bawahnya – lembut, hangat, basah mungkin.
“Iya, Ustadzah. Kadang, setelah pukulin rebana berjam-jam, tangan kita butuh… dipijat lebih dalam. Mau coba? Kami bisa tunjukin caranya.” Ngocoks.com
Alya mundur selangkah, tapi Rani menahan lengannya, sentuhan itu lembut tapi tegas, seperti jaring laba-laba yang lengket. “Jangan takut, Alya. Ini hal biasa. Aula ini rahasianya bukan cuma buat seni – di malam hari, kalau lampu redup, ini jadi tempat ‘kegiatan ekstrakurikuler’ yang bener-bener bikin nagih.
Para Ustadzah kayak aku, Diah, Shinta… kami sering ikutan. Bahkan para santri pun ikut, belajar ‘akhlak’ versi lain.” Matanya menelusuri tubuh Alya, dari lekuk pinggang semampai hingga pinggul yang ideal, seolah bisa melihat melalui kain tebal itu. “Kamu selama di Kairo cuma jadi akhwat biasa, ya? Tapi aku yakin, di balik jilbab rapi itu, ada akhwat yang penasaran pengen rasain… sentuhan pertamanya.”
Udara terasa lebih panas sekarang, meski angin siang bertiup dari jendela yang terbuka. Alya merasakan keringat tipis mengalir di punggungnya, menempel di kulit putihnya hingga basah.
Bisik-bisik santri lain terdengar lebih jelas. “Lihat tuh, yang baru… pasti mantap,” gumam seseorang di belakang, suara perempuan tapi nadanya kasar, penuh nafsu.
Tatapan mereka – santri laki-laki yang kebetulan lewat pintu, mata mereka lapar, menelusuri garis tubuh Alya seperti ingin merobek jilbabnya pelan-pelan.
Ada yang berbisik tentang “pesta malam nanti”, kata-kata samar tapi cukup untuk membuat imajinasi Alya berlari liar – tubuh-tubuh bergelut di tikar anyaman, erangan tertahan di balik tangan, cairan hangat yang menetes di lantai kayu.
“Aku… aku harus balik ke kamar,” pamit Alya tergagap, menarik tangannya dari Rani. Tapi kakinya terasa lemas, seperti sudah terperangkap. Rani hanya tersenyum, melepaskannya dengan enggan.
“Oke, tapi ingat, Alya. Rahasia Aula ini kayak candu – sekali kamu selidiki lebih dalam, susah lepas. Nanti malam, kalau penasaran, dateng aja. Kami tunggu… buat ajarin kamu ‘eksplorasi’ yang benar.”
Alya keluar dari aula dengan langkah cepat, napasnya tersengal, pipinya merah padam. Di lorong sepi, ia bersandar ke dinding kayu yang dingin, tangannya menekan dada untuk meredam degupan jantung yang liar.
“Apa yang barusan aku rasain? Ini… gila.” Tapi di balik penyesalan itu, ada percikan hasrat baru – bayangan tangan Nadia di paha Laila, jari Rani yang hangat, dan janji “pelepasan” yang membuat selangkangannya berdenyut samar, basah tipis di celana dalamnya.
Suasana aneh pesantren ini bukan lagi perasaan samar – itu nyata, seperti jaring yang mulai melilit tubuh polosnya, menariknya ke kegelapan manis yang tak bisa ia tolak sepenuhnya.
Bersambung…