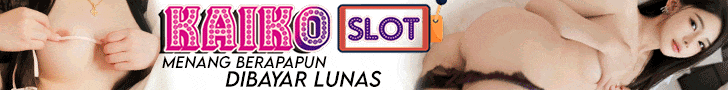KELAS PERDANA
Pagi menyingsing di Pesantren Darul Hikmah, udara pagi menyusup melalui celah gorden di jendela kamar Alya, membangunkannya dari tidur yang gelisah. Malam sebelumnya, mimpi-mimpinya penuh bayangan samar – tatapan lapar para santri di lorong, bisik-bisik ambigu Rani yang seperti belaian panas di kulitnya, dan kontras kehangatan Fahri yang membuat hatinya bimbang.
Ia terbangun dengan napas pendek, selimut tipis yang menutupi tubuh semampainya terasa lengket di kulit putihnya yang bersih, seperti keringat dari mimpi yang terlalu nyata. Jam dinding menunjukkan pukul 04:30, azan Subuh belum bergema, tapi Alya sudah terjaga, pikirannya berputar pada hari ini – kelas Tafsir Lanjutan pertamanya, di depan santri-santri yang tatapannya kemarin membuat tubuhnya bereaksi aneh.
“Alhamdulillah… hari pertama mengajar, harus bisa!,” gumamnya pelan, bangkit dari ranjang kayu dengan gerakan lambat. Kamarnya kecil tapi rapi – lemari kayu tua di sudut, meja belajar dengan tumpukan kitab, dan cermin bulat di dinding yang memantulkan wajah cantiknya yang masih polos – mata coklat teduh dengan lingkaran hitam tipis di bawahnya akibat kurang tidur, bibir tipis yang tergigit pelan karena gelisah.
Rambut hitam panjangnya tergerai liar, menyentuh punggungnya yang mulus hingga pinggang, dan tubuhnya masih terbungkus gamis tidur longgar berwarna putih, yang samar-samar menonjolkan bentuk payudaranya yang montok tapi kencang, dan pinggul yang melengkung sempurna.
Alya berdiri di depan lemari, menarik napas dalam untuk menenangkan degupan jantung yang sudah mulai kencang. Hari ini bukan sembarang hari – ia akan berdiri di depan kelas, mengajar ayat-ayat suci, tapi setelah apa yang ia rasakan kemarin, ia tahu tatapan-tatapan itu akan datang lagi.
“Fokus, Alya. Ini tugas dari Allah,” bisiknya, tapi tangannya gemetar saat membuka pintu lemari, menatap deretan gamis dan jilbab yang ia bawa dari koper.
Pilihan baju bukan lagi soal kenyamanan – itu juga soal perlindungan – bagaimana menutupi tubuhnya yang tiba-tiba terasa begitu sensitif, seperti setiap kain akan bergesekan dengan kulitnya dan membangkitkan sensasi aneh lagi.
Ia mulai menyusuri pilihan-pilihannya, tangan halusnya menyentuh kain-kain lembut satu per satu. Pertama, gamis krem panjang longgar yang ia pakai kemarin – sederhana, Islami, tapi ingatannya kembali ke lorong saat ia berpapasan dengan para santri – bagaimana cahaya matahari membuat bayangan lekuk pinggangnya terlihat, dan tatapan Laila yang seperti ingin merabanya. “Nggak… terlalu tipis kalau terkena cahaya,” gumamnya, menariknya keluar tapi meletakkannya kembali.
Selanjutnya, gamis abu-abu gelap dengan lengan panjang dan kerah tinggi – lebih tebal, lebih aman. Ia mengangkatnya, menempelkannya ke tubuh, membayangkan bagaimana rasanya berdiri di depan kelas dengan itu.
Kainnya kasar di kulit, tapi cukup untuk menutupi lekuk dadanya yang naik-turun cepat saat gelisah. “Ini… mungkin bisa,” pikirnya, tapi saat ia memegangnya di depan cermin, bayangan dirinya memantul – gamis itu akan menutupi semuanya, tapi justru membuatnya merasa terkungkung, seperti memenjarakan hasrat yang mulai menyelinap.
Ia membayangkan santri-santri menatapnya – bukan dengan rasa hormat, tapi lapar, seperti kemarin. Putingnya mengeras samar di balik gamis tidur, bergesekan dengan kain tipis, membuatnya menggigit bibir. “Astaghfirullah… aku kenapa sih?”
Ia meletakkan gamis abu-abu itu di ranjang, melanjutkan pencarian. Pilihan ketiga – gamis hijau zaitun dengan potongan sedikit lebih pas di pinggang, jilbab senada yang bisa diikat rapi tapi tak terlalu ketat. Ini setelan favoritnya di Kairo – elegan, menonjolkan sisi alimnya tanpa terlihat kaku.
Tapi saat ia menyentuh kain sutranya yang halus, ingatan tentang ucapan Shinta muncul. “Badan kamu bagus banget, lho. Pasti enak kalau… dibikin rileks.”
Jarinya berhenti, merasakan kelembutan kain itu seperti belaian, dan tanpa sadar, ia menyusurinya ke perutnya sendiri, di bawah gamis tidur. Panas tipis menyebar, membuat selangkangannya berdenyut pelan – basah yang ia coba abaikan sejak bangun. “Nggak… ini terlalu menggoda. Mereka bakal lihat lekuk tubuhku.”
Alya duduk di tepi ranjang, tangannya menutup wajah sejenak, napasnya pendek. Pilihan baju ini tiba-tiba terasa seperti pertarungan batin – antara ingin aman di balik kain tebal, atau tanpa sadar memilih yang membuatnya terasa… bebas.
Tubuhnya, yang dulu hanya alat untuk beribadah, sekarang seperti punya kehendak sendiri – payudaranya terasa lebih berat, sensitif terhadap gesekan kain, dan pahanya yang tertutup terasa hangat, seperti menunggu sentuhan yang belum datang.
“Ini pengaruh suasana kemarin… pasti,” bisiknya, tapi di hati, ia tahu – tatapan Reza yang intens, bisik Shinta yang ambigu, sudah menanam benih penasaran yang tumbuh liar semalam.
Akhirnya, ia memilih jalan tengahnya – gamis biru tua longgar dengan lengan lebar dan kerah bulat tinggi, cukup tebal untuk menutupi tapi nyaman untuk bergerak. Jilbab polos senada, diikat rapi tapi tak terlalu ketat di leher.
Ia melepas gamis tidur, berdiri telanjang sejenak di depan cermin – kulit putih mulus tanpa cacat, payudara montok berbentuk sempurna dengan puting merah muda yang mengeras karena udara pagi yang dingin, perut rata dengan garis halus ke pinggul lebar, dan rambut hitam panjang yang jatuh seperti air terjun ke pantat bulatnya.
Ia menatap dirinya lama, jarinya menyentuh perut, merasakan kehangatan di sana. “Kenapa… aku seperti ini? Seperti ingin disentuh,” pikirnya, malu tapi tak bisa berhenti. Klitorisnya berdenyut pelan, membuatnya menekan paha, tapi ia cepat-cepat menggeleng, mengenakan bra putih yang menekan payudaranya dengan lembut, lalu celana dalam katun polos yang langsung basah tipis saat kain menyentuh kulit sensitifnya.
Saat mengenakan gamis biru tua, kain itu meluncur di kulitnya seperti belaian – lengan panjang menyusuri lengan halusnya, badan longgar menutupi lekuk pinggang tapi tak bisa sembunyikan bentuk idealnya sepenuhnya.
Ia mengikat jilbab di depan cermin, menyesuaikan hingga menutupi leher dan dada, tapi saat melihat bayangannya dalam cermin, ia tersipu – gamis itu membuatnya terlihat alim, tapi cahaya lampu membuat siluet pinggulnya terlihat samar, seperti undangan tak sengaja. “Cukup… ini aman,” katanya, tapi hatinya berbohong – tubuhnya sudah panas, siap untuk tatapan tajam yang akan datang.
Setelah bersiap, Alya melangkah keluar kamar menuju masjid untuk sholat Subuh berjamaah. Lorong pagi masih remang, tapi sudah ada santri yang berlalu-lalang, tatapan mereka menyapa sopan – tapi lagi-lagi, ada yang lebih – seorang santri laki-laki melewatinya, matanya turun sekilas ke dada yang tertutup, senyumnya tipis tapi penuh arti.
Alya menunduk, jantungnya berdegup lagi, sensasi kemarin kembali – merinding, panas di perut bagian bawahnya. Di masjid, saf wanita penuh, dan ia sholat dengan khusyuk, tapi pikirannya melayang – membayangkan kelas nanti, suara santri yang mendengar tafsirnya, tapi tatapan mereka lapar.
Setelah sholat, Maya menunggunya di halaman, wajahnya ceria seperti biasa. “Kak, siap? Santri-santri pada heboh nungguin Kakak. Ustadz Reza bilang materi Kakak pasti bikin mereka ‘melek’.” Maya terkekeh, tapi ada nada menggoda di suaranya, membuat Alya tersipu.
“Semoga bermanfaat, Dek. Kakak deg-degan nih,” balas Alya, tangannya memegang tas erat. Mereka berjalan bersama ke ruang makan, sarapan sederhana – bubur ayam hangat dan teh manis. Tapi bahkan di sana, godaan halus muncul juga.
Ustadzah Diah duduk di meja sebelah, tersenyum hangat sambil menyapa.”Alya, baju hari ini cantik. Cocok buat hari spesial. Nanti kalau capek ngajar, mampir ke ruangan 9uru ya… nanti bisa cerita-cerita.” Senyum Diah keibuan, tapi matanya menelusuri gamis Alya, seolah bisa melihat basah samar di celana dalamnya.
Alya mengangguk sopan, tapi perutnya bergejolak. Setelah sarapan, ia berpisah dari Maya, menuju ruang kelas Tafsir Lanjutan di gedung utama. Lorong pagi lebih ramai sekarang, santri berlalu-lalang dengan buku di tangan, tapi tatapan mereka terhadap Alya lebih intens.
Seperti kemarin, tapi kali ini dengan senyum yang lebih berani. Laila dan Nadia lewat di depannya, Laila berbisik kepada Nadia cukup keras. “Lihat, bajunya rapi banget. Tapi di balik itu… pasti indah.” Nadia tersipu, tapi matanya bertemu Alya, penuh rasa ingin tahu.
Alya mempercepat langkah, pintu kelas sudah terbuka, santri-santri duduk rapi di bangku kayu panjang – sekitar 20 orang, campur laki-laki dan perempuan, usia 18-22 tahun, senior yang haus ilmu tapi juga… yang lain. Ustadz Reza sudah di depan, berdiri di samping papan tulis, tubuh atletisnya condong santai, matanya langsung bertemu Alya saat ia masuk.
“Assalamualaikum, Ustadzah Alya. Santri-santri, ini Ustadzah Alya yang akan mengajar hari ini. Ilmunya dari Kairo, pasti bikin kita tambah paham.” Suaranya dalam, tatapannya intens seperti kemarin, membuat Alya merasa telanjang meski bajunya rapat.
“Wa’alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh,” balas Alya, suaranya tenang meski jantungnya berpacu. Ia melangkah ke depan, meletakkan tas di meja 9uru, tangannya gemetar samar saat membuka mushaf. Santri-santri menyapa balik, tapi tatapan mereka… oh, tatapan itu.
Laila di baris depan tersenyum, matanya turun ke lekuk pinggang Alya yang terlihat saat ia bergerak. Andi di belakang menyeringai ke Faisal, bisiknya samar. “Kalau nanti ada kesempatan, aku duluan ya!.” Nadia menunduk malu, tapi pipinya merah, tangannya menggenggam pensil seperti ingin memegang sesuatu yang lain.
Alya memulai kelas dengan bacaan ayat, suaranya lembut dan alim, menjelaskan tafsir tentang penjagaan hati dari godaan duniawi.
“Dalam ayat ini, Allah SWT mengingatkan kita untuk menjaga pandangan dan hati dari yang haram…” Kata-katanya mengalir, tapi ia merasakan tatapan lain, tatapan Reza yang tak lepas dari bibirnya, tatapan Laila yang seperti membayangkan ciumannya, dan santri laki-laki di belakang yang menggeser posisi duduk, seperti menyesuaikan tonjolan di celananya.
Tubuh Alya bereaksi, dada berdebar kencang, puting tegang bergesek kain bra, dan basah di selangkangannya semakin licin, membuatnya menggeser kaki pelan di belakang meja.
Diskusi berjalan lancar pada awalnya, santri bertanya tentang sanad hadis, Alya jawab dengan pengetahuan mendalam. Tapi di bawahnya, ketegangan membara. Saat Ustadz Reza ikut bertanya, suaranya dalam membuat Alya tersipu,
“Ustadzah, bagaimana kalau godaannya itu berasal dari dalam diri sendiri? Bagaimana cara… mengatasinya?” Pertanyaan ambigu, tatapannya penuh gairah, membuat ruangan kelas terasa lebih panas. Para santri tertawa pelan, Laila menambahkan “Iya, Ustadzah. Bagaimana caranya mengatasi tubuh kita yang tergoda dengan suatu hal?”
Alya menelan ludah, menjawab dengan adab, tapi pikirannya liar – membayangkan Reza menyentuhnya di ruang kelas yang kosong, tangan kekar itu menyusuri gamisnya.
*
Kelas Tafsir Lanjutan akhirnya usai, suara tepuk tangan dari santri-santri masih bergema samar di telinga Alya saat ia membereskan mushaf dan catatan ke dalam tas kainnya.
Udara di ruang kelas terasa lebih tebal sekarang, bercampur aroma kertas tua dan keringat halus dari diskusi panjang – atau mungkin hanya imajinasinya yang membuat segalanya terasa lebih lembab, lebih menempel di kulit.
Tubuhnya lelah tapi gemetaran, denyut samar di selangkangannya belum reda sepenuhnya sejak tatapan Reza tadi, dan basah licin di celana dalam katunnya membuat setiap gesekan paha terasa seperti pengingat – hari pertama ini bukan akhir, tapi awal dari sesuatu yang lebih dalam, lebih berbahaya.
“Terima kasih, Ustadzah Alya! Materinya mantap,” seru Laila dari baris depan, berdiri sambil merapikan jilbabnya dengan gerakan lambat yang disengaja, matanya masih menelusuri lekuk gamis biru tua Alya seperti ingin mengupasnya lapis demi lapis.
Nadia di sebelahnya tersenyum malu-malu, pipinya merah. Santri laki-laki seperti Andi dan Faisal sudah keluar duluan, tapi Alya bisa merasakan tatapan mereka yang tertinggal – seperti jejak panas di tubuhnya, membuat bulu kuduknya berdiri.
Kini hanya tersisa Reza dalam kelas itu, ia mendekat saat Alya membereskan buku. “Hebat, Alya. Santri pada suka. Kamu… cocok ngajar di sini.” Tatapannya turun ke lehernya, napasnya dekat, membuat Alya mundur ke dinding.
“Kalau kamu butuh… bantuan lainnya, bilang saja.” Kata-katanya seperti janji, dan Alya merasakan denyut kuat di klitorisnya, cairannya menetes pelan di celana dalam.
“InsyaAllah, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di kelas berikutnya Ustadz,” balas Alya dengan suara tenang yang ia paksa keluar, meski jantungnya masih berdegup kencang seperti drum rebana di Aula Serbaguna.
Ia mengangkat tasnya, gamis biru tuanya bergoyang lembut mengikuti langkahnya, kain tebal itu bergesekan pelan dengan kulit pahanya yang sensitif, mengingatkannya pada basah yang menetes pelan tadi saat Reza bertanya soal “godaan”.
“Astaghfirullah,” batinnya, pipinya memanas di bawah jilbab. Ia harus keluar dari ruangan ini sebelum pikirannya semakin liar.
Pintu kelas terbuka dengan derit pelan, dan Alya melangkah ke lorong yang sudah mulai ramai dengan santri lain yang bergegas ke kelas berikutnya.
Cahaya pagi menyinari lorong kayu, menciptakan bayangan panjang yang jatuh di dinding, dan untuk sesaat, Alya merasa seperti berjalan di panggung – setiap langkahnya diamati, setiap lekuk gamisnya yang longgar tapi tak bisa sembunyikan bentuk ideal tubuhnya menjadi sorotan.
Seorang santri perempuan menyapanya dengan anggukan hormat, tapi matanya turun sekilas ke dada Alya yang naik-turun cepat, senyumnya tipis seperti sebuah rahasia.
Alya menundukkan pandangan, berusaha fokus pada langkahnya menuju ruang 9uru di ujung lorong, tapi sensasi itu tak hilang – panas tipis di perut bawahnya, puting yang masih tegang bergesek kain bra, seperti tubuhnya menolak untuk kembali tenang.
Tiba-tiba, di tikungan lorong dekat tangga, ia berpapasan dengan sosok yang langsung membuat degupannya melambat – Ustadz Fahri Fadhlurrahman. Ia baru saja keluar dari ruang Fiqh sebelah, bergerak dengan langkah tenang yang penuh wibawa, baju koko putihnya sederhana tapi menonjolkan bahu lebar dan dada yang kokoh, jenggot tipis rapinya menambah aura teduh seperti masjid di pagi buta.
Matanya teduh langsung bertemu dengan Alya, dan senyumnya muncul – bukan senyum menggoda seperti Reza, tapi hangat, tulus, seperti pelukan yang tak perlu disentuh. Aroma kayu cendana samar dari dirinya menyusup ke udara, kontras dengan panas maskulin Reza yang masih menempel di ingatan Alya.
“Assalamualaikum, Alya. Kelas pertamanya gimana? Lancar?” sapanya dengan suara lembut tapi tegas, seperti doa yang dibisikkan pelan. Ia berhenti di depannya, tak terlalu dekat tapi cukup untuk membuat Alya merasa… aman, seperti dinding benteng di tengah badai tatapan-tatapan liar tadi.
“Wa’alaikumsalam, Ustadz Fahri,” balas Alya cepat, tersenyum lega untuk pertama kalinya sejak kelas usai. Napasnya melambat, degupan jantungnya yang tadi liar kini seperti irama sholat yang tenang.
“Alhamdulillah, lancar kok. Santri-santri antusias, meski… suasananya agak bikin deg-degan.” Kata-katanya keluar tanpa filter, polos seperti biasa, tapi ada nada gelisah yang tak bisa ia sembunyikan – seperti ingin curhat, tapi takut terlalu terbuka.
Fahri mengangguk pengertian, matanya penuh perhatian tanpa menelusuri tubuhnya seperti yang lain. “Deg-degan itu wajar, apalagi hari pertama. Santri di sini… mereka pintar, tapi kadang ‘antusias’ mereka punya cara sendiri.
Kalau ada yang mengganggu, bilang aja ke saya, ya? Saya nggak mau kamu merasa sendirian di sini.” Suaranya rendah, hampir seperti bisikan pelindung, dan ia melangkah ke samping, memberi isyarat sopan untuk berjalan bersamanya menuju ruang 9uru. “Ayo, saya temani ke ruang 9uru. Kebetulan saya juga mau ke kelas dekat situ, ambil buku.”
Alya ragu sejenak, tapi kehangatan itu menang – ia mengangguk, berjalan di sampingnya, bahu mereka hampir dempet tapi tak pernah bersentuhan, jarak yang sopan tapi membuatnya merasa dilindungi.
Lorong pagi ramai, santri berlalu-lalang dengan buku di tangan, tapi tatapan mereka ke arah Alya dan Fahri terasa berbeda – beberapa santri perempuan tersenyum iri, laki-laki menunduk hormat, tapi tak ada bisik-bisik kasar seperti tadi.
Alya merasa napasnya lebih ringan, gamis biru tuanya terasa lebih nyaman sekarang, meski basah di celana dalamnya masih ada, seperti rahasia kecil yang tersembunyi.
“Saya senang bisa ngajar tadi, Ustadz. Materi tentang penjagaan hati… rasanya pas sekali buat saya sendiri hari ini,” kata Alya pelan, langkahnya mengikuti ritme Fahri yang tenang.
Mereka melewati jendela besar yang menghadap halaman, cahaya pagi menyinari wajahnya, membuat sorot matanya yang teduh terlihat lebih lembut. “Tapi… santri-santri tatapannya agak… intens. Kayak mereka lagi mikirin yang lain selain tafsir.”
Fahri tertawa ringan, suaranya seperti angin sepoi yang membawa kedamaian. “Iya, saya paham. Pesantren ini besar, Alya, dan nggak semua orang punya hati yang sama kuatnya. Beberapa santri senior… mereka sudah terbiasa dengan ‘kebebasan’ yang seharusnya nggak ada di sini.
Tapi kamu kuat – dari Kairo, kan? Pengalamanmu pasti bisa bantu kamu jaga diri.” Matanya melirik sekilas ke wajah Alya, penuh kekaguman tulus, tak ada gairah tersembunyi seperti Reza. “Kalau butuh teman diskusi, atau sekadar curhat, pintu ruang Fiqh saya selalu terbuka. Saya… senang lihat kamu di sini. Seperti angin segar.”
Alya tersipu, pipinya memanas tapi kali ini karena kehangatan, bukan panas nafsu. Kata-kata Fahri seperti obat yang menenangkan gelora di tubuhnya, membuat denyut di selangkangannya mereda pelan, meski basahnya masih menempel lengket di kulit pahanya.
“Terima kasih, Ustadz. Saya… juga senang punya teman kayak Ustadz. Di Kairo, saya biasa belajar malam-malam sendiri, tapi di sini… rasanya beda. Lebih… hidup, tapi juga lebih menakutkan.” Suaranya pelan, seperti curhatan, dan ia melirik Fahri sekilas – wajah tampannya yang berwibawa, mata teduh yang membuatnya ingin bersandar, ingin dilindungi dari tatapan lapar yang lain.
Mereka berjalan berdampingan, langkah selaras, melewati lorong yang mulai sepi karena kelas sudah dimulai lagi. Fahri melanjutkan, suaranya tetap lembut. “Menakutkan itu bagian dari ujian, Alya. Tapi ingat, Allah selalu kasih jalan keluar.
Kalau kamu merasa terganggu entah dari tatapan, atau bisik-bisik, jangan ragu hubungi saya. Saya bukan cuma pengajar, tapi… teman juga.” Ia tersenyum lagi, tangannya hampir menyentuh lengan Alya saat mereka berbelok ke tangga menuju lantai atas, tapi ia menahannya, menjaga jarak sopan.
Sentuhan itu tak terjadi, tapi Alya merasakannya seperti hembusan hangat yang kontras dengan jari Reza yang hampir menyentuhnya tadi, yang membuatnya basah. Ngocoks.com
Sampai di depan ruang 9uru, pintu kayu setengah terbuka mengeluarkan aroma teh hangat dan kertas, suara obrolan pelan ustadzah lain terdengar dari dalam. Fahri berhenti, menoleh ke Alya dengan mata penuh perhatian. “Nah, sampai juga. Istirahat dulu ya, Alya.
Kamu hebat hari ini. Sampai jumpa lagi.” Salam perpisahannya sederhana, sentuhan jari tangan kanan yang singkat, hangat murni tanpa arus listrik aneh, tapi cukup untuk membuat hati Alya tenang, meski tubuhnya masih bergetar samar dari kelas tadi.
“Terima kasih, Ustadz. Sampai jumpa,” balas Alya, tersenyum tulus sebelum melangkah masuk ke ruang 9uru. Pintu tertutup pelan di belakangnya, tapi kehangatan Fahri masih menempel, seperti perisai tipis di tengah pusaran godaan pesantren ini.
Di dalam, Rani, Shinta dan Diah sudah menunggu, senyum mereka melebar saat melihatnya – dan Alya tahu, istirahat ini takkan tenang. Tapi untuk sesaat, berkat Fahri, ia merasa bisa bernapas.
Rani duduk santai di kursi empuk sambil menyeruput teh, Diah merapikan tumpukan kertas dengan gerakan keibuan yang lembut, dan Shinta berdiri di dekat jendela, matanya menatap halaman pesantren dengan senyum misterius yang selalu membuat Alya bertanya-tanya.
“Eh, Alya! Masuk dong, kayaknya capek banget nih abis kelas,” sapa Rani dengan suara ramah tapi ada nada menggoda yang samar, seperti biasa. Ia menepuk kursi kosong di sebelahnya, matanya menyapu gamis biru tua Alya dari atas ke bawah – bukan tatapan lapar seperti para santri, tapi penuh rasa ingin tahu, seperti ingin membaca rahasia di balik kain rapi itu.
Diah tersenyum hangat, meletakkan secangkir teh di depan kursi Alya. “Alya, minum dulu. Hari ini pasti rame, ya? Santri-santri pasti pada suka kelas kamu.”
Shinta berbalik dari jendela, aura dewasanya membuat ruangan terasa lebih pekat. “Atau… suka sama kamu, maksudnya,” tambahnya dengan tawa pelan, suaranya rendah seperti bisikan rahasia, matanya berkedip ke arah Alya dengan kilatan yang ambigu.
Alya duduk di kursi yang ditunjuk Rani, tangannya memegang cangkir teh hangat untuk menyembunyikan gemetar samar di jarinya. “Alhamdulillah, semuanya antusias dan lancar kok. Santri-santri juga pintar, cuma… suasananya kadang bikin deg-degan.”
Suaranya lembut, tapi hatinya bergejolak – campuran panas dari tatapan Reza tadi yang masih menempel di kulitnya, seperti bekas sentuhan angin panas yang membuat dadanya naik-turun lebih cepat, dan kehangatan Fahri yang baru saja ia tinggalkan, seperti selimut lembut yang menyelimuti gelora itu.
Ia menyeruput teh pelan, rasa manisnya menyebar di lidah, tapi pikirannya melayang. Dalam hati, Alya mulai menyadari sesuatu yang tak bisa lagi ia abaikan.
Ada godaan kuat yang menarik tubuhnya, seperti api liar yang membara di perut bawahnya setiap kali Reza condong dekat, tatapannya yang penuh gairah membuat putingnya tegang dan pahanya berdenyut samar, basah tipis yang licin seperti undangan untuk disentuh lebih dalam.
Membuatnya ingin menyerah, ingin merasakan tangan kuat itu menyusuri pinggangnya, napas maskulinnya di leher, dorongan yang akan memecah kepolosannya dengan kenikmatan yang dulu ia takuti. Reza adalah badai yang menggoda, yang membuat tubuhnya hidup, haus, seperti benih nafsu yang sudah bertunas di tanah alimnya.
Tapi di sisi lain, ada kenyamanan yang menenangkan hati. Ustadz Fahri, dengan mata teduhnya yang seperti pelabuhan aman, suaranya yang lembut seperti doa yang dibisikkan, membuat emosinya tenang, seperti akhirnya punya tempat bersandar setelah bertahun-tahun sendirian di Kairo.
Bersamanya, Alya merasa utuh, dicintai tanpa syarat – tak ada panas membara, hanya ada kehangatan yang membungkus luka-luka kecil di hatinya, membuat ia ingin curhat semuanya, ingin berpegang tangan dan berjalan di halaman pesantren tanpa takut jatuh. Fahri adalah cahaya yang stabil, yang membuatnya ingin tetap alim, tetap kuat, meski badai datang.
Perasaan campur aduk ini seperti dua sungai yang bertemu. Pertama sungai yang deras dan panas, menarik tubuhnya ke jurang kenikmatan gelap. Satunya lagi sungai yang tenang dan dalam, menahan hatinya di tepi yang aman.
Alya menatap cangkir tehnya, uapnya naik pelan seperti hembusan napasnya yang tak stabil, dan ia bertanya-tanya, berapa lama ia bisa bertahan di antara keduanya? Godaan fisik Reza membuatnya gelisah, kenyamanan emosional Fahri membuatnya takut kehilangan, takut godaan itu akan menelan cahayanya.
Ini seperti panggung yang disiapkan untuk tubuhnya, siap untuk eksplorasi yang lebih dalam, lebih intim, di mana batas alimnya akan diuji, dan hatinya akan memilih antara api atau air.
Bersambung…