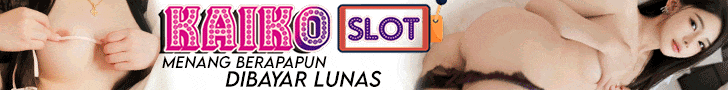Bahkan lalu Pak Mathias menjilati leherku ketika aku masih lemas karena baru habis orgasme. Namun gairahku bangkit kembali beberapa detik kemudian.
Gairah yang membuatku mulai berani untuk menciumi bibir Pak Mathias yang berkumis tipis itu. Bergairah untuk balas menjilati lehernya, dengan celucupan – celucupan mesra. Semesra mungkin. Karena aku akan menggantungkan masa depanku padanya.
Lalu… ketika penis Pak Mathias dibenamkan dan diikuti dengan pancaran spermanya yang bertubi – tubi, aku memejamkan mataku erat – erat. Dalam nikmat tiada taranya.
Lalu kubiarkan ia terkapar lemas di atas perutku.
Dan ketika ia mencabut penisnya dari liang sanggamaku, masih sempat aku bertanya lirih, “Bagaimana kalau hamil nanti Pak?”
“Hamil ya hamil aja. Dua minggu lagi juga kita kawin,” sahut Pak Mathias disusul dengan kecupan hangatnya di bibirku.
“Lho… bukannya Bapak mau ke luar negeri?” tanyaku.
“Diundurkan beberapa hari,” sahut Pak Mathias, “Karena aku ingin kawin dulu denganmu. Jadi, sepulangnya dari villa ini, nanti aku harus menjumpai ibumu. karena ayahmu sudah tiada kan?”
“Iya Pak. Tapi jangan diketawain nanti ya Pak. Rumah kami cuma rumah kecil dan sudah tua.”
“Siapa yang akan ngetawain? Kan aku sudah bilang, aku tidak butuh hartamu serupiah pun. Aku hanya ingin dirimu seutuhnya sebagai calon permaisuriku… “lagi – lagi Pak Mathias mencium bibirku dengan hangatnya, “Ohya… mulai sekarang panggil aku papie aja ya. Aku pun akan memanggilmu Mamie, meski Rina jauh lebih muda dariku.
Ucapan itu sangat membesarkan hatiku. Berarti dia tidak memasalahkan keadaanku yang tidak perawan lagi ini. Maka aku pun bertekad untuk tidak membahas masalah yang satu itu. Kecuali kalau dia menanyakannya.
Beberapa saat kemudian, aku sudah duduk di samping kiri Pak Mathias lagi, di seat belakang mobil mewahnya. Menuju rumahku. Dan aku sudah mengirim berita lewat handphoneku kepada Mama, bahwa Pak Mathias akan datang bersamaku. Entah untuk apa. Yang jelas aku minta agar Mama membersihkan dan menata rumah secepatnya, agar jangan terlihat berantakan.
Rumah Mama terletak di dalam gang yang tidak jauh dari mulut gang. Hanya sebuah rumah kecil yang sederhana.
Mama tampak senang sekali melihat kedatanganku bersama lelaki yang usianya lebih tua dari Mama. Seingatku usia Mama baru 45 tahun, sementara Pak mathias sudah 52 tahun menurut pengakuannya.
Tapi Pak Mathias mencium tangan Mama ketika baru dipersilakan masuk ke dalam ruang tamu yang sempit ini. Kemudian Pak Mathias mengatakan bahwa beliau berniat menikahiku paling lambat dua minggu lagi.
Untungnya Mama tidak kelihatan gugup. Dengan tenang Mama berkata, bahwa keputusannya terletak pada diriku sendiri, sedangkan Mama hanya bisa merestui saja apa pun keputusanku ini.
Pada saat Mama masuk ke dalam, untuk menyiapkan minum buat tamunya, Pak Mathias berbisik ke telingaku, “Nanti ajak mamamu ke rumah yang sudah kusediakan.”
“Rumah?” tanyaku heran.
“Ya. Rumah untuk Rina dan Mama. Jadi nanti akad nikahnya di situ aja. Aku takkan mengundang banyak orang, cukup dihadiri oleh tiga orang anakku yang ada di sini. Sedangkan anak – anak yang sedang kuliah di luar negeri, cukup dengan diberitahu saja.”
“Anak – anak Papie bakal setuju?” tanyaku.
“Mereka tak pernah membantah pada apa pun yang sudah kuputuskan.”
Sejam kemudian, aku dan Mama sudah berada di dalam mobil Pak Mathias yang mulai sekarang harus kubiasakan memanggilnya Papie, di jok belakang. Sementara Papie duduk di depan, di samping sopirnya.
Mobil Papie dihentikan di depan sebuah rumah yang cukup megah, meski tidak semegah rumah Papie yang laksana istana di jaman Romawi itu.
Di dalam rumah yang perabotannya sudah lengkap dan serba baru itu Papie berkata kepada Mama, “Kalau bisa, mulai besok Ibu dan Rina mulai pindah ke rumah ini. Rumah yang akan menjadi milik Rina ini. Jadi akad nikahnya pun kita laksanakan di sini saja. Setelah akad nikah, Rina akan dibawa ke rumah saya.
“Ada, “Mama mengangguk, “walinya paman Rina, adik kandung ayahnya.”
“Baguslah kalau ada walinya. Nanti kita tak usah bikin pesta ya Bu. Yang penting sah aja dulu. Soalnya dua hari kemudian saya harus terbang ke luar negeri. Mungkin Rina juga akan dibawa.”
“Keluarga Papi yang akan menghadiri akad nikah itu berapa orang kira – kira?”
“Mmm… sekitar tujuh orang saja. Mungkin keluarga Rina juga akan ada yang hadir kan?”
“Ada,” sahut Mama, “tapi takkan banyak. Sekitar sepuluh orang saja.”
“Nah… masalah catering pada hari akad nikah itu, biar saya yang atur semuanya. Ibu tak usah repot – repot.”
Kemudian Papie menyerahkan dua lembar cek, sambil berkata, “Itu untuk membeli baju pengantin dan sebagainya. Dan yang selembar lagi ini untuk membeli mobil besok. Supaya Rina jangan kelihatan kecil di mata keluargaku pada waktu mereka datang ke sini nanti.”
Lalu Papie berbisik di dekat telingaku, “Kalau ada lebihnya, kasihkan ke Mama aja.”
Aku mengangguk dengan tangan gemetaran. Karena kaget setelah melihat nominal yang tertulis di kedua lembar cek itu. Tak kusangka Papie sudah sebegitu seriusnya ingin memperistrikanku…!
Yang mengejutkan adalah laporan Mama keesokan harinya. Pada saat aku sedang berdandan untuk nyari mobil baru seperti yang disuruh oleh Papie kemaren, Mama menghampiriku. Dan berkata, “Kemaren siang, sebelum kamu pulang, Ricky datang.”
“Haa?! Mau ngapain dia?” tanyaku kaget.
“Dia mengadu sama mama.”
“Mengadu soal apa?”
“Mengadu karena hubungannya denganmu diputuskan olehmu. Dia sampai bercucuran air mata waktu mengadu kepada mama itu. Karena dia masih mencintaimu.”
“Terus Mama bilang apa?”
“Mama cuma berusaha menghiburnya. Mama bilang jodoh itu tidak bisa dipaksakan. Semoga saja dia takkan dendam padamu.”
“Ya… jangan sampai dia mengganggu rumah tanggaku setelah menjadi istri Pak Mathias nanti. Lagian seperti Mama bilang, hubunganku dengan Ricky tak jelas masa depannya. Untuk membayar cicilan motornya saja dia sering minjam uangku. Untuk beli rokok pun dia suka minjam duit padaku. Minjam – minjam yang tak pernah dibayar.
“Iya sih. Kalau hubunganmu dengan Ricky dipertahankan, paling juga dia bakal jadi benalu nantinya.”
Masalah Ricky pun langsung kulupakan. Karena aku sedang konsentrasi menghadapi pernikahanku dengan Papie nanti. Membeli mobil baru yang sangat kudambakan sejak lama, sebuah sedan matic berwarna merah metalik.
Memesan gaun pengantin. Membelikan pakaian untuk Mama dan sebagainya. Untungnya aku sudah trampil dalam mengemudikan mobil, karena waktu masih kuliah sering diajari oleh Destini, teman kuliahku yang sudah menjadi sahabat terdekatku di kampus.
Dengan dua lembar cek dari Papie yang sudah kucairkan, semua masalah keuangan tidak ada lagi. Bahkan setelah membeli segala perlengkapan untuk pribadiku dan untuk Mama, masih banyak sisa duitnya di dalam tabunganku.
Pada hari itu pula Mama kuajak pindah ke rumah megah hadiah dari Papie itu. Barang – barang di rumah Mama tidak perlu dipindahkan ke rumah megah ini. Rumah Mama pun cukup dengan dkikunci saja, kemudian Mama kubawa pindah ke rumah megah yang furniture segala peralatan elektroniknya sudah lengkap semua.
Hari demi hari pun berputar terus…
Dua hari menjelang pelaksanaan akan nikah, Papie mengajakku ke rumahnya yang laksana istana itu.
Ternyata kedua anak perempuan Papie beserta suaminya masing – masing sudah menungguku di sana. Papie pun lalu mengenalkan mereka kepadaku seorang demi seorang.
“Ini anak sulungku, Cinthia namanya. Dan itu suaminya bernama Walter,” kata Papie. Kemudian Papie menengok ke arah anak dan menantunya, “Mulai saat ini kalian harus memanggil Mamie padanya, yang dua hari lagi akan diresmikan sebagai istri papie.”
Kemudian Cinthia (yang usianya mungkin lebih tua dariku) berjabatan tangan denganku, lalu mencium pipi kanan dan pipi kiriku diikuti dengan bisikan, “Titip Papie ya Mam.”
Aku cuma menjawabnya dengan anggukan kepala sambil tersenyum.
Papi pun mengenalkan anak keduanya bersama suaminya, “Ini anak keduaku. Namanya Monica dan itu suaminya bernama Laurent. “Kemudian Papie menoleh ke arah anak kedua dan menantunya sambil berkata, “Kalian juga harus memanggilnya Mamie kepada calon istri papie ini.”
Monica dan suaminya pun menjabat tanganku disusul dengan cipika – cipiki. Pada saat cipika – cipiki denganku, Monica pun berbisik di dekat telingaku, “Semoga Mamie bisa membahagiakan Papie ya.”
Aku mengangguk lagi sambil tersenyum.
Kemudian Papi berseru – seru, “Boooy! Boyke !!!”
Terdengar suara cowok menyahut, “Yaaa… !”
Lalu muncul cowok yang kutaksir berusia 18 tahunan. “Ada apa Pap?” tanyanya.
“Ini kenalan dulu sama calon istri papie,” kata Papie sambil memegang pergelangan tangan cowok itu. Lalu menoleh padaku, “Kini anak bungsuku, Boyke namanya,” kata Papie. Sementara cowok bernama Boyke itu tampak cuek sekali. Memandang ke arahku pun tidak.
“Ayo jabatan tangan dulu dengan calon mamiemu itu,” kata Papie kepada anak bungsunya.
Cowok bernama Boyke itu menjabat tanganku sambil menunduk, kemudian pergi lagi meninggalkan kami yang masih berada di ruang keluarga ini.
Papie bergegas mengejar anak bungsunya, sementara anak sulung Papie yang bernama Cinthia itu menghampiriku sambil berkata perlahan, “Boyke memang begitu. Sejak ibu kami meninggal, Boyke jadi berubah. Jadi bandel sekali. Kuliah nggak mau, disuruh kerja di perusahaan Papie juga gak mau. Jadi kerjanya cuma makan, ngeluyur dan tidur.
Aku tidak berani menanggapi ucapan anak sulung Papie itu. Cuma mengangguk – angguk saja sambil tersenyum.
Kehidupanku laksana satelit yang diletakkan di hulu roket, lalu melesat ke angkasa biru sampai meninggalkan atmosphere bumiku. Segalanya langsung berubah drastis. Karena aku sudah menjadi Nyonya Mathias, yang memiliki segalanya.
Setelah menjadi istri Papie, aku terbiasa dipanggil Mamie oleh anak – anak tiri yang usianya lebih tua dariku. Begitu juga dengan suami mereka, yang lebih tua daripada istrinya masing – masing, aku senantiasa dipanggil Mamie. Seminggu setelah aku diresmikan sebagai istri Papie, kedua anak tiriku yang kuliah di Amerika dan Kanada pun datang.
Mereka mengucapkan selamat pada Papie dan juga padaku. Meski mereka hanya seminggu berada di Indonesia, mereka kelihatan sangat mendukung perkawinanku dengan ayah mereka. Aku pun jadi bisa membedakan mana anak tiriku yang ketiga dan keempat. Anak tiri yang ketiga bernama Bobby, kuliah di Kanada. Sementara anak keempat bernama Kent, kuliah di Amerika Serikat.
Kesimpulannya, keempat anak tiriku, baik yang tinggal di Indonesia, mau pun yang pada kuliah di Kanada dan Amerika, sama – sama merasa senang, karena ayah mereka telah memiliki pendamping, meski usiaku jauh lebih muda daripada ayah mereka.
Satu – satunya anak tiri yang sulit diajak berkomunikasi, adalah anak tiriku yang bungsu dan bernama Boyke itu. Bahkan kata “Mamie” pun tak pernah kudengar dari mulutnya.
Tapi aku berusaha untuk beradaptasi dengan anak tiriku yang bungsu itu. Karena Papie sering berkata, bahwa sikapnya memang berubah sejak ibunya meninggal dunia. Maklum tadinya Boyke sangat dimanjakan oleh ibu kandungnya almarhumah. Lalu setelah ibunya meninggal, Boyke seolah kehilangan pegangan yang paling disayang dan diandalkannya.
Setiap pagi Boyke meninggalkan rumah di atas motor gedenya. Lalu pulang setelah larut malam.
Pernah pada suatu pagi, ketika Boyke sedang menyantap sarapan pagi di ruang makan, aku mencoba mendekatinya. Ikut sarapan pagi di ruang makan.
Boyke melirik pun padaku tidak. Asyik saja makan roti bakar dan minum kopi susunya.
“Kamu tiap hari ke mana aja Boy?” tanyaku dengan nada lembut.
Boyke menyahut dengan ketus, “Bukan urusan Anda.”
“Nggak tertarik untuk kuliah seperti teman – teman sebayamu?” tanyaku, tanpa mempedulikan keketusannya.
Boyke menggeleng.
“Padahal sayang lho waktumu dibuang – buang begitu. Ilmu itu kan penting untuk masa depanmu…”
Belum lagi habis kata – kataku, Boyke berdiri sambil berkata, “Anda bukan ibuku. Jadi nggak usah ngasih ceramah padaku.”
Lalu ia meninggalkan ruang makan. Beberapa saat kemudian terdengar bunyi mesin motornya, yang lalu menjauh sampai hilang dari pendengaranku.
Aku cuma bisa menghela nafas panjang. Sepertinya sulit sekali berkomunikasi dengan anak tiriku yang satu itu. Sementara Papie sering berada di luar kota. Sehingga Papie mungkin tidak tahu kalau aku sering berusaha mendekati anak bungsunya, tapi selalu mentok dan membuatku nyaris putus asa.
Ketika aku mengadu kepada Papie tentang sikap dan perilaku anak bungsunya itu, Papie berkata, “Nggak usah dipikirin Boyke sih. Jangankan sama Mamie, sama aku aja sangat jarang berkomunikasi. Dia seperti hidup di alamnya sendiri. Tapi yang jelas, dia tidak nakal, apalagi jahat. Dia tidak pernah menghabiskan duitku untuk berfoya – foya dengan temannya.
Dia juga tidak banyak teman. Beberapa kali kusuruh satpam untuk menguntitnya, agar aku tau ke mana saja dia pergi. Ternyata dia hanya duduk sendiri di puncak bukit, tanpa seorang teman pun. Mungkin di puncak bukit itu hatinya terasa tenang, mungkin juga dia sedang mengenang ibunya yang sudah tiada. Yang jelas, dia tidak pernah cari gara – gara, baik di rumah mau pun di luar.
“Apakah dia suka memakai narkoba?” tanyaku.
“Tidak pernah, “Papi menggeleng, “jangankan narkoba, minuman keras pun tak pernah disentuhnya. Bahkan pernah kutawari minum bir waktu sedang malam tahun baru, dia menolaknya.”
“Jadi, “lanjut Papie, “pada dasarnya Boyke itu anak baik. Hanya saja dia sulit beradaptasi dengan kenyataan bahwa ibunya sudah tiada. Makanya sebagai sarjana psikologi, cobalah dekati dia terus. Bujuk dia agar mau kuliah, jangan cuma pergi hanya untuk menyendiri begitu.”
“Papie pernah membuijuknya agar mau melanjutkan pendidikannya?”
“Sering. Tapi dia selalu menolaknya. Buat apa kuliah bikin pusing aja… selalu begitu jawabannya. Makanya aku memilihmu karena selain cantik Mamie kan sarjana psikologi. Cobalah lakukan segala cara agar dia mau kuliah. Tapi harus ulet dan sabar. Lama – lama juga pasti luluh hatinya. Tentu saja dengan asesmen yang biasa diterapkan oleh para psikolog.
“Aku belum jadi psikolog Pap. Baru sarjana psikologi. Harus kuliah es-dua dulu baru jadi psikolog.”
“Tapi dasar – dasar psikologi kan sudah punya. Tentu Mamie punya trik untuk membujuk anak muda seperti Boyke agar tertarik untuk kuliah. Pokoknya lakukanlah segala cara, agar dia mau kuliah. Mamie pasti bisa.”
“Mmmm… hobby Boyke apa Pap?” tanyaku.
“Setauku hobbynya cuma main catur, dengarin musik dan mendaki bukit. Bukan mendaki gunung tinggi. Kalau sudah menemukan bukit yang indah pemandangan di sekitarnya, dia bisa seharian duduk di situ. Ohya… dahulu waktu masih di SMA, dia suka sekali memelihara ikan di aquarium. Senengnya cuma ikan kecil – kecil.
“Dia perokok ya Pap.”
“Ya. Tapi dia hanya merokok di luar rumah. Karena dia juga tau, merokok di ruangan berAC itu sangat tidak baik. Dan aku tak pernah melarangnya merokok. Karena aku sendiri sudah jadi perokok sejak masih di SMP dahulu.”
“Kebiasaan Papie itu jadi menurun kepada anaknya ya?”
“Iya. Biar sajalah kalau sekadar merokok gak apa – apa. Kalau dilihat dari umur, dia itu kan sudah dewasa. Tapi kelakuannya masih kayak abege.”
Ucapan – ucapan suamiku itu seolah indoktrinasi, bahwa aku harus ikut berjuang agar Boyke mau kuliah seperti teman – teman sebayanya. Dan yang terngiang – ngiang terus di telinga batinku adalah ucapan suamiku ini…
Pokoknya lakukanlah segala cara, agar dia mau kuliah. Mamie pasti bisa …
Aku sendiri merasa sudah menjadi bagian dari keluarga Mathias ini. Sehingga aku pun punya kewajiban untuk mendekati dan membujuk Boyke agar mau kuliah seperti cowok – cowok sebayanya.
Pada suatu hari, ketika suamiku sedang berada di luar negeri (dia memang sering sekali ke luar negeri untuk mengurus bisnisnya), aku semakin tersemangati anjuran suamiku, untuk membujuk Boyke dengan segala cara, agar ia punya semangat untuk melanjutkan pendidikannya di perguruan tinggi.
Mengingat salah satu hobbynya adalah main catur, aku sengaja membeli papan catur dan bidaknya yang terbaik dan termahal. Kemudian kuletakkan papan itu di meja kecil meja kecil yang dikelilingi sofa dalam kamarku. Dan kuletakkan bidaknya pada tempat yang semestinya sebelum permainan dimulai.
Kebetulan aku bisa juga main catur, meski tidak seberapa ahli.
Malamnya ketika terdengar derum motor Boyke memasuki pekarangan, aku pun bersiap – siap untuk menyambutnya dengan ajakan main catur di kamarku.
Di lorong menuju ke pintu kamar Boyke, aku menyambutnya, “Baru pulang Boy?”
Boy cuma menatapku sekilas, lalu mengangguk dan membuka pintu kamarnya. Pada saat itulah aku bertanya seolah – olah belum tahu bahwa main catur adalah salah satu hobbynya, “Bisa main catur Boy?”
Boy menoleh padaku, lalu mengangguk dengan suara nyaris tak terdengar, “Bisa…”
“Temenin mamie main catur yuk,” ajakku sambil memegang bahunya.
Boyke tidak menyahut. Cuma berdiri sambil memandang ke dalam kamarnya, yang pintunya sudah dibuka.
Tapi aku mendesaknya, “Boy Sayang, Papie kan lagi di luar negeri. Mamie jadi sulit tidur. Mendingan kita main catur sampai sama – sama ngantuk yuk.”
Boyke memandangku sekilas, lalu menunduk lagi sambil menyahut perlahan, “Mau mandi dulu.”
“Iya… iya… mandi dulu deh. Mamie juga mau mandi dulu. Mamie tunggu di kamar mamie ya.”
Boyke cuma mengangguk, lalu masuk ke dalam kamarnya.
Aku pun kembali ke dalam kamarku sambil memutar otakku.
Lalu aku benar – benar mandi, karena memang belum mandi sore.
Setelah mandi, kukenakan kimono sutera hitamku.
Pada saat itulah terdengar pintu diketuk dari luar. “Masuk aja, gak dikunci… !” seruku.
Lalu Boyke masuk ke dalam kamarku, dalam baju kaus dan celana pendek serba putih.
Aku pun duduk di sofa yang berhadapan dengan Boyke, sambil bertanya, “Mau putih atau hitam?”
“Mana aja,” sahutnya sambil memegang pion hitam di depannya. Diperhatikannya pion itu sambil bergumam, “Bagus sekali bidak caturnya.”
“Iya, sengaja mamie pilih yang paling bagus. Supaya kalau dibawa ke luar gak malu – maluin.”
“Dibawa ke luar? Ke dalam pertandingan antar grup maksudnya?”
“Bukan,” sahutku sambil melangkahkan pion putihku duluan, “Mamie sih maunya maen catur itu di luar. Di puncak bukit misalnya. Jadi kita bisa maen catur sambil menikmati segarnya udara bebas polusi. Apalagi kalau ada angin sepoi – sepoi meniup kita… pasti lebih nyaman lagi.”
“Mamie suka maen ke puncak bukit?” tanya Boyke. Inilah pertama kalinya Boyke memanggilku Mamie.
“Suka banget.”
Boyke melangkahkan pion hitamnya sebagai counter atas langkah pionku. “Sayang sekarang sudah malam,” ucapnya, “Kalau pagi – pagi bisa maen catur di puncak bukit. Tapi… Mamie gak keberatan kalau kubonceng di motorku?”
“Mauuu…” sahutku, “asal jangan dibawa ngebut aja. Ngeri soalnya, kalau jatuh dari motor pasti ada bekasnya di badan.”
“Aku jarang ngebut, kecuali kalau lagi ngejar waktu. Besok pagi aja kita ke puncak bukit ya Mam. Pakai motorku, bukan pakai mobil Mamie. Kalau pakai sedan, bisa rusak nanti sedannya, karena jalannya masih bergerinjal – gerinjal di antara bebatuan.”
“Iya. Mamie juga pengen ngerasain dibonceng sama Boy. Pasti menyenangkan dibonceng saama amnak kesayangan mamie,” sahutku sambil memijit hidung Boyke.
Lalu… untuk pertama kalinya aku melihat Boyke tersenyum.
Mudah – mudahan aja skenarioku akan berjalan sebagaimana mestinya.
Permainan catur di kamarku itu hanya berlangsung satu set. Boyke yang menang. Sengaja aku mengalah agar hatinya senang. Padahal kurasa masih bisa mengalahkannya kalau aku mau.
Lalu Boyke keluar dari kamarku setelah janjian akan membawaku ke puncak bukit sambil membawa papan catur dan bidaknya ke sana.
Esok paginya, kukenakan celana pendek corduroy berwarna biru tua, dengan baju kaus berwarna biru peacock. Sepatu yang kukenakan pun sepatju sport berwarna biru, agar matching dengan baju kaus dan celana pendekku. Aku pun membawa selimut tebal yang kumasukkan ke dalam ranselku. Sekalian membekal mantel panjang yang tidak tembus air, untuk jaga – jaga kalau turun hujan nanti.
Kuketuk pintu kamar Boyke sambil berseru, “Sudah siap Boy?”
“Sudah… !” sahut Boyke dari dalam, “Masuk aja… pintunya gak dikunci Mam… !”
Kulihat Boyke sudah mengenakan celana jeans dan baju kaus putih yang ditutupi dengan jaket jeans pula.
Aku pun melangkah ke belakang Boyke. Lalu memeluk Boyke dari belakangnya sambil berkata, “Sebenarnya mamie sayang sekali sama kamu Boy.”
Boyke seperti kaget pada awalnya. Tapi lalu menyahut perlahan, “Aku juga tak p;ernah membenci Mamie…”
Ucapan Boyke itu sangat berarti bagiku. Semoga skenarioku berjalan lancar, meski harus step by step.
Beberapa saat kemudian, aku sudah duduk di belakang Boyke, di atas motor gedenya. Aku baru mau mengenakan helm, masih sempat mengingatkan Boyke, “Jangan ngebut ya Boy. Santai aja.”
“Iya Mam,” sahut Boyke sambil mengenakan helmnya.
Kemudian Boyke meluncurkan motor gedenya ke jalan aspal. Aku pun memeluk pinggangfnya erat -erat, sehingga terasa sepasang toketku menghimpit punggungnya.
Tapi aku tidak mempedulikannya. Karena aku menganggap sedang bersama anakku sendiri, meski usia Boyke hanya tujuh tahun lebih muda dariku.
Dua jam kemudian kami sudah tiba di puncak bukit yang dituju. Puncak bukit yang sangat indah pemandangan di sekitarnya.
“Wooow… pemandangannya indah sekali Boy. Apakah pemilik bukit ini takkan menegur karena kita masuk ke sini tanpa izin?” tanyaku sambil melingkarkan lengan kananku di pinggang Boyke.
“Bukit ini kan punya Papie,” sahut Boyke.
“Ohya?! Mmm… kita mau ngapain aja di sini takkan ada yang berani negor dong,” ucapku sambil mempererat lingakaran lengan kananku di pinggang Boyke, karena udara di puncak bukit ini terasa dingin sekali.
“Emangnya Mamie mau ngapain?”
“Maen catur kan. “ Boyke terperanjat, “Mam! Kotak caturnya lupa! Gak dibawa !” serunya.
“Haaa?! Tapi biarin deh. Kita duduk – duduk atau rebahan aja di sini sampai siang…” kataku sambil mengeluarkan selimut tebal dari ranselku. Lalu menggelarnya di atas rumput yang rata, tidak ada lekuk – lekuknya.
Boyke tampak girang, “Wow! Mamie bawa selimut tebal itu…?!” serunya sambil duduk menyelonjorkan kakinya di atas selimut yang sudah kuhamparkan di atas rumput.
Aku pun duduk merapat ke sisi kiri Boyke sambil berkata, “Kalau sudah berada di puncak bukit begini, hati mamie terasa damai sekali Boy.”
“Kok Mamie sama dengan aku seleranya ya?” Boy menatapku dengan sorot “jinak”. Tidak cuek lagi. Ini pun sudah membesarkan harapanku, agar dia bisa mengikuti apa yang Papie inginkan.
“Iya… hobby mamie mungkin banyak yang sama denganmu. Memelihara ikan di dalam aquarium juga mamie suka.”
“Ohya?! Ooooh Mamie… ternyata hobby Mamie sama dengan hobbyku. Aku sayang sama Mamie, “cetus Boyke diikuti dengan kecupan hangatnya di kedua belah pipiku.
Lalu entah kenapa… aku menanggapi kecupan – kecupan di pipiku dengan kecupan hangat di bibirnya… sambil melingkarkan lenganku di lehernya, lalu merebahkan diri, sehingga wajah Boyke berada di atas wajahku, dengan bibir yang masih melekat di bibirku. Bahkan entah disengaja entah tidak, perutnya menghimpit perutku, dadanya pun menghimpit sepasang toketku yang kebetulan sedang tidak mengenakan beha.
Aku pun berusaha untuk mengikuti “irama” yang Boy inginkan. Ketika bibirnya terasa lekat menyedot bibirku, aku pun mulai melumat bibirnya dengan penuh kehangatan.
Lalu… entah apa yang timbul di dalam benak Boy, ketika ia balas melumat bibirku, sementara tangannya menyelundup ke balik baju kaus biru peacock-ku. Lalu memegang payudara kananku dengan mata terpejam – pejam.
Kubiarkan semuanya itui sebentar. Lalu kukeluarkan tangan Boy dari balik baju kausku, sambil berkata dengan lembut, “Jangan lewat batas Sayaaang…!”
“Ooo… oooooh… Mamie… maafin aku Mam… barusan aku merasa seperti dengan mendiang ibuku. Maaaf… jangan marah ya Mam…” ucap Boy sambil menundukkan kepalanya.
Aku pun membelai rambutnya dengan lembut, “Memangnya bagaimana perasaanmu terhadap mamie sekarang?”
Boyke tidak menyahut. Cuma menundukkan kepala sambil membiarkan rambutnya kubelai terus dengan lembut.
“Ngomong aja terus terang. Mamie takkan marah, asalkan kamu jujur menjawabnya. Bagaimana perasaanmu terhadap mamie sekarang ini?” tanyaku sambil mengepit kedua belah pipinya dengan kedua telapak tanganku.
“Mungkin barusan ada setan lewat Mam. Tiba – tiba aja aku merasakan hal yang aneh ini. Aku… aku jadi punya perasaan ingin memiliki Mamie…” sahut Boy dengan sikap seperti merasa bersalah.
“Sebenarnya hal itu wajar Boy. Karena kamu sudah mulai dewasa. Yang gak wajar adalah… mamie ini kan punya Papie.”
“Iya Mam. Aku mohon Mamie memaafkanku…”
“Dengar Boy… kalau kamu mau mendaftarkan diri ke perguruan tinggi pilihanmu, mamie akan mengikuti apa pun yang kamu inginkan. Asalkan kamu bisa merahasiakannya.”
“Haaa?! “Boyke menatapku dengan sorot bersemangat, “Serius Mam?”
“Serius. Mamie akan menganggapmu sebagai anak tercinta sekaligus kekasih tercinta. Asalkan kamu melanjutkan pendidikan ke universitas dan fakultas pilihanmu sendiri.”
“Mau Mam… mau…! Besok juga aku akan mendaftar ke sebuah universitas swasta. Aku mau daftar ke fakultas ekonomi aja ya Mam.”
“Terserah. Yang penting kamu sudah siap belajar, siap mengikuti pendidikanmu dengan serius. Kalau sudah seperti itu, setiap Papie nggak ada, mamie akan kasih ini nih,” sahutku sambil menurunkan celana pendek biru tuaku yang pinggangnya elastis, sehingga kemaluanku terbuka di depan mata Boyke.
“Mamie… ooooh… Mamie… !” Boyke berlutut di depanku, dengan mata nyaris tak berkedip, memandang kemaluanku seperti kafilah dahaga menemukan oase di tengah gurun pasir…!
“Mamie takkan ngasih memek mamie sekarang. Mamie hanya akan ngasih kalau kamu sudah kuliah, dengan nilai bagus pula. Kalau IPKnya di bawah tiga, jangan harap bisa terus – terusan bisa menikmati memek mamie.”
Boy malah menekan – nekan bagian di bawah perutnyha sambil menyeringai.
“Kenapa?” tanyaku.
“Ini punyaku… jadi pegel dan sakit Mam… sakit sekali…” sahutnya.
“Coba buka celananya… sembulkan tititnya… biar mamie bantu supaya gak pegel lagi,” sahutku bernada perintah.
Aku pernah mendengar bahwa kalau cowok sedang sangat bernafsu, lalu nafsunya itu ditahan – tahan, maka penisnya akan pegal – pegal. Testisnya pun ikutan pegal dan sakit.
Dan Boyke menurut saja. Celana jeans sekaligus celana dalamnya dipelorotkan, maka tersembullah penisnya yang tampak ngaceng sekali itu. Penis yang… waaaw… penis Boyke itu ternyata lebih panjang dan lebih gede daripada penis papienya…!
Bersambung…