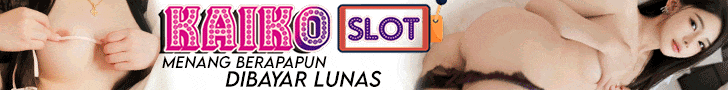Novel Melamar Santriwati – Jodoh itu rahasia Tuhan. Tak ada yang tahu dengan siapa dan kapan jodoh akan datang. Begitu pula dengan Ifah, seorang mbak ndalem yang harus menjalani skenario Allah yang berliku dalam urusan jodohnya.
“Semoga ustaz belum masuk!”
Langkah gadis kelas dua aliyah itu semakin cepat. Rok model sepan yang dia kenakan mau tidak mau membuat jangkauannya tidak begitu lebar.
Dengan napas ngos-ngosan, juga bulir keringat yang menghiasi kening, dia nyengir karena usahanya sia sia. Seorang lelaki berpeci hitam dengan kemeja polos kuning langsat dan bersarung coklat sudah duduk menghadap absen kelas.

Ngocoks Jari mengetuk pintu dan mengucapkan salam, santriwati yang merangkul kitab itu melangkah masuk. Wajahnya merunduk mendekati meja sang ustaz. Kembali dia mengucap salam lalu mengungkapkan alasan kenapa datang terlambat.
“Mohon maaf, Ustaz. Saya datang terlambat karena baru selesai membantu bu nyai membuat kue,” ujar gadis berjilbab putih itu seraya menunduk.
Lelaki yang disebut ustaz itu tanpa menoleh, berujar, “Bu Nyai itu orang yang disiplin dan pengertian. Beliau tahu kapan waktunya meminta tolong dan kapan santri harus masuk madin. Jadi alasanmu tidak bisa saya terima.”
Mulut gadis itu cemberut. Dia sudah tahu kalau alasan macam apa pun tak akan diterima oleh orang yang duduk di depannya. Ustaz yang dikenal sangat disiplin ketika mengajar. Walau belum genap satu tahun mengajar di kelasnya.
“Nama?”
“Ghina Ulya Syarifah.”
“Baik, salin pelajaran hari ini dua kali dan kumpulkan nanti malam maksimal pukul sembilan di kantor! Sekarang, duduklah! Kamu sudah membuang beberapa menit hak temanmu untuk belajar.”
Ifah, panggilan gadis itu nyengir karena ucapan sang ustaz. Juga tentang takzir yang harus dia kerjakan. Bukannya apa, ba’da salat Isya’, bu nyai menyuruhnya ke ndalem lagi. Maka tak akan ada waktu untuk mengerjakan takzir yang diberikan. Jadi … ifah berniat untuk menawar deadline pengumpulan takzir.
Karena Ifah masih bergeming, membuat sang ustaz berdehem.
“Masih kurang takzirnya?”
Terkejut, dia pun menjawab cepat, “Eh, cukup, Ustaz! Hanya sa-ja ….”
“Mau menawar?” potong sang lelaki itu cepat.
“Emm ….”
Belum sempat gadis itu mengungkapkan keinginan untuk mengundur deadline, ultimatum tak terbantahkan dia peroleh.
“Tidak ada tawar menawar untuk tugas saya. Sepertinya hal itu sudah pernah saya sampaikan di awal pembelajaran. Kamu belum terlalu tua untuk mengingatnya, bukan?”
“Injih, Ustaz.”
Dalam hati, Ifah ngedumel ingin protes, tapi percuma. Toh, dia tetap harus menerima apa yang disampaikan ustaznya. Peraturan tidak boleh datang terlambat memang sudah disetujui sejak awal. Tidak hanya dirinya yang mendapatkan takzir karena telat masuk kelas. Namun, beberapa teman sekelasnya juga pernah mengalami.
Bagi Ifah, ustaz satu itu terlalu kaku dalam menegakkan aturan. Seharusnya bisa lebih santai apabila alasan yang diberikan masuk akal. Susah payah dia merangkai alasan, tapi nihil hasilnya.
“Kenapa kamu telat, sih? Aku ‘kan sudah bangunkan tadi sebelum berangkat,” tanya Ilmi–sahabat Ifah–saat usai kelas madin.
“Habis bantuin bu nyai, disuruh makan di ndalem. Perut kenyang, badan capek, rebahan sebentar sudah lenyap. Saat kamu bangunin, aku langsung ke kamar mandi. Namun ternyata penuh. Ya sudah telat jadinya,” papar Ifah tak bersemangat.
“Rejekimu, Fah. Telat saat jadwalnya Ustaz Harun. Ustaz paling dingin plus killer.”
Ifah mengangguk lesu, berjalan dengan lunglai menuju kamarnya. Matahari semakin meredup. Awan pun mulai mengumpul. Burung-burung kecil bergerombol menuju peraduan. Suara qiraat dari toa masjid menjelang Magrib mulai menggema.
***
“Fah, kamu sudah selesai kerjakan takzir dari Ustaz Harun?”
Kedua sahabat itu kini berada di dapur ndalem untuk membantu membuat kue kering sejak ba’da Magrib.
“Belum nih. Sudah jam delapan. Duh, aku izin bu nyai saja, ya. Khawatir gak nutut kalau nunggu adonan habis.”
Obrolan kedua santriwati itu tak sengaja terdengar oleh sang empunya rumah. Bu nyai yang baru kembali dari menemui tamu, mengerti kegelisahan Ifah. Beliau seketika berujar, “Kamu kena takzir, Fah?”
“Eh, ngapunten, Bu Nyai. Sa-ya ….” Ifah terkejut dengan kemunculan tiba-tiba wanita berwajah mirip orang Arab itu.
“Siapa yang mentakzir kamu?”
“Emm … Us-taz … Ha-run.” Dia menjawab terbata karena malu.
“Oalaaahh … kok tumben. Yawes kamu berhenti saja! Segera kerjakan tugasnya. Tolong panggilkan mbak besar yang lain buat bantu di sini, ya.” Bu Nyai Zumaroh malah tertawa mendengar pengakuan Ifah. Dia merasa lucu sekaligus heran karena baru kali ini mendengar Ifah, santriwati yang rajin itu mendapat takzir dari ustaz yang super disiplin.
Tanpa babibu, gadis bersarung batik mega mendung itu segera pamit, meninggalkan adonan kue yang belum selesai dicetak. Setelah meminta seorang mbak besar untuk menggantikan tugasnya, Ifah segera mengerjakan apa yang diminta Ustaz Harun.
Beberapa bait di nadhom Alfiyah Ibnu Malik yang diajarkan di kelas tadi dia salin. Kebetulan atau entah kenapa makna lain dari baitnya membahas jodoh. Ifah mengingat kembali keterangan sang ustaz saat di kelas.
Dalam bait tersebut tersirat bahwa jodoh umumnya dari sama-sama kenal dan akrab. Namun banyak pula yang bertemu jodohnya tanpa diduga dan tanpa perkenalan mendalam sebelumnya. Adakalanya saling jatuh cinta pada pandangan pertama, lalu langsung melaju pada jalan pernikahan. Ada pula yang baru jatuh cinta setelah akad nikah.
Tanpa disadari, bibir gadis itu tertarik ke atas mengingat keterangan tersebut. Pikirannya menggembara. Seperti apakah jodohnya nanti? Apakah mereka akan kenal dan akrab terlebih dahulu? Atau kenal sekilas langsung menikah?
Atau bahkan dia tak akan mengenal jodonya sebelum mereka halal. Ah … Ifah lupa. Semua kakaknya menikah karena dijodohkan oleh orang tua. Jadi perjodohan sudah seperti tradisi di keluarga. Tak mungkin punya kesempatan untuk memilih jodohnya sendiri.
Membayangkan tentang jodoh, membuat waktu berjalan seolah semakin cepat. Sadar dari lamunannya, Ifah segera melanjutkan tugas agar tidak melampaui batas waktu yang ditentukan.
Setelah selesai, Ifah segera berjalan tergopoh menuju kantor asatid di ujung kompleks bangunan antara pondok putra dan putri. Sambil berharap tak mau kena takzir lagi. Ini harus menjadi yang pertama dan terakhir baginya. Dia tak mau orang tua mendapat laporan kalau anaknya di pesantren langganan kena takzir.
Melewati lorong yang becek karena hujan baru reda, langkah Ifah harus tetap cepat. Saat ekor matanya bisa menangkap sosok sang ustaz yang sedang mengunci pintu kantor, tiba-tiba sandal jepit yang dikenakan putus dan membuatnya terpeleset.
Suara tubuh yang jatuh, menarik perhatian Harun dan temannya. Sedangkan Ifah tak menghiraukan keadaan dirinya. Dia meringis melihat kertas tugasnya berceceran di lantai yang becek. Tugas yang dia salin dengan segala upaya sekarang telah lecek.
Harun dan temannya menghampiri untuk memastikan keadaan santriwati itu.
“Mbak gak papa?” tanya teman Harun khawatir.
Ifah tak kuasa mendongak. Berusaha menyembunyikan wajah agar tidak dikenali, dia menggeleng tanpa suara.
Mengerti akan jawaban yang diberikan, Harun menyahuti, “Kok bisa terjatuh, sih, Mbak? Perempuan itu jalannya pelan-pelan. Lagian ini sudah jam sembilan. Kok mau keluyuran!”
Ifah medumel dalam hati. ‘Orang jatuh bukannya dikasihani, malah diomeli. Ketusnya gak ilang-ilang!’
“Afwan Ustaz,” jawab Ifah lirih sambil berdiri dan masih tetap merunduk. Biar bagaimanapun dia harus bisa menjaga sikap.
“Mbak bukan santri baru yang mau kabur dari pondok ‘kan?” Harun menelisik karena heran melihat santriwati sendirian dan masih berada di luar kamar jam sembilan malam.
“Bu-bukan Ustaz. Sa-ya hanya mau ….” Ifah mengurungkan niatnya untuk memberitahu orang yang berdiri di depannya tersebut. Dia tidak siap jika ditertawakan karena kejadian memalukan itu.
“Hemm?”
“Afwan, saya hanya mau melancarkan hafalan nadhom di luar kamar. Tak tahunya terpeleset.” Alasan paling tepat saat ini yang bisa diberikan Ifah.
Harun memperhatikan kepala gadis yang masih menunduk itu. Sebagian sarungnya kotor. Tak ada tas ataupun dompet yang dia bawa. Hanya kertas bertuliskan huruf hijaiah yang berserakan di depannya. Dia berpikir bahwa alasan gadis itu masuk akal.
Harun menyayangkan, di saat dia sedang menunggu salah satu santri yang lalai mengumpulkan takzir, ada santriwati lain yang berjuang menghafal nadhom hingga terpeleset.
“Ya sudah, segera balik ke kamar karena gerbang pondok putri akan kami kunci sekarang!” pungkas Harun lalu melangkah menjauh bersama temannya.
Ifah tak tahu seperti apa warna wajahnya sekarang. Malu, kesal, sedih menjadi satu. Sebenarnya dia ingin mengatakan kalau mau mengumpulkan tugas yang diberikan. Namun, insiden itu membuatnya mengurungkan niat.
Ifah tak yakin kalau Harun mau menerima tugasnya yang sudah lecek dan basah. Jatuh di depan laki-laki membuatnya merasa sangat malu. Beruntung lampu tidak terlalu terang, sehingga dia yakin kedua lelaki itu tidak mengenalinya. Apalagi ustaz satu itu tak pernah memandang santriwati kalau bicara.
“Sampean kalau sama mbak-mbak, kok ketus ya, Kang,” ujar teman Harun saat mereka berjalan menuju pondok putra.
“Ketus piye?”
“Banyak yang bilang sampean cuek dan kalau ngajar killer.”
Bukannya marah, Harun justru tertawa.
“Kenapa kok tertawa?” protes lelaki bertubuh ceking tersebut.
“Sampean itu laki-laki kok ikut ngosip. Gini lho Kang, mbak-mbak itu kalau dikasih kendor saat ngajar, bisa-bisa aku yang kalah. Apalagi kelas aliyah sudah pinter ngojloki para ustaz yang masih muda.
Nah, aku gak mau jadi bahan ledekan mereka. Malu jenderal! Karena itu, jurus jitu menghadapi mereka ya macak kereng (bersikap killer) biar disegani.” Penuturan panjang lebar itu hanya ditanggapi bibir monyong oleh temannya.
“Ya gak papa macak kereng. Tapi awas nanti kalau gak laku. Hahahaa ….”
“Enak aja. Gini-gini banyak mbak-mbak yang kepincut. Wew.”
Ledekan demi ledekan mereka lontarkan sampai di dalam kamar pondok. Karena tidak ada alat komunikasi, kecuali para ustaz dan abdi ndalem yang diperbolehkan membawa ponsel, membuat interaksi sesama santri cukup akrab. Ponsel yang dimiliki Harun hanya dipakai saat ada acara keluar.
Kembali ke kamar setelah memungut kertas lembaran yang berserakan, Ifah segera tengkurap di ranjangnya. Ilmi yang baru pulang dari ndalem, bertanya-tanya melihat sahabatnya seperti itu.
“Kenapa, Fah?”
“Huwaaa … Ilmi ….”
“Kamu nih, ditanya malah nangis. Cerita, kenapa?”
Ifah duduk dan menceritakan kejadian yang barusan dialami. Bukannya simpati, Ilmi justru ngakak mendengarnya. Mendapat respons tak diharapkan, Ifah semakin bad mood.
“Lha kamu lucu. Kenapa pakai acara jatuh segala? Ini namanya sudah jatuh tertimpa tangga.” Ilmi masih saja cekikikan mendengar cerita sahabatnya itu.
“Orang jatuh bukan kemauanku. Wew! Kenapa sial banget, sih hari ini?”
“Astagfirullah, Fah. Kok ngomongnya gitu! Ambil hikmahnya saja.”
“Hikmah apa?”
“Hikmahnya kamu bakal dikenal Ustaz Harun sebagai santriwati yang jatuh di depannya. Bukan yang jatuh cinta, lho ya. Hahaha ….”
Ifah semakin cemberut mendengar ledekan Ilmi.
***
Azan Subuh kembali menyapa. Para santri dan santriwati diwajibkan bangun sebelum subuh. Kegiatan rutin di pesantren salah satunya adalah qiyamullail. Salat tahajud, salat witir, semaan al quran menjadi agenda mengawali hari. Begitu juga dengan Ifah dan teman-temannya.
Kali ini, rasa ngantuk masih menghinggapi gadis bermata bulat tersebut. Pasalnya, semalam dia lembur menyalin tugas yang telah basah dan lecek.
Pagi ini sebelum berangkat sekolah formal, Ifah berniat menyerahkan tugas tersebut kepada ustaznya agar tidak dinilai lepas tanggungjawab. Bersama Ilmi, dia mendatangi kantor asatid. Hanya ada satu ustaz di kantor tersebut, tapi bukan Harun. Terpaksa dia menitipkan tugasnya kepada ustaz tersebut.
“Semoga ustaz baru itu berbelas kasih mau menerima tugasku yang telat,” ujar Ifah lirih.
“Ifah ….” Suara teriakan salah satu temannya membuat gadis berseragam sekolah itu menoleh.
“Kenapa?”
“Bu Nyai pesan, sepulang sekolah kamu disuruh ke ndalem. Gus Amar sudah datang.”
Bersambung…