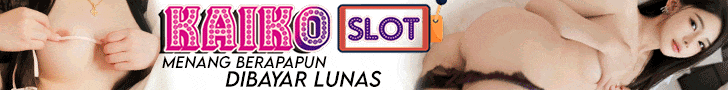“Njenengan beneran sudah dijodohkan?”
Pertanyaan gadis bergamis hitam itu membuat Amar sedikit tersentak. Dia tak menyangka akan mendapat todongan dari Ifah. Ternyata ucapan sang kakak di mobil tadi membuatnya penasaran. Haruskah lelaki itu menjawab yang sebenarnya?
Amar menarik napas sejenak lalu tersenyum memandang rimbunnya bunga matahari yang menghiasi sudut taman. Kedua ponakan sedang asyik main kejar-kejaran mengelilinginya. Sedangkan Ifah duduk di bangku kayu samping dia berdiri.
“Maunya sampean (kamu) bagaimana?”
“Kok balik tanya, Gus?”
“Daripada balik kucing. Hayoo ….” Amar mencoba mencairkan suasana dengan bercanda. Akan tetapi sepertinya percuma. Gadis itu terlihat murung.
Ifah tersenyum kecut, lalu berucap, “Saya ‘kan tanyanya serius, Gus.”
Amar meliriknya lagi. “Kenapa kok ingin tahu? Apa jawaban saya nanti ada hubungannya dengan sampean?”
“Maaf Gus. Saya lancang,” ucap Ifah lirih. Dia menyesal karena berusaha mengorek informasi tentang gus e.
Amar pun menyesal kenapa menjawab seperti itu. Sejujurnya dia ingin menggiring Ifah agar bisa menunjukkan responsnya. Dia punya keyakinan kalau gadis itu menyukainya. Melalui bahasa tubuh setiap bertemu, juga cara Ifah bertanya tentang perjodohan tadi, membuat Amar lebih yakin akan perasaan gadis itu kepadanya.
Tak ingin suasana menjadi canggung, Amar menjawab pertanyaan Ifah.
“Jodoh itu rahasia Tuhan. Manusia hanya bisa berencana tapi Allah yang menentukan. Namun Dia sudah memberi jaminan bahwa laki-laki baik adalah jodoh bagi perempuan yang baik. Begitu pula sebaliknya.
Kini … saya sedang berusaha menjadi baik agar Allah memberi saya pendamping yang baik pula,” jawab Amar tanpa melihat Ifah. Mereka berdua menatap tingkah bocah yang berkelakar ceria di depan mereka.
Mendengar jawaban seperti itu, membuat Ifah berhenti bertanya. Dia mengerti kalau pertanyaan itu salah. Tidak semestinya bertanya tentang privasi gus e. Barangkali memang benar bahwa Gus Amar sudah dijodohkan dengan seseorang yang tentu salihah.
“Maaf Gus kalau pertanyaan saya lancang,” ujar Ifah lirih.
Amar tersenyum kecut. “Mboten nopo, Mbak.” (Tidak apa-apa, Mbak.)
Keduanya menarik napas berat. Amar melirik sekilas gadis yang sedang menunduk dan memainkan ujung jilbab hijau botol bermotif abstrak yang dikenakan.
“Mbak Ifah sendiri apa sudah punya pandangan calon imam?” tanya Amar menelisik.
“Hah!”
Ifah terkejut sekilas tapi bisa cepat mengendalikan sikap. Kembali dia menatap ke depan dan menyunggingkan senyum hambar.
“Saya masih muda sekali, Gus. Belum lulus sekolah pula. Masih lama perjalanan ke sana,” tuturnya tetap dengan senyum hambar, lalu melanjutkan, “dalam keluarga saya, perjodohan sudah biasa. Kedua kakak saya menikah karena dijodohkan. Mungkin hal itu juga berlaku pada saya nanti.” Suaranya semakin melemah. Menahan sesuatu yang sesak di dalam hatinya.
Amar berpikir. Mereka sama-sama bakal dijodohkan. Andai saja perjodohan itu adalah antara mereka berdua. Sayangnya Amar belum tahu siapa gafia yang dijodohkan dengannya. Dia juga belum punya keberanian untuk bertanya tentang perasaan gadis di sampingnya tersebut.
“Apa sampean setuju dengan perjodohan?” tanya Amar kembali sambil memasukkan kedua jari ke saku jaket abu yang dia kenakan.
Ifah tersenyum sekilas dan mengedarkan pandangan ke sekeliling. Ada beberapa orang yang sedang duduk di bangku kayu. Sebagian mereka sibuk dengan ponselnya. Sebagian yang lain sedang mengobrol entah tentang apa.
“Saya tak bisa mengatakan setuju atau tidak. Namun, kita sebagai muslim tentu tahu larangan pacaran. Menurut saya salah satu ikhtiar orang tua untuk menyelamatkan anak-anaknya dari perbuatan itu adalah dengan menjodohkannya.”
“Kalau yang dijodohkan tidak cinta bagaimana? Bukankah itu zalim?”
“Cinta bisa hadir saat sudah halal, Gus. Kakak saya pun begitu. Mereka belum kenal sebelumnya. Namun sekarang anaknya sudah banyak. Hehee … bukankah itu artinya mereka saling mencintai walau sebelumnya tidak saling mengenal?”
Amar tersenyum sepintas. Dia meresapi apa yang diucapkan mbak ndalem itu. Pemikirannya simple tapi masuk akal. Namun, hati kecil masih belum sepenuhnya mendukung cara perjodohan yang sudah familiar tersebut.
Di saat kedua orang itu sedang sibuk dengan pikiran masing-masing, seorang pemuda memanggilnya dari belakang.
“Ngapunten, Gus Amar ditimbali pak kiai.” (Mohon maaf, Gus Amar dipanggil Pak Kiai.)
Amar menoleh dan mengangguk, lalu melangkah menjauhi taman tanpa sepatah kata pun. Meninggalkan seorang gadis yang menunduk dengan mata berembun. Menyisakan tanda tanya yang belum menemukan jawab pasti.
‘Allah akan memberikan yang terbaik. Siapa pun dia dan di saat yang tepat. Aku yakin,’ batinnya.
***
Tiga tahun sudah Ifah menempuh pembelajaran tingkat aliyah. Namun dia masih kerasan di pesantren untuk menghafal Al Quran. Setelah haflah, dia dijemput orang tua karena masuk masa liburan.
Terbiasa berinteraksi dengan Ifah, walau hanya melihat sosoknya saja, lalu sekarang tak bertemu, membuat Amar merasakan sesuatu yang berbeda. Dia tak tahu apakah itu namanya rindu. Sedangkan selama mengenal gadis itu, Amar berusaha menjaga hati. Perasaannya memang condong pada gadis itu, tetapi dia tak sanggup membantah keinginan orang tua.
“Nanti lebaran kita silaturahmi ke rumah teman ummah ya. Kamu ‘kan belum tahu anak perempuannya yang baru lulus. Ayu lan calon hafizah, cah e (cantik dan calon penghafal Al Quran, anaknya),” ajak Ummah Zumaroh di suatu pagi.
Amar hanya mengangguk pelan. “Monggo kerso, Ummah.” (Terserah, Ummah.)
Sebenarnya Amar ragu ingin menolak. Namun tak ada salahnya silaturahmi. Toh dia belum pernah bertemu dengan gadis yang ingin dijodohkan dengannya. Sejauh ini lelaki itu tak pernah mengungkapkan perasaannya terhadap Ifah kepada orang tua. Apa mungkin kalau dia utarakan, orang tuanya akan berubah pikiran tentang perjodohan itu.
“Ummah ….”
“Ummah, ada telepon dari Jombang.” Panggilan abah membuat Amar urung mengutarakan perihal Ifah.
“Kamu mau bicara apa?”
Amar menggeleng. “Ummah jawab teleponnya dulu.”
Wanita itu berlalu dari ruang tengah menuju kamar untuk menerima panggilan telepon. Dengan perasaan sedikit kecewa, Amar pun meninggalkan ruangan itu dan menuju masjid pesantren.
Sekalian dia mau melaksanakan salat Dhuha. Tak sengaja dia melihat Harun yang sedang murojaah (mengulang bacaan beberapa kali agar lancar dan terjaga hafalannya) hafalan Al Quran di sudut masjid.
Beberapa santri yang belum pulang, juga menjadikan masjid sebagai tempat kegiatan memperlancar hafalannya. Selesai salat, Amar menghampiri dan duduk di samping Harun.
“Nggak pulang, Kang?”
“Mboten, Gus.”
“Kenapa?”
“Mau posoan (puasa ramadhan) di pondok saja. Nanti pulang setelah bodo (hari raya Idul Fitri).”
“Oohh iya,” jawab Amar singkat.
Hening.
“Kang.”
“Nggih, Gus.”
“Boleh minta pendapat?”
“Monggo.”
“Ada seorang pemuda. Dia sudah dijodohkan oleh orang tua tanpa pernah bertemu satu sama lain. Dalam waktu dekat ini, rencananya mereka akan ditemukan.” Amar mulai bercerita. “Di satu sisi, pemuda itu memiliki perasaan khusus pada gadis lain yang sudah dia kenal.
Namun, dia juga tak pernah mengungkapkannya. Orang menyebutnya cinta dalam diam. Hehee ….” Amar tertawa kecil. “Menurut sampean apa yang harus dilakukan pemuda itu?” tanyanya melanjutkan.
Harun terdiam. Mencoba mengalisa apa yang disampaikan anak kiainya tersebut. Senyum tipis tercetak di bibirnya.
“Kalau saya yang jadi pemuda itu, pertama akan mengerjakan salat istikharah. Perasaan pada gadis lain yang belum tentu bersambut, bisa jadi adalah cara setan untuk menghalangi jalan kita. Ngocoks.com
Kalau hasilnya baik, tentu bakal manut sama orang tua. Saya yakin pilihan orang tua tak akan menjerumuskan anaknya. Apalagi orang tua yang mengerti agama. Paling tidak, mereka sudah tahu seperti apa perempuan yang cocok untuk dijadikan menantu.”
Harun menarik napas lalu melanjutkan. “Namun apabila belum sreg dan sudah punya pandangan lain, bisa diutarakan juga. Orang tua yang bijak pasti akan mempertimbangkan pendapat anaknya.”
Amar mengangguk. Itulah yang akan dia lakukan. Berusaha mengungkapkan apa yang ada dalam benaknya.
“Seumpama orang tua menyetujui pilihan pemuda itu, lalu datanglah dia ke rumah sang gadis. Ternyata ditolak. Bagaimana?”
“Siapa juga yang akan menolak sampean, Gus?” celetuk Harun dengan senyum lebih lebar.
“Lho, ini bukan kisahku, Kang.” Amar berkilah.
“Bukan sampean, tapi kok baper,” sahut Harun sambil tertawa.
Amar menggeleng sambil tertawa juga. Ternyata Harun bisa menebak siapa pemuda itu.
Bersambung…