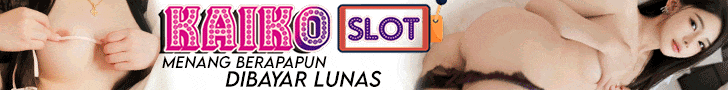“Mbak, bisa titip ini ke Bu Nyai?”
Seorang mbak ndalem yang sedang menyapu teras, menghentikan kegiatannya. Dia menoleh sejenak lalu menunduk, memerhatikan kresek putih besar yang dijinjing seorang pemuda.
“Apa itu … Kang?” tanyanya lirih. Dia bingung harus memanggil apa pada lelaki di depannya tersebut.
“Ini sayuran hasil kebun ibu. Keponakan saya ngaji di TPQ sini. Itu, Farida.” Lelaki berperawakan tinggi itu menunjuk seorang bocah usia enam tahunan yang sedang bermain bersama teman-temannya di halaman TPQ.
“Ooh … njih. Nanti saya sampaikan bu nyai. Terima kasih.” Mbak ndalem bersarung batik itu menerima uluran kresek besar tersebut dengan tangan bergetar.
Setelah kresek berpindah tangan, sang pemuda segera berlalu. Namun berbeda dengan perempuan yang barusan bicara dengannya. Dia cukup terkejut dengan pertemuan itu.
Bersyukur pemuda itu tidak mengenali lawan bicaranya.
Tersadar dari lamunan, gadis itu segera masuk dan menyerahkan pemberian tersebut kepada umminya. “Ummi, ada yang kasih ini, dari … keluarganya Farida anak TPQ.”
“Oh iya, alhamdulillah. Ibunya pernah kirim sayuran saat panen hasil kebun.” Ummi membuka kresek yang sudah diletakkan di atas meja. Ada kacang panjang, manisa, sawi, cabe dan tomat yang masih segar.
“Tadi yang ngasih laki-laki, Um. Dia bilang pamannya Farida,” ucap gadis itu hati-hati. Dia berusaha mengorek informasi dari umminya.
“Oohh iya,” sahut ummi sekilas sambil mengeluarkan sayuran tersebut dan meletakkan di tempeh bambu untuk dipilah.
“Emm … Ummi kenal sama keluarga Farida? Termasuk … pamannya?” Karena penasaran, gadis itu melanjutkan pertanyaannya.
“Mboten. Ya tahu sekedar wali santri saja.”
Gadis itu mengembuskan napas karena tak berhasil mendapatkan informasi yang dia inginkan. Perasaannya menjadi gelisah, entah kenapa. Sepertinya butuh waktu sendiri untuk menenangkan hatinya. Segera anak bungsu tersebut berpamitan ke kamar.
Ingatan gadis itu melayang ke waktu tujuh tahun lalu. Di mana segala rasa campur aduk menguasai hati. Sebuah fase kehidupan yang tak bisa dia hindari. Masa yang ingin dia lupakan. Akan tetapi karena kemunculan orang yang pernah berhubungan dengan masa lalunya tersebut, mau tak mau, gadis itu seolah ditarik kembali ke masa itu.
Namun dia bersyukur lelaki itu tidak mengenalinya. Biarkan gadis itu menjadi sosok baru, tanpa ada yang tahu manis getirnya perjalanan hidup sampai di titik sekarang. Biarkan masa lalu itu menjadi kenangan. Sesuatu yang tak bisa dihapus dalam perjalanan hidupnya. Bulir bening meluncur di pipi. Namun segera dia seka karena tak ingin terlarut dalam kenangan yang sudah susah payah dia kubur.
“Aku Ifah yang kuat! Aku punya Allah dan orang tua yang sangat sayang. Kenangan itu tidak boleh membuatku lemah kembali. Yah … senyum Ifah … senyum ….”
Sambil menghadap kaca, gadis itu bermonolog. Menata perasaannya agar tetap tegar menatap masa depan tanpa bayang-bayang kenangan.
***
“Sudah diberikan sayurannya ke bu nyai tadi?”
“Sampun, Bu. Saya kasihkan ke mbak ndalem yang sedang nyapu teras.”
“Oh iya sama saja,” sahut ibu singkat.
Bagi sang pemuda, itu adalah pertama kalinya dia melihat dari dekat dan berkomunikasi dengan mbak ndalem yang setiap sore selalu menyapu teras rumah induk pak kiai. Berpakaian khas anak pondok dan selalu menjaga pandangan dari ikhwan. Terlihat sosok sederhana tapi memiliki kharisma tersendiri.
Setelah kepergian bapak setahun lalu, pemuda berusia 32 tahun itu memutuskan untuk boyong dari pesantren. Ibunya tinggal sendirian. Kakak dan adik perempuan sudah berumah tangga dan tinggal di rumah masing-masing. Kakanya di luar kota, sedangkan sang adik tinggal di tetangga desa. Hanya dia laki-laki sau-satunya dan masih betah melajang.
Sejak kecil lelaki itu tinggal bersama sang nenek di Magelang karena kasihan tak ada anak cucu yang tinggal bersamanya. Setelah lulus MI dia mondok di kota yang sama dekat rumah sang nenek. Kemudian saat tamat MA, neneknya meninggal. Dia memutuskan untuk pindah nyantri di Kudus sampai bapaknya meninggal setahun lalu.
Lelaki itu masih menikmati masa lajangnya, walau sang ibu sudah sering menyuruh mencari jodoh. Bahkan ada tetangga yang terang-terangan ingin menjadikannya menantu. Namun belum ada yang sreg di hati.
Usaha rumahan menjahit sandal dan sepatu dari kulit yang ditekuni almarhum bapak sudah berjalan lumayan lancar. Namun di tangan pemuda itu, usahanya semakin berkembang. Dia memberdayakan para tetangga yang punya skill di bidangnya. Sedangkan sang ibu memang gemar berkebun. Beraneka sayur mayur dia tanam. Hasilnya dinikmati sendiri dan dibagi-bagikan ke tetangga.
***
“Le, kamu antarkan Farida ngaji, ya. Adikmu belum datang. Tadi pengasuhnya telepon,” ucap ibu di suatu sore.
Sudah sebulan terakhir, lelaki tersebut sering mengantar Farida mengaji karena ibunya dipindahkan ke tempat kerja yang lebih jauh.
“Pakde Harun kok lama jemputnya,” protes Farida saat lelaki itu baru tiba menjemputnya dengan motor.
“Maaf, pakde ketiduran. Ayo berangkat!”
Pondok pesantren yang dijadikan TPQ itu tidak terlalu jauh. Berada di desa sebelah yang dibatasi sawah terbentang luas. Lelaki bernama Harun itu pun baru-baru ini masuk kompleks pesantren. Dari kegiatan itulah, dia sering tak sengaja melihat mbak ndalem yang sedang menyapu teras. Entah kenapa, diam-diam dia menikmati pemandangan tersebut.
‘Ya Allah … semoga ini bukan godaan setan.’
Beberapa kali dia merasa bahwa seolah pernah mengenal mbak ndalem tersebut. Akan tetapi dia tak mengingatnya sama sekali. Mungkin saja saat bertemu di jalan. Entahlah … tetapi sepertinya tidak asing.
Sejak di pesantren, Harun tak pernah dekat dengan perempuan manapun. Fokusnya adalah menimba ilmu sebanyak-banyaknya. Sampai diminta mengajar diniyah di kelas santriwati juga tak pernah berniat tebar pesona dengan santriwatinya. Dia takut akan godaan memandang perempuan yang bisa melalaikan. Walau terlihat cuek pada perempuan, tetapi dia sosok yang menyenangkan dan mudah bergaul dengan teman-temannya.
Suatu hari, ibu mengajak Harun membicarakan perihal jodoh. Usia lelaki itu memang sudah waktunya berkeluarga. Usaha juga sudah mulai berjalan lancar. Sebagai anak laki-laki satu-satunya dan adik juga sudah menikah, ibu tentu menginginkan menantu yang baik agamanya dan mau tinggal bersama beliau yang sudah tak bersuami.
“Kamu mau carikan ibu menantu yang seperti apa, tho, Le?”
“Ya yang bisa membuat ibu senang,” jawabnya tersenyum.
“Jangan mikirin ibu terus. Cari perempuan yang sesuai keinginanmu. Nilam itu kan anaknya cantik, jilbaban, sudah ngajar walau honorer. Kurang apa, Le?”
Nilam adalah salah satu anak tetangga yang ingin dijodohkan oleh ibunya, tapi ditolak Harun.
“Iya, Bu. Nilam perempuan yang baik sepertinya. Namun saya belum sreg dengannya.”
“Belum sreg kan ada alasannya, Le. Mosok mung urung sreg tok? (Masak hanya belum sreg saja?)”
“Alasannya saya gak sreg sama Nilam itu karena … pernah melihat dia nongkrong berdua dengan laki-laki yang bukan saudaranya. Di rumah makan dekat alun-alun Mojoagung.”
“Ah, mosok?” Harun hanya menjawab dengan anggukan.
“Bisa saja itu temannya dan mereka sedang menunggu teman lain yang belum datang. Jangan ambil kesimpulan yang belum tahu sebenarnya, Le.” Ibu masih membela Nilam.
“Bisa jadi begitu, tapi bisa juga tidak. Namun, dari apa yang saya lihat, Allah sudah menunjukkan sesuatu sehingga hati ini tak bisa sreg memilihnya jadi pendamping hidup, Bu.”
“Mosok Nilam pacaran? Nanti ibu tanya ibunya ya.”
“Jangan Bu! Cukup kita saja yang tahu. Itu bukan urusan kita,” cegah Harun cepat. Dia tidak mau ibunya dinilai keluarga Nilam sebagai penyebar gosip. Hidup dengan masyarakat harus hati-hati menjaga lidah agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan.
“Terus piye? Kamu gak punya kenalan mbak-mbak pondok atau siapa gitu untuk jadi mantu ibu? Ibu kepingin kamu cepet nikah, Le.” Wajah wanita tua itu sendu. Benarkah ini saatnya dia serius mencari pendamping hidup?
Mbak-mbak pondok? Pilihan itu sepertinya yang tepat baginya. Selintas, pikiran Harun tertuju pada mbak ndalem di pondok tempat Farida mengaji. Setelah pergulatan batin yang dialami beberapa hari lalu, Harun sengaja salat istikharah. Selain untuk meminta petunjuk, juga agar hati ditentramkan jika perasaannya hanya fatamorgana semata.
Namun, bingung juga cara mendekati seorang mbak ndalem. Seorang santriwati sejati, tak mungkin mau diajak kenalan sembarangan. Mereka mampu menjaga marwahnya dengan lawan jenis.
Beberapa hari setelah pembicaraan pekara jodoh dengan ibunya, Harun menceritakan sosok yang dimaksud pada ibu.
“Bu, saya punya calon, tapi belum pasti karena belum tahu juga caranya,” ucap Harun ragu.
“Siapa?”
“Di pondok Darul Falah ada seorang mbak ndalem yang kerap terlihat nyapu rumah pak kiai saat saya antar Farida ngaji. Saya bicara dengannya hanya saat mengantar sayur ke bu nyai kala itu.” Ngocoks.com
“Mbak ndalem?” tanya ibu semringah.
Harun mengangguk. “Njih.”
“Ibu setuju saja. Ibu dulu kan seorang mbak ndalem di pondok. Kenal bapakmu juga karena diajak bu nyai belanja di kios pasar eyangmu. Bapakmu sering bantu di sana. Jadi lama-lama diajak nikah. Hihii … duh kok ibu malah cerita masa muda.”
Wanita tua itu tersenyum malu menceritakan masa perkenalan dengan suaminya. Cerita sederhana tapi bertahan sampai maut memisahkan. Tak ada yang merasa unggul dan saling menerima kelebihan dan kekurangan masing-masing. Itulah cinta sejati.
Harun ikut tersenyum membayangkan kisah cinta orang tuanya dulu.
“Wes, balik bahas mbak ndalem tadi.” Setelah mengusap ujung matanya, ibu kembali bersua.
“Ya begitulah, Bu. Pandangan saya ke mbak ndalem itu cocok. Namun … saya tak tahu bagaimana cara mendekatinya,” ungkap Harun lirih.
Keduanya terdiam beberapa saat. Lalu sang ibu berujar, “Mintalah dia pada pak kiai. Biasanya kalau yang meminta kiainya, para santri akan setuju. Sebab pak kiai tak mungkin menjodohkan asal para santrinya.
Pasti ada usaha lahir batin yang beliau lakukan untuk menerima atau menolak lamaran yang datang.” Penuturan ibu membuat Harun sedikit lega. Setidaknya dia tahu cara yang tepat untuk melangkah.
“Njih, Bu. Mohon doanya. Insya Allah hari Jumat mau sowan ke pak kiai,” ucap Harun menyanggupi. Ibu tersenyum sambil mengangguk pelan.
“Rida ibu untukmu, Le.”
Bersambung…