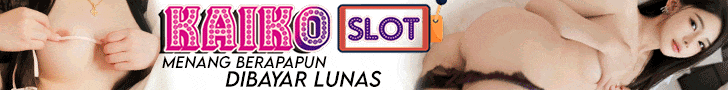Mencari pasangan tulang rusuk membutuhkan usaha lahir dan batin. Begitu pula dengan yang sedang dilakukan Harun. Pertemuan sekilas dengan seorang perempuan telah mampu memantapkan hatinya untuk mencari kepastian.
Santriwati itukah kiranya pasangan tulang rusuk yang ditakdirkan untuk melengkapi hidupnya?
Roda motor berhenti di pelataran pesantren pada Jumat malam. Dada pemuda itu dag dig dug tak karuan saat kaki mulai melangkah mendekati bangunan di tengah kompleks. Sederhana tetapi cukup asri dengan banyak tanaman yang menghiasi teras.
Dia ingat saat berbicara dengan mbak ndalem di teras ini beberapa waktu yang lalu. Wajah menunduk dengan tangan sedikit gemetar saat menerima pemberiannya. Dari situ Harun bisa menyimpulkan kalau mbak ndalem tersebut jarang berkomunikasi dengan ikhwan.
Seorang lelaki muda yang membukakan pintu. Lelaki bersarung itu mempersilakan masuk dengan ramah setelah Harun mengatakan ingin sowan pada kiai. Sepertinya dia kakang ndalem yang biasa membantu di rumah kiai.
Harun menunggu sekitar lima menit di ruang tamu tanpa sova. Hanya beralas karpet dan sebuah meja kayu pendek ukuran 1x1m yang diletakkan di sudut ruang. Tatanan khas ndalem kiai agar mudah menerima tamu dalam jumlah banyak.
“Sepertinya saya baru kali ini melihatmu,” ucap Kiai Rahman, pria berusia sekitar enam puluh tahunan. Beliau terkenal bijak dan ramah pada sesama.
“Njih, Yai. Maaf karena baru kali ini sowan Panjenengan (bertamu pada Anda),” jawab Harun takzim. Dia berusaha bersikap biasa saja walau dalam hatinya dag dig dug tak karuan.
Kiai Rahman mangangguk pelan dengan senyum simpul di sudut bibirnya. “Ada maksud apa kamu ke mari?”
Mendapat pertanyaan langsung seperti itu, tak ayal membuat pelipis Harun dibanjiri keringat. Padahal tadi dia sudah menyiapkan kalimat agar tidak grogi. Namun apalah kini, kenyataannya melamar anak orang memang membutuhkan persiapan mental yang matang.
“Eemm … pertama, saya ingin silaturahim dengan Panjenengan. Nama saya Harun Ar Rosyid. Warga kampung sebelah, tetapi baru setahun ini tinggal di rumah.
Sebelumnya di Jawa Tengah,” tutur Harun hati-hati lalu melanjutkan, “maksud saya yang kedua … sa-ya … ingin meminta bantuan Pak Kiai untuk … meminang mbak ndalem yang setiap hari menyapu teras ndalem ini,” lanjutnya dengan suara bergetar.
Ini pengalaman pertama bagi Harun melamar seorang perempuan. Sendirian. Pada kiainya. Bukan hal mudah bisa mengeluarkan apa maksud hatinya seperti ini. Butuh keberanian ekstra karena menyangkut masa depan kehidupannya.
Kiai Rahman termenung sejenak, lalu menarik napas dengan kepala mengangguk pelan beberapa kali.
“Jadi mbak ndalem yang setiap hari nyapu teras?” Harun mengangguk. Sang kiai masih memandangnya dengan intens.
“Baiklah, nanti kutanya ummi, siapa orang yang kamu maksud. Di sini ada beberapa santriwati yang membantu ndalem.”
Rasa deg-degan yang tadi menyergap Harun, menjadi sedikit mencair karena sikap ramah dan terbuka Kiai Rahman menyambut niat baiknya.
“Njih, Pak Kiai. Matur suwun sanget.”
Rasanya sedikit plong hati Harun setelah memberanikan diri mengungkapkan maksud hati pada pria berpeci putih itu.
Suasana hening sejenak. “Kamu mondok di mana sebelumnya?” tanya Kiai Rahman.
“Saya lulusan ponpes Al-Hidayah Kudus. Boyong setahun lalu karena bapak tiada dan tak ada saudara yang menjaga ibu,” jelas Harun sedikit rileks karena sudah melewati masa menegangkan sebelumnya. Obrolan sekarang sudah kembali normal seperti orang bertamu pada umumnya.
“Kiai Mustofa?” Pak kiai menebak nama pengasuh pesantren tempat Harun nyantri.
“Njih, leres Pak Kiai.”
Mendengar jawaban Harun, beliau hanya mengangguk-angguk. Sebagai sesama kiai, tentulah mudah mengenal karena sering menghadiri acara yang sama.
“Baiklah, Jumat depan salat di sini saja. Insya Allah sudah ada jawabannya ba’da salat Jumat.”
Dalam hati Harun bersyukur walau belum mendapat jawaban langsung, setidaknya dia sudah berusaha mencari pasangan tulang rusuk melalui pak kiai. Berharap semoga jawaban terbaik yang didapatkan.
Sepeninggal Harun, istri Kiai Rahman menghampiri ke ruang tamu.
“Siapa tadi, Bah?”
“Pemuda desa sebelah. Dia … mau melamar mbak ndalem yang biasa nyapu teras setiap sore.”
Bu nyai terkesiap mendengar jawaban suaminya. “Abah tidak bilang kalau ….” Belum sempat beliau melanjutkan kalimatnya, sang suami sudah menggeleng.
“Nanti malam kita salat istikharah. Besok abah akan cari tahu tentangnya.”
Setelah mengatakan hal itu, Kiai Rahman meninggalkan istrinya yang masih tertegun. Entah apa yang ada dalam benaknya saat itu.
***
Fajar menyingsing menyinari bumi yang masih basah karena sapuan lembut air langit semalam. Kegiatan di PP Darul Falah sudah menggeliat. Kesibukan tiga ratus lebih santri di pesantren itu membuat suasana pagi yang dingin terasa hangat.
Setelah selesai mengisi ngaji pagi, Kiai Rahman meminta Ifah untuk bicara di ruang tengah. Di dapur sudah ada beberapa mbak ndalem yang membantu memasak. Kegiatan rutin yang Ifah lakukan bersama mbak ndalem lainnya.
“Nduk, semalam ada seorang pemuda yang ingin melamar mbak ndalem yang setiap sore menyapu teras rumah ini,” ujar Kiai Rahman.
Gadis bergamis itu tersentak. Siapa gerangan pemuda yang dimaksud kiai? Kenapa ucapannya berbeda dengan lamaran sebelum-sebelumnya? Mbak ndalem? Menyapu teras?
“Siapa namanya, Bah?”
“Harun Ar Rosyid.”
Bagai tersengat tegangan tinggi. Ifa membisu dengan mata terbelalak. Seolah tak percaya dengan apa yang diucapkan kiai.
“Harun Ar Rosyid siapa, Bah?” tanya Ifah meyakinkan. Bisa jadi hanya kesamaan nama saja.
“Dia sering melilatmu menyapu teras setiap sore. Pemuda desa sebelah, lulusan PP Al Hidayah Kudus.”
Kali ini tidak hanya tersentak, tapi Ifah refleks menutup mulutnya yang mengangga karena tak percaya.
‘Ustaz Harun? Jadi … benar Ustaz Harun yang melamarku? Ya Allah … skenario apa lagi yang Engkau rancang untukku?’ batinnya bersua.
“Kamu mengenalnya? Bukankan kalian pernah satu pondok?”
Ifah masih terdiam. Apakah dia harus jujur siapa Harun sebenarnya?
Ifah mengangguk pelan. “Njih, Bah. Saya mengenalnya … tapi tidak banyak. Beliau guru saya saat kelas dua aliyah. Kadang juga bertemu saat diutus bu nyai nyupiri mobil pas ada acara ke luar,” tutur Ifah apa adanya.
Kiai Rahman hanya mengangguk. Membiarkan Ifah bercerita tentang siapa Harun yang melamarnya. Dia ingin tahu seberapa jauh mereka mengenal.
“Menurut kamu Harun bagaimana orangnya?”
Ifah kembali menunduk. Matanya memejam dan ingatannya terbang ke masa tujuh tahun silam. Mencoba mengingat kembali sosok yang ditanyakan Kiai.
“Setahu saya Uztaz Harun orang yang baik. Banyak yang bilang beliau orang yang dingin. Bicara seperlunya. Namun anggapan itu muncul karena beliau selalu menjaga pandangan dari perempuan. Saat mengajar pun demikian. Beberapa hari yang lalu saat memberi sayuran dan saya yang menerima. Sepertinya … beliau tidak mengenali saya.”
Kembali Kiai Rahman mengangguk. Dia bisa mengambil kesimpulan seperti apa sosok Harun, terutama di mata Ifah.
“Kamu mau menerima lamarannya?”
Ifah kembali menegang. Apa yang harus dia jawab. Harun memang orang baik, tapi dia berhubungan dengan masa lalunya yang sudah susah payah dilupakan. Apa harus, dia hidup di lingkup kenangan selamanya?
Melihat Ifah yang hanya terdiam menunduk tanpa jawaban, Kiai Rahman bisa mengerti keadaan hatinya. Dia orang yang demokratis dan tidak suka memaksa. Apalagi masalah jodoh. Anak-anaknya menikah dengan calon yang dia berikan, bukan berarti harus diterima secara mutlak. Namun mungkin sudah jalan jodoh, mereka langsung klik dengan lelaki yang dicalonkan.
Begitu pula dengan Ifah. Dia tak mau memaksanya menerima Harun. Apalagi Harun pernah satu pondok dengan Ifah yang otomatis akan mengingatkannya dengan kenangan lama saat mondok di sana.
3
“Abah tidak memaksamu menerima lamarannya. Masih ada waktu satu minggu untuk memutuskan. Lakukan ikhtiar batin sesuai syariat! Jumat besok dia akan ke sini lagi. Kalau kamu menolaknya, berikan alasan yang tepat. Namun jika kamu tidak punya alasan menolak, diammu abah anggap persetujuan.”
“Eemm … kenapa Abah memberi waktu hanya seminggu? Bukankah itu terlalu cepat untuk mengambil keputusan. Apalagi ini pekara jodoh. Sekali seumur hidup.”
“Pekara baik jika ditunda terlalu lama, setan yang akan berkuasa.”
Ifah masih tertunduk mencerna ucapan abahnya. Banyak hal yang berkecamuk dalam pikirannya. Menerima Harun artinya dia harus membuka kembali kenangan yang sudah ditutup rapat. Untuk menolak? Dia butuh alasan yang tepat agar bisa diterima abahnya.
***
Selama hampir seminggu Ifah mencoba meminta petunjuk Allah di sepertiga akhir malam. Selain ummi, hanya kepada-Nya dia bisa mencurahkan apa yang ada dalam hati.
“Ikuti kata hatimu, Nduk. Umi dan abah hanya bisa mendoakan yang terbaik untukmu. Percayalah hati tak akan berbohong. Sebesar apa pun kamu mengelak, jika hati kecilmu menerima, itulah yang sejujurnya kamu inginkan.”
Nasihat ummi semalam membuat Ifah semakin tergugu di atas sajadah. Dia memang ingin menolak, tapi kata hatinya seolah tak membenarkan. Berusaha mencari alasan yang tepat pun tak bisa. “Karena tak cinta.” Apa abahnya akan menerima alasan klasik semacam itu? Ah … dia rasa itu tak berguna.
Dalam hening malam, dia ingat dengan sahabatnya di pesantren. Ilmi. Sudah lama mereka tak bersua walau melalui jaringan.
“Ilmi ….” Kata pertama yang keluar setelah salam.
“Masya Allah … Ning sombong yang gak pernah telepon. Mimpi apa pagi-pagi namaku dipanggil. Hehee ….” Suara di seberang menjawab dengan bercanda.
Setelah bertanya kabar dan kangen-kangenan, Ifah menceritakan apa yang terjadi pada dirinya. Ibu dua balita itu malah menanggapi dengan bercanda.
“Jadi aku tahu kenapa dulu Ustaz Harun dingin macam kulkas berjalan. Ternyata dia sedang jaga image di depan kamu, Ning.”
“Jaga image bagaimana? Orang pas kami bertemu dia tak mengenaliku, kok. Saat kita kenal dulu memang begitu orangnya. Namun kemarin ketemu itu memang lebih ramah. Sedikit saja.”
“O ya jelas … dia kan ada mau melamar kamu. Kalau masih bersikap dingin aja, ya gak bakal ada yang mau.”
“Ish … kamu ini. Jadi bagaimana? Aku harus kasih jawaban apa sama abah?”
“Gini lho, Ning. Yang lalu biarlah berlalu. Sekarang kamu hidup di masa tujuh tahun setelah hatimu porak poranda. Istilahnya anak sekarang, move on gaess. Sambut masa depan yang lebih baik. Jangan mau dikurung belenggu kenangan.
Ustaz Harun dan Gus Amar itu orang yang berbeda. Walau mereka pernah dekat, bukan berarti sifatnya sama. Ikuti saja kata hatimu. Apakah hati kecilmu lebih condong ingin menerima atau menolaknya. Kamu sendiri yang tahu jawabannya. Jujurlah sama hatimu!”
Nasihat panjang lebar yang diberikan Ilmi memberikan efek luar biasa bagi perasaan Ifah. Dia merasa beruntung punya sahabat yang tak pernah jaim dan mau menasihati dengan jujur.
***
Hari yang ditentukan tiba. Sebelum berangkat, Harun berpamitan dan mencium tangan ibu untuk memohon restu. Senyum di wajah wanita tua itu membuatnya merasa tenang.
“Kalau jodoh, akan dimudahkan, Le,” tutur beliau saat Harun berpamitan.
“Njih, Bu. Insya Allah.”
Lelaki itu sengaja datang lebih pagi ke masjid pesantren untuk menderas beberapa lembar ayat suci. Sebelum seorang santri putra mendatangi dan mengatakan bahwa pak kiai menyuruh dia ke ndalem. Dalam hati, Harun sempat bertanya-tanya, ‘Kenapa sekarang? Bukankah beliau bilang ba’da jumatan?’
Mengabaikan beberapa pertanyaan yang menghinggapi, Harun berjalan mengikuti kang santri tersebut. Di ruang tamu, pak kiai sudah duduk menyambutnya. Setelah mengucap salam dan mencium tangan beliau, Harun dipersilakan duduk di depannya.
“Nak Harun, aku mau minta tolong badali khotbah. Badanku agak meriang sejak semalam,” dawuh pak kiai membuat lelaki muda itu terkesiap.
Bagaimana bisa tiba-tiba beliau meminta Harun untuk badali khotbah? Bukankah banyak ustaz pengajar di sini yang bisa badali? Kenapa memintanya yang notabene orang luar? Pertanyaan demi pertanyaan berseliweran membuat Harun merasa bingung.
“Kenapa harus saya, Pak Kiai?”
“Kalau kamu mampu, kenapa harus orang lain?”
“Saya hanya santri biasa, dulu. Ilmunya masih sedikit.”
“Wes lah, gak usah merendah. Sekarang bersiap-siaplah. Nanti ba’da salat, ke sini lagi. Ummi sudah dapat jawaban dari mbak ndalem yang kamu maksud.” Penuturan pak kiai membuat jantung lelaki itu semakin riuh berdetak. Tadinya sudah tenang saat mendapat restu ibu, kini mulai berdebar tak karuan lagi.
#Melamar_Mbak_Ndalem (8)
Mencari pasangan tulang rusuk membutuhkan usaha lahir dan batin. Begitu pula dengan yang sedang dilakukan Harun. Pertemuan sekilas dengan seorang perempuan telah mampu memantapkan hatinya untuk mencari kepastian. Santriwati itukah kiranya pasangan tulang rusuk yang ditakdirkan untuk melengkapi hidupnya?
Roda motor berhenti di pelataran pesantren pada Jumat malam. Dada pemuda itu dag dig dug tak karuan saat kaki mulai melangkah mendekati bangunan di tengah kompleks. Sederhana tetapi cukup asri dengan banyak tanaman yang menghiasi teras.
Dia ingat saat berbicara dengan mbak ndalem di teras ini beberapa waktu yang lalu. Wajah menunduk dengan tangan sedikit gemetar saat menerima pemberiannya. Dari situ Harun bisa menyimpulkan kalau mbak ndalem tersebut jarang berkomunikasi dengan ikhwan.
Seorang lelaki muda yang membukakan pintu. Lelaki bersarung itu mempersilakan masuk dengan ramah setelah Harun mengatakan ingin sowan pada kiai. Sepertinya dia kakang ndalem yang biasa membantu di rumah kiai.
Harun menunggu sekitar lima menit di ruang tamu tanpa sova. Hanya beralas karpet dan sebuah meja kayu pendek ukuran 1x1m yang diletakkan di sudut ruang. Tatanan khas ndalem kiai agar mudah menerima tamu dalam jumlah banyak.
“Sepertinya saya baru kali ini melihatmu,” ucap Kiai Rahman, pria berusia sekitar enam puluh tahunan. Beliau terkenal bijak dan ramah pada sesama.
“Njih, Yai. Maaf karena baru kali ini sowan Panjenengan (bertamu pada Anda),” jawab Harun takzim. Dia berusaha bersikap biasa saja walau dalam hatinya dag dig dug tak karuan.
Kiai Rahman mangangguk pelan dengan senyum simpul di sudut bibirnya. “Ada maksud apa kamu ke mari?”
Mendapat pertanyaan langsung seperti itu, tak ayal membuat pelipis Harun dibanjiri keringat. Padahal tadi dia sudah menyiapkan kalimat agar tidak grogi. Namun apalah kini, kenyataannya melamar anak orang memang membutuhkan persiapan mental yang matang.
“Eemm … pertama, saya ingin silaturahim dengan Panjenengan. Nama saya Harun Ar Rosyid. Warga kampung sebelah, tetapi baru setahun ini tinggal di rumah.
Sebelumnya di Jawa Tengah,” tutur Harun hati-hati lalu melanjutkan, “maksud saya yang kedua … sa-ya … ingin meminta bantuan Pak Kiai untuk … meminang mbak ndalem yang setiap hari menyapu teras ndalem ini,” lanjutnya dengan suara bergetar.
Ini pengalaman pertama bagi Harun melamar seorang perempuan. Sendirian. Pada kiainya. Bukan hal mudah bisa mengeluarkan apa maksud hatinya seperti ini. Butuh keberanian ekstra karena menyangkut masa depan kehidupannya.
Kiai Rahman termenung sejenak, lalu menarik napas dengan kepala mengangguk pelan beberapa kali.
“Jadi mbak ndalem yang setiap hari nyapu teras?” Harun mengangguk. Sang kiai masih memandangnya dengan intens.
“Baiklah, nanti kutanya ummi, siapa orang yang kamu maksud. Di sini ada beberapa santriwati yang membantu ndalem.”
Rasa deg-degan yang tadi menyergap Harun, menjadi sedikit mencair karena sikap ramah dan terbuka Kiai Rahman menyambut niat baiknya.
“Njih, Pak Kiai. Matur suwun sanget.”
Rasanya sedikit plong hati Harun setelah memberanikan diri mengungkapkan maksud hati pada pria berpeci putih itu.
Suasana hening sejenak. “Kamu mondok di mana sebelumnya?” tanya Kiai Rahman.
“Saya lulusan ponpes Al-Hidayah Kudus. Boyong setahun lalu karena bapak tiada dan tak ada saudara yang menjaga ibu,” jelas Harun sedikit rileks karena sudah melewati masa menegangkan sebelumnya. Obrolan sekarang sudah kembali normal seperti orang bertamu pada umumnya.
Penulis: Ellinda
TAMAT