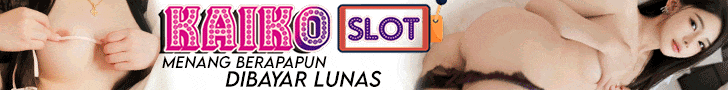AYO BERCERAI
“Aku mau tinggal di rumah Ibu.”
Pergerakan Sabda mengancingkan kemejanya terhenti ketika Shanum tiba-tiba berkata demikian. Pria itu membalik tubuhnya menghadap sang istri. Sebelah alisnya terangkat.
“Kenapa? Apakah kamu tidak nyaman tinggal di rumah ini?”
Jelas tidak nyaman. Sabda pulang tengah malam tadi. Meskipun pria itu sudah berada di rumah, hatinya mendadak dipenuhi kegelisahan. Belum lagi Shanum mencium bau parfum lain dari kemeja sang suami. Shanum tidak setenang biasanya, selalu ada perdebatan kecil di antara mereka.
Entah ini salah Shanum yang terlalu takut menghadapi kenyataan, atau salah Sabda sendiri yang tak tahu malu. Intinya, wanita itu sudah tidak nyaman lagi berada di sana.
Dia harus memikirkan alasan yang bagus supaya Sabda mengizinkannya pergi. Shanum bisa saja pergi tanpa izin dari pria itu. Hanya saja, Sabda masih seorang suami yang harus dihormati. Jadi, Shanum tidak punya pilihan.
“Aku hanya ingin tinggal dengan ibu. Tidak apa-apa kalau kamu tidak mengizinkanku menetap di sana, setidaknya biarkan aku tinggal di sana sementara.”
“Nggak bisa. Kalau kamu pergi, siapa yang akan merawatku di sini? Ibu juga sudah sering mewanti-wanti kita untuk pergi ke rumahnya bersama, bukan sendiri. Apa karena kemarin aku pulang terlambat makanya kamu kesal?”
“Sudahlah.”
“Padahal aku sudah sukarela pulang ke rumah setelah mendengar rengekanmu sepanjang hari di telepon. Apa lagi yang kamu inginkan?”
Sabda mengatakannya tanpa merasa bersalah. Dia pulang karena pusing mendengar ocehan Shanum yang terus memintanya kembali. Rencana Sabda untuk pulang esok hari dimajukan karena Shanum terus marah-marah di telepon.
Sabda kembali memutar tubuh menghadap cermin. Pria itu menyelesaikan kegiatannya mengancingkan kemeja. Dia masih semangat untuk pergi bekerja setelah kemarin berjalan-jalan dengan Rania selama seminggu.
Shanum berusaha untuk memupuk sabar. Jika dia tahu menikah dengan pria seperti Sabda hanya akan menambah beban pikiran dan masalah yang tak kunjung selesai. Sejak awal dia tak seharusnya mengikuti kata hatinya untuk menjadikan pria itu sebagai suami.
Untuk apa menikah dan punya suami jika pada akhirnya dia tetap memikirkan dirinya sendiri tanpa peduli perasaan Shanum sebagai seorang istri? Bahkan sekarang pria itu seolah melupakan janjinya. Apa yang harus Shanum harapkan dari pria itu?
So, apakah sekarang Shanum menyerah?
Jawaban Shanum, iya, karena memiliki suami seperti Sabda seperti tak ada gunanya. Selama ini dia sudah berupaya untuk sabar dan mempercayai Sabda kembali, tapi respons lelaki itu masih sama. Seolah menarik ulur perasaannya. Entah apa yang Sabda inginkan, tapi tampaknya Shanum sekarang mulai hilang kesabaran.
Shanum memejamkan matanya, lalu menghela napas berat. “Kamu yakin nggak mau mendengarkan perkataanku? Aku ingin tinggal di rumahku sendiri dan aku mau menengok butik hari ini.”
“Nggak. Tetap pada keputusanku. Kamu sendiri tahu kalau istri harus nurut apa kata suami, ‘kan?”
“Kapan aku tidak pernah nurut kata-kata kamu? Kalau kamu emang gak suka sama istri yang suka membantah sepertiku, lebih baik kita cerai aja.”
Terjadi keheningan sepersekian detik. Hanya deru napas penuh luapan emosi Shanum yang terdengar. Wanita itu tampak berusaha untuk tak kembali meledak setelah melihat respons biasa suaminya. Pria itu menoleh ke arah sang istri. Entah mendapat keberanian dari mana Shanum bisa mengatakan hal tersebut, Shanum sudah benar-benar di puncak kesabaran.
“Kamu terlalu emosi. Jangan pernah keluarkan kata-kata seperti itu dalam keadaan marah. Apa kamu tidak takut menyesal suatu saat nanti?” tanya Sabda sembari menatap istrinya penuh penekanan, seolah Shanum baru saja membuat kesalahan yang sungguh fatal.
Usai memastikan penampilannya rapi, Sabda beranjak meninggalkan cermin. Dia berjalan mendekati Shanum yang duduk di atas ranjang dengan wajah kesal.
“Aku tidak akan membiarkanmu pergi semudah itu, Sha. Tidak akan. Bukankah kamu pernah berjanji tidak akan meninggalkanku kecuali aku yang memintanya?”
Seiring meluncurnya kalimat serupa pertanyaan itu, Shanum menghela napas, lalu meraup wajahnya menggunakan telapak tangan.
Saat dia telah mantap untuk bercerai, Sabda malah membuat pikirannya berkecamuk. Wanita itu meragukan keputusannya sendiri. Kata cerai yang sempat terucap mantap, perlahan memudar.
“Astaga!” Shanum mengacak rambutnya sendiri. “Semua ini membuat kepalaku sakit.”
“Jangan pernah ngomong aneh-aneh saat lagi sakit. Mama udah bikinin kamu bubur ayam. Tadi pagi beliau datang dan memberi pesan untuk menghabiskannya, jangan manja dan makanlah.”
Oh, lihatlah bagaimana telaten dan baiknya sang mertua dalam memperlakukan menantunya. Bahkan Shanum bisa bertaruh, bahwa mama mertuanya lebih perhatian pada sang menantu daripada putranya sendiri.
“Kamu saja yang makan, aku mau makan di rumah ibu,” ujarnya ketus.
Shanum tetap pada pendiriannya untuk pergi, Sabda menghela napas berusaha untuk sabar. Menghadapi Shanum di saat dirinya sedang emosi memang cukup sulit. Terlebih Sabda tidak diberi kesempatan untuk menjelaskan sesuatu padanya.
“Mas, kamu bisa tinggal di rumah Mama Diana jika tidak ada yang merawat. Aku tidak suka di sini, rumah ini membuatku stres, Mas. Biarkan aku bernapas sebentar.”
Ucapan Shanum sama sekali bukan ide bagus. Rasanya sangat mustahil untuk tinggal di rumah ibunya dan alasan macam apa yang harus Sabda berikan untuk menjawab pertanyaan orang tuanya nanti? Sabda tidak habis pikir, kenapa Shanum setega itu mengajaknya bercerai.
“Jangan membahas tentang penceraian. Kamu pikir bercerai semudah itu? Kita akan cari jalan keluar untuk menyelesaikan masalah ini bersama-sama. Bukankah kamu pun sudah berjanji bah-”
“Aku tahu, tapi aku ingin menarik kata-kataku yang dulu. Apa yang harus kuharapkan dari pernikahan yang rusak ini, Mas? Setiap harinya hanya memberi luka saja. Kupikir kamu sudah cukup pintar untuk memahami perasaan istrimu. Kenyataannya tidak.”
Shanum menghela napas lagi. Dalam kondisinya saat ini, lagi-lagi suaminya tak berhenti membuatnya berada dalam masalah. Belum reda rasa pusing yang menderanya selama masa sakit ini. Suaminya malah menambah rasa pusing itu.
“Sebaiknya bicarakan masalah ini lain waktu saja. Hormonmu sedang naik turun makanya gampang emosi. Ayo makan, atau buburnya akan dingin nanti.”
Sabda berusaha menenangkan, tapi kalimat itu sama sekali tidak membantu, malah semakin memperkeruh suasana. Shanum ingin tetap pergi ke rumah ibu, dan Sabda yang enggan melepaskannya walau sebentar saja.
“Cukup. Baiklah, aku tidak akan menuntut cerai, tapi aku tetap ingin pergi.” Shanum bangkit dari ranjangnya dan membuka lemari, mengeluarkan koper dari sana. Wanita itu mulai nekat sekarang.
Sabda berusaha menghentikan. Namun, Shanum menyentak kasar tangannya. Pria itu sadar jika istrinya sedang marah besar. Namun, dia masih tidak mengerti apa inti permasalahannya.
“Seharusnya dulu kamu pilih-pilih kalau mau cari calon istri. Jangan memilih perempuan yang banyak menuntut sepertiku. Ditambah, kamu sudah membohongiku selama ini. Aku nggak akan sekecewa ini kalau dari awal kamu sudah jujur. Aku benar-benar capek menghadapi rumah tangga penuh drama ini, Mas!”
Di sela kegiatannya, mata Shanum sedikit berkaca-kaca. Sabda tak berani beranjak mendekat. Dia hanya terdiam di belakang istrinya tanpa berani mencegah.
“Aku nggak habis pikir sama kamu. Apa yang kurang dariku selama ini? Masa lalumu, aku sudah menerimanya dengan baik.” Shanum menghentikan aktivitasnya sejenak, tapi dia enggan untuk menghadap Sabda.
“Jika memang kamu tidak mencintaiku, seharusnya katakan itu pada orang tuaku mungkin mereka akan memakluminya. Jika memang sudah lelah bicaralah, toh aku takkan mengemis agar kamu tetap di sini. Jangan berbohong demi membahagiakanku. Kebohongan itu meskipun manis, dia selalu meninggalkan akhir yang pahit.
Aku tidak peduli apa alasanmu begitu mencintainya. Hanya saja … mengapa kamu tidak bisa menghargai perasaan seorang wanita? Kalau memang kamu sudah tak bisa bertanggung jawab atas kebahagiaanku, lebih baik kamu pulangkan saja aku pada ayah dan ibu.”
Lagi-lagi Sabda tidak bisa menjawab pertanyaan itu. Dia ingin bilang bahwa semuanya tak sepenuhnya benar, tapi Sabda tahu wanita itu takkan percaya. Mau sebanyak apa pun Sabda berterus terang. Justru semua kebenaran itu hanya melukai perasaannya.
“Cukup lama aku mencoba berdamai dengan hatiku, tapi kembali kudengar kau pergi ke luar dengan wanita yang tak lain adalah selingkuhanmu itu. Kau pikir aku sekuat apa?”
Sabda terbelalak, istrinya tahu? “Shanum!”
Shanum berbalik ketika mendengar suara Sabda yang sedikit keras itu. Dia tersenyum gamang. “Aku tahu, sudah kubilang jangan membohongiku, Mas. Ternyata benar kalian selama ini pergi liburan bersama.”
Sebuah perkataan yang menohok, membuat Sabda diam mematung. Ucapan Shanum seolah sukses membuat Sabda tak bisa membantah. Sebab pada kenyataannya apa yang Shanum katakan benar adanya.
“Baiklah semoga kamu bahagia dengan kehidupanmu, nikmatilah jalanmu. Maaf, mulai sekarang, sekarang aku akan tinggal di rumah ibu sampai waktu yang tidak ditentukan. Maaf karena telah menyusahkanmu selama ini.”
Sabda sontak membulatkan mata, dia tidak menyangka bahwa Shanum akan benar-benar nekat seperti itu.
“Sha! Apa-apaan kamu?” Sabda tampak kesal.
“Jaga kesehatanmu, aku sudah siapkan obat yang harus kamu minum tiga kali sehari. Jangan lupa makan, tenang saja … aku bisa mengurus diriku sendiri.”
Shanum langsung berbalik. Koper besar dan tas miliknya turut dibawa. Sabda terlalu lamban untuk bertindak dengan mencegah istrinya pergi. Sehingga, ketika mobil Shanum telah berlalu jauh, baru Sabda sadar dan bergegas mengejar.
“Ya Tuhan, apa yang sudah kulakukan?”
Sabda menyalahkan dirinya dalam kasus ini. Istrinya yang berada dalam keadaan emosi memang begitu susah dimengerti. Apakah kesalahannya cukup fatal sehingga wanita itu ingin pergi?
TAK LAGI UTUH
“Kenapa dia bisa tahu aku pergi dengan Rania kemarin? Apakah dia menggunakan orang suruhannya untuk memata-mataiku? Keterlaluan!”
Tak berhasil mengejar mobil yang dikendarai oleh istrinya. Sabda akhirnya mengikuti wanita itu ke rumah orang tuanya. Sifat Sabda yang selalu merasa benar, lagi-lagi menyalahkan Shanum dalam perihal masalah yang saat ini mereka hadapi.
Mereka bertengkar di rumah orang tuanya, Shanum yang sudah muak meladeni Sabda terus berusaha untuk menghindar. Namun, Sabda tetap pada pendiriannya. Dia tidak mau Shanum pergi begitu saja.
Shanum berusaha menutup pintu rumah rapat-rapat, tidak memberikan akses untuk Sabda masuk ke dalam. Sabda menahan pintu tersebut, berusaha untuk mencegah istrinya agar mereka bicara baik-baik. Sayangnya, kepercayaan Shanum serupa gelas kaca, sekali pecah dia tidak akan kembali utuh.
“Keluar! Ayo kita bicarakan masalah ini. Ini tidak seperti apa yang kamu pikirkan. Bukankah kamu juga tahu kalau selama ini Rania adalah kekasihku, kenapa sekarang kamu malah marah padaku?”
Tentu saja limpahan kesalahan yang Sabda bebankan padanya membuat Shanum geram. Tanpa sadar Shanum melempari pria itu menggunakan kunci mobil yang kebetulan sedang dipegangnya.
Akibat lemparan itu, Sabda sampai memekik tak menyangka Shanum bisa sekasar itu pada suaminya sendiri. Beruntung hari ini orang rumah sedang tidak ada, jadi pertengkaran itu hanya mereka berdua yang tahu.
Juga tetangga. Mungkin.
“Kenapa kamu kasar sekali, Sha. Gimana kalo keningku berdarah?” Sabda mengusap pelipisnya yang berdenyut. Tidak menyangka Shanum akan semarah ini bahkan bertindak di luar dugaan.
Shanum memberinya pelototan tajam. Kedua tangannya berkacak pinggang. “Siapa yang kasar? Aku hanya mengusirmu. Ngapain kamu ngikutin aku kembali ke sini? Pulang sana, nikahi saja wanita simpananmu itu!”
“Oke, aku pulang, tapi kamu juga harus ikut aku.”
“Siapa bilang aku mau ikut pulang ke sana? Pergi sendiri!” tolak Shanum penuh amarah. “Kalau saja dari dulu aku tahu kau akan mencintai seorang pelakor. Aku gak akan menerima pinanganmu. Aku menerimamu dengan baik, keluargaku memperlakukanmu dengan baik. Namun, kau? Semaumu saja memperlakukanku!”
Napas Shanum menderu. Kepalang emosi, dia akan melimpahkan semuanya pada Sabda saat itu juga. Kondisi Shanum yang masih lemah pasca sakit ditambah kelelahannya menghadapi Sabda membuat kesabaran Shanum serupa bom waktu yang kapan saja bisa meledak.
“Setidaknya dengarkan aku dulu, Sha!” Sabda tetap ngotot.
“Apa? Apa yang mau kau jelaskan? Kau sendiri yang bilang akan berusaha menjauh darinya, tapi sampai saat ini kalian masih intens berdekatan, dan yang paling tidak bisa kutolerir adalah … bagaimana bisa kau pergi liburan berdua dengan wanita tak tahu malu itu di belakang istrimu yang sedang sakit? Bajingan Sabda, kau memang bajingan!”
Shanum benar-benar emosi. Dia ingin sekali menyiksa Sabda yang tidak tahu diri. Bagaimana bisa Shanum menikah dengan pria bajingan? Apa dosa yang sudah dia perbuat di masa lalu?
Shanum mengetahui fakta ini setelah menerima panggilan staf kantor Sabda. Staf itu tak sengaja mengatakan bahwa atasannya pergi berlibur ke luar kota, dari situ Shanum tahu bahwa Sabda tidak pergi sendiri. Sakit … perasaannya amat sakit.
“Kalau sejak awal kamu merasa pernikahan ini hanya kebetulan, kenapa marah di saat aku pergi liburan dengannya? Kamu sendiri juga tahu seperti apa hubungan rumah tangga kita akhir-akhir ini. Aku gak bahagia, Sha. Aku juga butuh seseorang yang bisa menghilangkan kejenuhan itu. Emang kamu gak capek terus bersandiwara di depan keluarga seperti ini?”
Sabda mengatakan hal itu tanpa rasa bersalah, juga tanpa perasaan. Sukses membuat hati Shanum semakin remuk redam.
“Begitu? Bukankah itu alasan yang bagus? Kita bisa bercerai karena kenyataannya kamu gak bahagia saat bersamaku. Selama ini aku gak becus jadi istri. Baiklah, kembali kuajukan. Aku minta cerai!”
Telapak tangan Sabda mengepal. Bukan ini yang dia inginkan. Meskipun benar bahwa Sabda telah merencanakan pernikahan dengan Rania. Tetap saja, Sabda tidak bisa berjauhan dari istrinya. Shanum memang wanita yang keras kepala, tapi Sabda tidak bisa melepaskannya begitu saja.
Shanum adalah istri yang sempurna bagi laki-laki yang telah menyuntingnya, tapi laki-laki itu bukan dirinya. Sesungguhnya Sabda juga menyadari bahwa dia bukan suami yang baik untuk Shanum, tapi kenapa wanita itu mengatakan bahwa dialah yang selama ini tidak becus menjadi istri?
Apa pun itu, Sabda tetap butuh Shanum. Hanya dia yang boleh memintanya untuk pergi. Shanum tidak boleh memutuskan hubungan tanpa seizinnya. Entahlah, Sabda tak mau orang tuanya kehilangan sosok Shanum, atau mungkin Sabda sudah mulai jatuh cinta padanya.
Sabda terlalu bodoh untuk memahami apa arti cinta yang sebenarnya. Sepanjang pernikahan mereka, dia terlalu sibuk bekerja dan melupakan perasaan Shanum. Kini wanita itu sudah meminta cerai. Apakah Sabda bisa menerima keputusannya begitu saja?
Desahan napas pria itu terdengar. Kepalan telapak tangannya mengendur. Wanita yang merupakan istrinya itu ditatap dengan wajah penuh permohonan.
“Aku gak bermaksud untuk bohong sama kamu, Sha. Sejak awal aku ingin menjelaskan padamu, tapi kamu telanjur emosi. Berhenti mengada-ada. Ayo kita pulang dan selesaikan semuanya dengan kepala dingin.”
Shanum mendengkus. “Kamu yang menceraikanku atau aku yang maju lebih dulu untuk menggugat cerai?”
“Shanum ….” Sabda memelas.
“Oke. Tunggu saja surat panggilan dari pengadilan. Apa pun yang berusaha kamu jelaskan, aku tetap ingin berpisah sama kamu. Tenang saja, kita masih bisa bertemu. Entah dengan kamu yang kusemogakan hari ini, atau dengan kamu yang membuatku bersyukur karena doa-doaku dikabulkan dengan jawaban yang lain.”
Shanum sama sekali tak memberi kesempatan pada Sabda. Stok kesabarannya telah habis. Hatinya hancur berkeping-keping saat mengatakan hal ini, tapi mau bagaimana lagi. Bertahan pun tidak membuat semuanya membaik, kondisi hatinya tak lagi sama.
Dia merasa sudah cukup bersandiwara sampai di sini saja. Orang tuanya mungkin tidak akan menerima perpisahan mereka, karena setahu keluarganya Shanum dan Sabda tampak baik-baik saja. Mereka selayaknya keluarga yang utuh.
“Aku mau istirahat. Jadi, silakan pergi dari rumahku sekarang!”
“Sha, ayo kita bicarakan baik-baik sekali lagi, ya?”
“KELUAR SEKARANG!!”
Napas Shanum naik turun dan terdengar menderu. Matanya melotot tajam berubah kemerahan. Pertanda bahwa Shanum benar-benar tidak ingin diganggu oleh siapa pun, keputusannya sudah final. Shanum tetap ingin bercerai dengan Sabda.
“Apa yang akan kamu katakan pada ibu dan ayah kalau kamu pergi dengan keadaan kayak gini? Kamu pikir ini mudah untuk kita?”
“Lebih baik begitu, ‘kan? Mereka pasti akan mengerti kalau kita berpisah karena sudah tak ada kecocokan lagi.” Shanum berkata final.
Melihat respons istrinya yang tetap ingin berpisah, Sabda memilih mengalah. Mau bagaimana pun, dia tidak akan bisa menenangkan Shanum yang tengah marah. Shanum selalu kehilangan kendali saat emosi, seperti hari ini. Sabda tak diberi kesempatan sedikit pun untuk menjelaskan semuanya pada Shanum.
“Baik, aku akan pulang, tapi jangan membuat keputusan saat sedang marah, Sha. Tenangkan dirimu dulu, baru kita bicara lagi.”
“Apakah wajar kalau seorang istri tidak marah saat dibohongi oleh suaminya? Aku juga punya hati, Mas. Mama dan papa memintaku dengan cara baik-baik untuk menjadikanku sebagai menantu mereka. Aku hanya menerima, bukan meminta. Justru kau yang tidak waras! Ke mana otak cerdasmu yang selalu kau banggakan itu? Kau buang ke tempat sampah?”
Mendengar ucapan Shanum yang merendahkan, Sabda melotot. “Sha, jangan kurang ajar!”
Shanum memutar bola matanya. Begitu Sabda mundur melewati batas pintu rumahnya, Shanum langsung menutup pintu dengan kasar.
Brakk!
“Shanum, kumohon jangan seperti ini!” Sabda menggedor pintu yang tertutup di hadapannya.
Usai menutup pintu dengan kasar, Shanum bersandar di pintu, lalu merosot begitu saja. Sesak yang tadi ditahan akhirnya tumpah bersama dengan tangisan.
Shanum benci jika harus terlihat lemah di hadapan pria yang selalu menginjak-injak harga dirinya. Dia tidak mau terlihat menyedihkan. Apa yang akan orang katakan nanti tentangnya? Wanita dengan kekayaan dan karier sempurna memiliki rumah tangga yang hancur.
“Mengapa harus ada aku yang sangat jatuh cinta kepadamu? Padahal aku punya pilihan. Sialnya, cinta tidak membiarkan aku memilih.”
Apakah Shanum betah? Tidak. Berkali-kali dia ingin menyerah. Namun, entah apa yang membuatnya bertahan, entah kekuatan apa yang memampukannya berjuang. Saat Shanum sendiri tidak tahu apa yang sedang dia perjuangkan. Kenyataannya, Shanum tetap di sana, tidak pernah benar-benar ingin pergi.
“Sha, nanti aku kan menjemputmu. Jangan macam-macam. Tenangkan dulu pikiranmu.”
Itulah ucapan sabda sebelum melangkah pergi dari sana. Membawa pergi patahan hatinya yang berhamburan. Entah sampai kapan perpisahan itu akan berlangsung. Sabda tidak mau mereka berakhir, tapi dia juga tidak bisa memaksa Shanum untuk menarik kembali ucapannya.
Setiap kali dia hendak memperbaiki semuanya, permasalahan itu selalu muncul kembali ke permukaan. Mungkin benar dia bukan suami yang baik.
“Bagaimana pun, aku akan membawamu kembali.”
Bersambung…