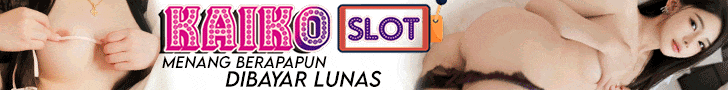MEMUTUSKAN UNTUK PUTUS
Duduk bersama seorang wanita yang tidak pernah Shanum inginkan keberadaannya.
Shanum sudah mengirimkan pesan pada Sinar dan mengatakan bahwa dia akan bicara sebentar dengan Rania, wanita itu mengerti dan memberikan mereka ruang untuk saling bicara.
Wajah wanita yang duduk di kafe bersama Shanum saat ini belum berubah dari yang pernah Shanum lihat. Perbedaan besar yang dia sadari hanyalah kantung matanya yang menghitam, kentara sekali dia kurang tidur.
Sampai pramusaji mengantarkan minuman, belum ada satu pun dari mereka yang bicara. Shanum yakin wanita tersebut egois, sama sepertinya. Melihat wanita ini sekarang, seakan melihat masa lalu Shanum yang penuh masalah.
“Kamu cantik, terlihat lebih muda dariku. Berapa usiamu?” tanya Shanum memulai pembicaraan.
“24 tahun.” Mata Rania yang gelap menyorot tajam. Suaranya dalam, parau, dan tegas.
Sedikit demi sedikit Shanum bisa menilai seperti apa dia sebenarnya. Rania tampak sangat gugup berhadapan dengan Shanum. Dilihat dari gerak-geriknya yang terus merunduk. Shanum tak bisa hanya diam saja menunggu perempuan di depannya bicara.
“Aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini. Omong-omong ada apa mengajakku bertemu?”
Perlahan Rania mendongak, Shanum tidak suka basa-basi. Terlebih sudah sepuluh menit berlalu semenjak mereka duduk di kafe. Shanum masih tak bisa mencari letak hal yang ingin Rania bicarakan.
Entah kenapa Rania merasa ingin kembali ke bekerja. Sepertinya dia salah memilih timing yang pas untuk bertemu. Kenapa harus ke sini? Kenapa harus bertemu Shanum?
“Ada apa? Kenapa tiba-tiba mengajakku bertemu? Ada hal lain yang ingin kamu katakan?” Shanum mengulang pertanyaan.
Beberapa detik berlangsung dalam keheningan, Rania akhirnya membuka suara. Suaranya terdengar pahit dan pilu.
“Aku hanya ingin minta maaf … a-aku … aku berpacaran dengan suamimu.”
Saat mengatakan itu, matanya tak lepas dari cincin Shanum. Wanita itu masih memakai cincin pernikahannya. Hal yang membuat Rania sadar bahwa dia bukan siapa-siapa di hidup Sabda. Setelah itu mata mereka kembali beradu. Seolah Rania benar-benar putus asa dan bingung harus bagaimana.
Shanum berusaha untuk mengerti apa yang gadis itu katakan, semua ini memang terdengar pahit dan Shanum masih setia mendengarkan kelanjutan ceritanya.
“Aku tidak bisa hidup tanpa pria itu, aku tidak tahu sebelumnya kalau dia sudah menikah. Lebih dari itu, dia bahkan sudah datang ke rumahku dan menghadap papa.”
Shanum menekuk kesepuluh jarinya di atas paha, meremat dalam tinjunya saat mendengar Rania mengucapkan seluruh rangkaian kalimat yang rasanya bekerja seperti kail pencungkil organ.
“Mas Sabda menemui ayahmu? Untuk apa?” Dia bertanya lagi.
“Hubungan kami sudah berjalan dua tahun, aku tidak tahu kalau kalian adalah suami istri. Waktu itu aku sudah meminta Mas Sabda untuk segera menemui papa dan menikahiku.”
Mendengar ucapan Rania, emosinya naik turun. Ternyata benar, apa yang Shanum dengar waktu itu mereka tak hanya sebatas liburan saja. Hati Shanum benar-benar sakit mengetahui fakta itu.
Rania juga tersakiti, dia masih tidak percaya kalau Sabda bisa sejahat itu padanya. Di sini bukan hanya Shanum yang merasakan sakit, Rania pun merasakannya. Bahkan dia tak tahu apa-apa.
Rania mengulum senyum. “Aku mencintainya. Sangat, tapi sekarang aku mulai berpikir, rasanya aku tidak bisa bertahan dengan pria itu lebih lama. Sekarang aku punya alasan kenapa aku harus meninggalkannya.”
Rania menengadahkan kepalanya dan tertawa tanpa suara. Dia mengambil napas sekali tarikan dan menatap Shanum. Seolah dia lega sudah mengatakan hal itu.
Kejujuran yang dipendam selama ini akhirnya bisa diluapkan pada seseorang.
“Kamu tidak mau menemani Mas Sabda lebih lama?” tanya Shanum memastikan. Dia terkejut mendengar gadis itu berkata ingin meninggalkan Sabda.
Sama seperti Shanum yang berkali-kali berniat meninggalkan Sabda dan menggugat cerai. Setiap malam Shanum selalu berpikir ‘apakah sampai akhir hubungan kami akan tetap seperti ini?’ tapi seperti yang semua orang lihat hari ini. Mereka masih bersama. Hubungan mereka belum masuk ke proses penceraian.
Rania menarik dua sudut bibirnya. Kali ini Shanum gagal menebak apa arti senyuman itu.
“Kamu wanita hebat, Mbak Shanum.”
“Begitukah?”
“Aku bahkan tak bisa membayangkan rasanya hidup bersama orang yang hanya bisa menyakiti,” tambahnya.
Shanum tidak tersanjung, baginya itu bukan hal yang pantas mendapat pujian. Shanum justru merasa menjadi perempuan bodoh karena sudah bertahan dengan pria yang sama sekali tak ada kemajuan apa pun selama menikah dengannya.
“Rania, bukankah sebelum berhubungan seharusnya kau tahu, siapa pasanganmu, seperti apa kondisinya, dan apa masa lalunya, kamu harus mengerti, ikatan pernikahan berbeda dengan pacaran yang bisa diputuskan seenaknya ketika bosan.”
“Jadi, ini salah satu alasan Mbak tetap bertahan, meskipun tak bahagia?”
Shanum menahan diri sejenak. “Jika hanya mencari bahagia, hidup saja melajang. Tujuan pernikahan bukan hanya tentang mencari bahagia. Pernikahan bukan hanya tentang cinta. Ada masa depan di dalamnya.”
Shanum tidak marah dengan Rania, dia bisa paham kenapa gadis itu bertanya demikian padanya. Shanum berusaha untuk menjelaskan.
“Pernikahan bukan tentang dua hati saja, tapi juga dua keluarga, dua kepala yang berbeda,” katanya, lalu dilanjutkan dengan nada setengah merenung ke dalam gelas milik Rania yang isinya hampir habis.
“Ayahku pernah mengatakan pernikahan itu berat. Hampir setiap hari dia terpikir, apakah dia bisa memperjuangkan pernikahannya sampai akhir, apakah kelak mereka bisa memiliki anak, apakah dia sanggup menjaga keluarganya, apakah mereka akan tinggal sehidup-semati, belum lagi memikirkan sumber pendapatan atau jaminan untuk keluarga. Terdengar mudah, tapi sulit dijalani. Sampai saat itu kamu takkan pernah menemukan seseorang yang cocok selain menerima mereka dengan tangan terbuka.”
Rania masih bungkam, Shanum terus melanjutkan kalimatnya.
“Rania, orang yang kau miliki sekarang, dia adalah suami orang lain. Dia orang yang pernah mengikrarkan janji suci di depan ayahku lima tahun yang lalu. Dia tidak sempurna, tentu saja. Namun, semua yang ada padanya sudah sesuai kriteria. Orang tuanya baik, mereka bahkan menyimpan harapan yang besar terhadapku, kiranya apa yang akan terjadi jika mereka tahu kami bercerai?”
Shanum hanya ingin memberi pengertian bahwa makna pernikahan tak sesederhana yang biasa dia lihat di FTV atau drama. Lebih dari itu dan memutuskan sesuatu tak semudah kelihatannya. Seharusnya Rania mengerti.
“Menurutmu, seperti apa pria itu? Suamiku, pria yang berselingkuh denganmu?”
Ketika Shanum bertanya mengenai hal itu, Rania menarik napas seolah tak mengerti kenapa Shanum bertanya. Bukankah dia istrinya, sudah pasti Shanum mengetahui jawabannya.
“Haruskah aku mengatakan hal ini, Mbak? Aku hanya takut menyakitimu.”
“Tidak akan.” Shanum tersenyum kecil. “Jelaskan saja.”
Rania menggigit bibir, tapi pada akhirnya dia menuruti perintah Shanum.
“Pria yang menjadi suamimu, adalah seseorang yang melihat bukan dari nilai. Namun, menjadikanku di atas standar. Seseorang yang peduli dengan kondisiku. Seseorang yang benar-benar mendengarkanku ketika berbicara, yang mampu mengingat hal-hal kecil yang kusebutkan dalam percakapan.
Seseorang yang akan memelukmu hangat ketika sedih. Seorang pria yang sanggup menahan rindunya agar dia tidak mengganggumu ketika istirahat, yang lebih senang meluruskan bukan selalu membenarkan, yang bersedia menghubungi ketika dia akan datang terlambat.”
Shanum tampak terperangah mendengar ucapan Rania. Sebaik itu Sabda memperlakukan gadis tersebut sehingga hanya kebaikan yang keluar dari mulutnya, mata Shanum memerah, entah kenapa Rania sedikit iba melihatnya.
“Mbak, dia tak pernah pernah meninggalkan seseorang kecuali seseorang itu memintanya. Sekarang dia layak mendapat seseorang yang ingin tinggal bersamanya dan mencintainya sepanjang waktu. Kurasa dia sangat mencintaimu, karena itu dia tak ingin kalian bercerai.”
Usai mengatakan hal itu, Shanum dan Rania kembali terdiam. Mereka benar-benar tidak bersuara. Entah sampai kapan keduanya akan terjebak dalam kehampaan seperti ini. Shanum pun tak menyangka akan benar-benar bicara dengan gadis yang Sabda cintai.
Segala aliran darahnya seperti berhenti di satu titik hingga membuat Rania menahan napas selama beberapa detik. Meski begitu, dia berpura-pura terlihat biasa saja saat wanita di depannya tersenyum dengan sorot tidak biasa.
Kini suara bising pengunjung kafe yang kerap menjadi penyebab kepalanya pusing tak lagi begitu terdengar. Satu-satunya suara yang paling berisik dan bergaung di telinga Rania hanya dari pikirannya sendiri.
Shanum tak bisa bergerak barang sedikit pun. Tubuhnya mirip kertas yang diremas dan dilempar ke lantai. Shanum terus memperhatikan wanita itu yang sedang tersenyum padanya.
Dia memang Rania. Duduk di depannya dengan senyuman manis dan anggun seperti biasa. Pantas saja Sabda jatuh cinta padanya.
“Kamu benar-benar mau mengakhirinya? Bukankah kalian saling mencintai. Jangan cemas, lagipula aku mungkin akan selesai dengannya tak lama lagi. Aku bisa hidup sendiri dengan bayiku nanti.” Shanum memulai obrolan karena Rania hanya terdiam sejak tadi.
Senyum Rania berubah begitu dia mendengar Shanum menyebutkan kata bayi. Pertahanan Rania semakin runtuh, hal yang tidak pernah dia duga sebelumnya. Shanum hamil?
“Mbak, kamu hamil?”
“Iya, masuk usia tiga minggu.”
Perkataan Shanum membuat senyum Rania sirna beberapa detik. Serumit ini berhadapan dengan istri sah Sabda. Entah kenapa Rania merasa begitu jahat karena sudah membuat Shanum menderita, tapi dia pun tidak tahu apa-apa. Haruskah Rania merasa begitu bersalah padanya?
“Minumlah, barangkali bisa membuat perasaanmu membaik.” Shanum menyuruh Rania untuk minum karena wajah gadis itu tiba-tiba saja memucat.
Rania menyentuh minumannya. Dia benar-benar tak habis pikir dengan apa yang terjadi, kenapa hal ini bisa terjadi padanya. Sabda mau menikahinya di saat istrinya sendiri tengah hamil.
“Aku hanya menawarimu untuk minum. Tidak ada apa-apa di dalam kopinya. Aku tidak akan melukaimu, Rania. Tidak akan pernah bisa.”
“Mbak Shanum, kamu tentu masih ingat apa yang kukatakan, kan? Aku memang memintanya untuk memberi kepastian, tapi itu sebelum aku menyadari kalian sudah menikah.”
Shanum menghela napasnya sejenak. “Tapi sekarang kamu sudah tahu, kan? Dan aku juga tahu kalau kalian belum putus. Lantas, kamu pikir aku percaya begitu saja?”
“Aku tahu, aku cuma belum menemukan waktu yang pas untuk mengajaknya bicara. Aku terlalu takut,” katanya. “Tetapi yang temanmu katakan hari itu terus mengusikku. Semua tuduhanmu, perkataan bahwa aku mengencaninya karena harta semata, itu semua tak benar. Semuanya salah. Tuduhanmu salah, Mbak Shanum, jangan pernah mengecapku sudah berlaku jahat pada Sabda. Aku mencintainya karena suatu alasan, dan dia memahaminya.”
Shanum mengerti dengan keresahan Rania, dia akan menarik praduganya tentang hal ini. Rania memang tidak berharap apa pun kepada Sabda selain cinta. Namun, apakah cinta saja cukup?
“Bukankah kamu seolah-seolah mengatakan dia bisa memberimu apa saja?”
Rania menarik napas. Kelihatan tak berdaya dengan ucapan Shanum. Percuma saja dia mengubah suaranya semanis madu, atau membuat ekspresi selembut mentega. Shanum tidak akan terpengaruh.
“Jujur saja, aku mencintai semua tentangnya. Semua yang ada padanya. Bau citrus-nya, kehadirannya, mata polos berwarna cokelatnya. Perhatiannya yang selalu melimpah dengan kasih sayang.”
Mata Shanum berembun seketika. Bohong kalau dia tidak cemburu, segala hal yang Rania ceritakan. Itu sama … sama seperti dia melihat Sabda.
“Caranya bersenandung hingga aku terlelap, membelai rambutku dengan jarinya yang indah, berbaring di tempat tidur yang sama denganku, kami sering bercerita mengenai pernikahan.”
Rania tidak bermaksud melukai Shanum, tapi dia hanya menjelaskan alasan lain kenapa dirinya mencintai Sabda, sama seperti istrinya sendiri.
Bolehkah Shanum menangis sekarang?
“Namun, pada kenyataannya kami harus sama-sama terluka. Mas Sabda sakit. Mbak Shanum, dan aku juga sakit. Ada yang tidak bisa kuterima dari hubungan ini. Aku akan memutuskan pergi darinya.”
Shanum menghapus air matanya dan menatap Rania lekat. Dia baru saja bersikap cengeng di hadapan kekasih Sabda. Ada jeda beberapa detik yang menyertai ucapan Shanum.
“Kamu mencintai suamiku?” tanya Shanum dengan berani, berusaha tegar dengan segala hal yang akan didengarnya. Meskipun agak menyakitkan.
Rania tampak terkejut dengan pertanyaan Shanum. Butuh waktu dua detik menunggu Rania menjawab ucapan wanita itu.
“Semua orang pasti mencintai kekasihnya, Mbak, tapi kurasa kami tidak bisa terus bersama, dan—“
“Tidak, aku bertanya apa kamu masih mencintai suamiku?” potong Shanum sekali lagi, sebab Rania menjawab tak sesuai keinginannya.
Rania hanya bisa terdiam sebentar, tak lama dia mengangguk.
“Masih. Itu yang selalu aku rasakan. Selalu sama.”
CINTA YANG BERAKHIR
Ada bagian yang hilang dari semesta.
Sejujurnya, semua pasti membaik. Orang bilang, waktu adalah obat terbaik untuk hati yang terluka.
Barangkali benar adanya jika ditilik dari mereka yang telah berhasil bangkit mati-matian menyeret langkah bahkan merangkak hanya untuk kembali mendapati seberkas cahaya yang muncul dari kegelapan, setelah merelakan sisa hidupnya untuk bergulat, dihajar habis-habisan oleh jalan hidup yang mengerikan.
Itu juga yang tengah dirasakan Rania. Baginya, yang menyembuhkan luka hanya dua. Waktu atau kedatangan sosok baru. Sayangnya, yang datang padanya saat ini adalah pria itu.
“Mas Sabda, kamu sudah pulang?” Rania berusaha bersikap ramah dan biasa. Ya, biasa.
Sabda tersenyum lantas berjalan mendekati Rania yang sedang duduk di sofa. Rania menunggu Sabda pulang dari kantor sekaligus berusaha untuk tetap bersikap tenang dan melupakan segala pemikiran buruknya.
Dia harus memutuskan segalanya sekarang.
“Iya, kamu menungguku? Tumben kamu di sini. Skripsimu sudah selesai?” tanya Sabda dengan tenang. Sangat tenang hingga mampu membuat kilasan-kilasan memori dalam kepala Rania melesak ke luar.
“Iya, aku menunggumu pulang.”
Rania tak pernah lupa dan tak akan pernah lupa bagaimana kedua iris cokelat itu menatapnya dengan penuh cinta dan hangat. Tidak pernah mengizinkan Rania untuk pergi. Sekarang dirinya yang harus memaksa pergi.
Rania berusaha untuk menahan rasa sakit yang tercipta dari mulut manis sosok yang dia cintai. Rania pikir semua yang Sabda katakan adalah ketulusan, tapi ternyata dia hanya sosok figuran dalam hidup Sabda.
Bagaimana tubuh kurus itu dipaksa untuk menjejalkan makanan setidaknya dua sendok setiap harinya untuk bertahan hidup, mati-matian menahan mual di pangkal tenggorokan ketika kilatan menyakitkan itu datang dan Sabda tidak ada di sana untuk merangkulnya.
Menyedihkan. Tapi kini, Rania pikir dia memang harus bicara dengan Sabda, dia tidak bisa selamanya terus berada dalam rantai ketidakpastian seperti ini. Rania selalu berharap wanita itu bahagia dengan pasangan yang seharusnya.
“Bukankah kamu bekerja? Sudah pulang atau bagaimana? Kenapa tak menghubungi?”
“Iya, aku meminta untuk pulang cepat hari ini karena ada sedikit urusan. Bagaimana kalau kita bicara empat mata?” tawar Rania.
“Ada apa memangnya?”
“Tidak ada apa-apa, aku hanya ingin bicara saja denganmu, Mas.”
Jelas Rania ingin memastikan kalau pria itu benar-benar sudah menikah dengan perempuan cantik seperti Shanum. Rania akan merindukan semua hal yang ada di diri pria itu.
Aroma citrus yang menguar, senyum manisnya, dan iris cokelat yang penuh kehangatan saat menatap. Pria sedingin es dan kaku, tapi penuh dengan kasih sayang. Kadang Rania sering berpikir kenapa pria itu tidak menceraikan Shanum saja jika dia benar-benar mencintainya.
“Duduklah di sini, ayo kita bicara dari hati ke hati, ya.” Rania menepuk sofa di sebelahnya. “Mumpung kamu sudah pulang. Bagaimana jika kubuatkan teh dulu?”
Sabda terkekeh mendengar ucapan kekasihnya itu. Sebuah pujian yang biasa membawa Sabda terbang menuju langit kebahagiaan, bahkan pujian Shanum tidak sampai membuatnya seperti demikian.
“Baiklah, ayo kita bicara. Apa yang mau kamu bahas? Teman-temanmu bersikap buruk lagi? Atau skripsimu tak kunjung selesai?”
Sabda seolah mengerti nyaris sebagian kehidupan Rania tanpa perlu gadis itu jelaskan. Pria itu menatap kekasihnya lekat. Sama saja bagi Sabda, wanita itu tidak berubah.
Butuh beberapa menit bagi Rania untuk membuka suara, sejak tadi dia hanya terdiam saja. Hal itu membuat Sabda heran.
“Kamu masih tidak mau bicara?” tegur Sabda karena sejak tadi gadis di depannya hanya diam.
Rania menggeleng. Masalahnya, dia tidak mungkin mengatakan tentang keputusannya untuk mengakhiri hubungan begitu saja. Dia harus memilih kata-kata yang tepat agar Sabda tidak marah.
“Perasaanmu sudah membaik? Oke kalau tidak mau cerita,” kata Sabda mulai menyerah.
“Bagaimana kalau kita putus saja? Aku merasa kita memang tidak cocok.”
Bagi Sabda, itu bukan pertanyaan, tapi lebih pada keraguan karena gadis itu terlihat tidak begitu niat mengatakannya.
Rania melipat bibirnya ke dalam. Tersenyum samar memikirkan bagaimana Sabda tampak santai menikmati hidup tanpa memikirkan pernikahannya yang sekarang.
Kalau kebanyakan orang memilih untuk menangis saat sedang tertekan atau merasa sedih. Rania justru memilih diam. Tidak ada air mata barang setetes pun. Namun, rasa sakitnya jelas membawa dampak besar.
“Ada apa, Rania? Jangan bercanda. Aku tidak suka!” Sabda mulai tersinggung.
“Aku sedang tidak bercanda.”
Sabda mulai menyadari kondisi mulai berbalik, mereka tengah serius sekarang. “Apa yang terjadi?”
“Tidak tahu.”
Sejujurnya, Rania terus mengulang pertanyaan itu sebanyak yang dia bisa. Terlebih setelah ia sadar bahwa sosok yang mengucap pertanyaan itu bukanlah siapa-siapa untuknya, tapi Sabda pun tidak pernah bertanya demikian.
“Kumohon Rania, jangan pernah mengatakan hal ini. Kita sudah berjanji akan menikah.”
“Lalu mengabaikan istrimu? Apakah seperti itu sifat asli pria yang nanti kunikahi?”
Sabda membulatkan mata, dia terkejut saat Rania berkata demikian. Apakah Rania memang benar-benar sudah mengetahui tentang statusnya yang merupakan suami Shanum? Perasaannya tak tenang, Sabda berusaha untuk menenangkan diri dan meminta penjelasan pada gadis itu. Dia yakin hanya salah dengar.
Pandangan Rania terpatri pada rintikan air hujan yang perlahan turun. Terkutuklah ramalan cuaca pada ponsel wanita itu yang tak berguna. Dia jadi tidak bisa menyiapkan baju tebal atau bahkan sekedar payung untuk pulang dari apartemen setelah mengatakan kata putus pada kekasihnya.
“Mungkin akan lebih baik kalau kita putus saja. Keadaannya menjadi semakin rumit ketika aku mengetahui semuanya. Aku tak mau merebut apa yang sudah istrimu pertahankan. Lagipula, aku kecewa padamu. Kenapa baru mengetahuinya sekarang. Kau pikir aku ini wanita macam apa?”
“Maafkan aku, Rania.”
“Tidak, lupakan!”
“Aku benar-benar minta maaf, Rania. Sebenarnya aku ingin menceraikannya saat aku sudah resmi akan menikahimu.”
Alasan yang cukup bodoh. Justru membuat Rania semakin tersakiti, tidak hanya Rania, tapi juga Shanum. Tidak ada yang tak tersakiti atas semua pilihan yang Sabda ambil. Semuanya menyakitkan.
“Maaf, aku sudah lelah dengan semuanya, Mas. Aku sudah memutuskan semuanya. Biarkan aku pergi.”
“Aku tak akan membiarkanmu pergi.”
Rania menghela napas berat, memejamkan mata sembari menahan hawa yang terus bergelayut pada tubuhnya. Beberapa detik setelahnya ia kembali menatap Sabda.
“Lalu, bagaimana dengan istrimu? Aku sudah bilang pada papa kalau rencana kita untuk menikah dibatalkan. Tenang saja, aku tidak mengatakan apa pun, aku hanya bilang kita ternyata tidak cocok. Aku yakin papa akan memakluminya.”
Rania tidak menatap Sabda sedikit pun. Tatapannya terus menjurus pada gelas berisi jus di atas meja. Berusaha menguatkan diri bahwa ini adalah jalan terbaik yang harus diambilnya.
“Aku benar-benar tak bisa melanjutkan hubungan ini.”
“Kenapa? Apa kamu sudah tidak memiliki perasaan lagi padaku, Rania? Sampai-sampai kamu tega meninggalkan Mas seperti ini?”
Rania meminum jus dalam gelas di depannya, tatapannya kini beralih pada pria di hadapannya yang tampak sangat kacau. Perasaan Sabda menjadi tak keruan. Dia kerap ketakutan dan tak bisa melepaskan Rania begitu saja. Padahal dirinya sebentar lagi akan menjadi ayah.
Kehilangan yang paling parah adalah kehilangan Rania, Sabda merasa tak siap untuk itu. Meski dia memang sedang berusaha untuk berbaikan dengan sang istri.
“Mau sampai kapan seperti ini terus? Pikirkan dirimu sendiri, pikirkan istri dan anakmu. Tolonglah ….”
Rania nyaris menangis melihat keadaan kekasihnya sekarang. Jauh dalam lubuk hatinya dia merasakan cemburu melihat pria itu hidup bahagia bersama wanita lain.
“Kenapa tiba-tiba kamu ingin selesai, kamu pikir aku bisa menerima begitu saja?” tanya Sabda gusar.
“Dengar, aku sudah benar-benar berdamai dengan semuanya. Aku tidak mempermasalahkan kalau Mas Sabda kembali pada Mbak Shanum lagi. Aku baik-baik saja.”
Tatapan pria itu kini tertuju pada Rania, sudah satu jam lebih mereka duduk hanya untuk membicarakan hal ini. Setidaknya Rania cukup lega karena Sabda hidup dengan baik, dia juga sudah sembuh dari sakitnya.
Setahunya, Sabda dan Shanum tidak tinggal satu rumah. Mereka tinggal di tempat berbeda. Itu yang Shanum ceritakan kemarin.
“Aku nggak suka lihat kamu terpuruk lama-lama kayak gini.” Rania langsung menyampaikan rasa tidak relanya atas keadaan yang tengah Sabda lewati.
Sebelah alis Sabda terangkat, Rania ditatap meminta penjelasan. “Kalau begitu, coba jelaskan bagaimana caranya membuat dirimu kembali dan tidak pergi?”
“Kamu kira aku ini biro jodoh yang bisa menyatukan orang yang sempat terpisah? Tidak, Mas Sabda. Jika itu sudah takdir Tuhan, jangan memaksanya untuk kembali. Aku tidak ingin menjadi batu sandungan untuk kehidupan kalian.”
“Tapi aku masih mencintaimu.”
“Aku tahu, tapi … saat ini dia sedang mengandung anakmu. Tidak mungkin aku membiarkannya begitu saja lahir tanpa ayah. Tolong mengertilah, Aku nggak suka jika kamu bersikap seperti ini.”
Sabda menghela napas. Dulu Rania bilang akan tetap bertahan di samping Sabda apa pun yang terjadi, sekarang gadis itu malah ingin pergi dan membiarkan Sabda terpuruk seorang diri.
“Kamu adalah calon ayah, Mas. Bukannya aku tidak peduli pada perasaanmu. Hanya saja, aku tak bisa membiarkan kalian hidup terpisah hanya karena masalah ini. Aku juga punya hati, aku bukan perempuan simpanan!”
“Beri tahu aku, kenapa kamu semudah itu meminta pisah dariku? Kita bisa menikah sebagaimana rencana awal kita.”
Sabda bersikeras pada pendiriannya untuk menjadikan Rania sebagai istri. Padahal gadis itu sudah tak lagi mau. Harga dirinya seperti jatuh berkeping-keping saat Sabda tetap memintanya untuk melanjutkan pernikahan.
Sabda mendekat, dia menatap lekat mantan kekasihnya meminta penjelasan. Bukannya menjawab, mata Rania malah berlinang mendengar pertanyaan itu. Dia tertunduk beberapa saat dengan suara yang mulai serak.
“Maafkan aku, Mas Sabda. Maafkan.”
Rania mulai terisak. Sabda bingung harus bagaimana, wanita itu menangis hanya karena sebuah pertanyaan yang Sabda berikan.
Sejujurnya Rania masih tidak percaya kalau dia sudah menjadi duri di kehidupan rumah tangga orang lain. Dia mencintai Sabda, selamanya selalu sama, tapi apa yang harus dia perbuat di posisinya yang serba salah seperti ini?
Rania tidak mau menjadi batu sandungan bagi Shanum. Menyakitkan sekali mengetahui fakta bahwa dia mengandung anak Sabda, dan tidak mungkin Rania sejahat itu menjauhkan mereka.
Secara perlahan, dia membawa wanita itu dalam pelukan, berusaha menenangkannya dengan tepukan lembut di punggung. Meskipun kerap jahat pada Sabda, Rania tetap saja punya sisi rapuh.
“Ada apa? Kenapa kamu menangis? Apakah benar aku menyakitimu sehingga kita akhirnya berpisah. Kalau memang benar. Tolong beri tahu aku semuanya,” kata Sabda masih berusaha menenangkan.
Rania melepaskan pelukan Sabda, tatapannya beralih pada pria itu. Dia menatapnya dengan sorot penuh kesakitan.
“A-aku … aku ….” Rania sedikit terbata. Sabda tetap sabar menunggu penjelasan Rania selanjutnya.
“Aku tak mau menjadi duri dalam pernikahanmu. Mungkin dulu aku memang ingin menikah denganmu, tapi itu sebelum aku mengetahui semuanya.”
Sabda terdiam, kali ini dia benar-benar bingung harus bagaimana. Hatinya tidak bisa bohong kalau dia merindukan Shanum, tapi di sisi lain dia juga tak mau Rania pergi.
Rania tidak bisa bertahan dalam sandiwara seperti ini, dia sudah tahu semuanya. Menyakitkan memang, dia sudah berpikir ribuan kali sebelum bertemu Sabda. Hal apa yang akan dia katakan nanti kalau mereka bertemu. Pada akhirnya putus menjadi pilihan terbaik agar mereka tak terlalu berharap.
“Aku bertemu dengan Mbak Shanum hari itu, kulihat dia perempuan yang sempurna. Aku penasaran kenapa Mas bisa tega berselingkuh terang-terangan di depannya. Padahal Mbak Shanum baik.”
Sabda ingin sekali menghentikan ucapan Rania tentang Shanum, wanita itu tidak tahu apa pun tentang istrinya. Kenapa tiba-tiba dia membahas hal ini?
“Berhenti bersikap seolah kamu mengenalnya, Rania.”
“Aku mengenalnya, Mas. Mungkin aku hanya mengenalnya secara kebetulan. Kami hanya bicara satu jam saja, tapi dari situ aku bisa tahu seperti apa dia.”
Rania berusaha untuk terlihat tegar. Dia bahkan mengabaikan tatapan Sabda yang begitu tajam dan menusuk. Sabda tidak suka ada nama Shanum yang hinggap di tengah pembicaraan mereka.
“Aku melihatnya sebagai perempuan yang baik, dia tidak pernah membicarakan hal buruk tentang siapa dirimu. Dia yang cukup dewasa menghormati keputusanmu, yang mau merelakan cintanya atas kehendakmu meskipun hatinya menderita dan seseorang yang berbesar hati melepaskanmu meskipun dia terluka, itu yang kulihat dari diri Mbak Shanum, Mas.”
Bersambung…