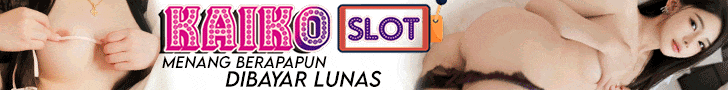Di suatu karaoke…
Hingar-bingar musik dan nyanyian sumbang memenuhi ruangan kecil yang penuh asap rokok dan tawa. Di depan layar TV, seorang laki-laki setengah tua yang bertubuh pendek buntak seperti kodok bernyanyi mengikuti syair lagu yang ditayangkan di TV, mulutnya yang lebar seperti mau menelan mikrofon.
Dia menyanyi sambil merangkul seorang perempuan berkacamata dan berhidung mancung yang juga menggenggam mikrofon. Di sofa dalam ruang karaoke itu, duduklah Mang Enjup, Bram, dan dua orang anggota DPRD kota yang sedang tertawa-tawa dan mengomentari bapak Wakil Ketua Fraksi yang sedang bernyanyi ditemani Febby, sekretaris Mang Enjup.
Selain mereka, ada juga dua orang perempuan pemandu karaoke; kedua cewek itu duduk di sebelah masing-masing anggota DPRD. Mang Enjup melihat Bram habis mengirim SMS.
“Sudah pengen pulang, Bram?” goda Mang Enjup. “Mang juga, kalo punya istri geulis seperti Tia, pasti pengennya cepat pulang terus.”
“Ya… kita selesaiin aja dulu urusan kita, Mang,” kata Bram.
Tiga orang anggota DPRD sudah mereka pegang. Sayang tadi Pak Walikota tidak mau diajak ke karaoke. Bram tidak tahu, SMS-nya jadi satu bagian dalam rangkaian peristiwa yang akan menimpa Tia
***
“Aduh, Bu… maafin banget nih, tadi pas keluar pool taksi saya gak kenapa-kenapa,” supir taksi yang membawa Citra dan Tia berulangkali minta maaf. Taksinya mogok, mesinnya berasap. Citra dan Tia keluar dari taksi.
“Ya udah, Ibu berdua gak usah bayar deh, saya yang salah,” kata si supir taksi.
“Kita cari taksi lagi,” kata Citra.
Tia mengangguk. Jalan ke rumah masih jauh…tapi, taksi mereka mogok di daerah yang sepi. Citra melihat sekelilingnya gelap dan tidak ramai. Selain susah mencari taksi di sana, lingkungannya mungkin rawan, berbahaya untuk dua orang perempuan.
“Ti, ayo kita jalan ke tempat yang lebih rame,” usul Citra.
“Ayo Kak,” jawab Tia.
Tia juga sadar dengan lingkungan di sana. Keduanya pun berjalan kaki ke ujung jalan yang terlihat lebih terang dan ramai, meninggalkan si supir taksi yang sibuk membetulkan mesin taksinya. Tak seberapa lama, mereka berdua telah sampai ke tepi jalan yang agak terang.
Memang lebih terang, tapi sama sepinya; di jalan itu ada beberapa toko yang buka siang hari, sebagian besar telah tutup. Hanya ada satu-dua yang masih buka. Setelah sekitar lima menit menunggu, tidak juga ada taksi yang lewat… dari ujung jalan terdengar langkah-langkah orang sedang berlari.
Citra dan Tia menengok ke arah datangnya suara, dan melihat seorang perempuan jangkung… bukan, laki-laki? Rupanya yang berlari ke arah mereka adalah seorang banci. Citra dan Tia tidak tahu apa yang terjadi. Si banci melewati mereka sambil berteriak, “Awas! Ada razia!!”
“Razia…?” keduanya bertanya-tanya.
Belum sempat keduanya mencerna keadaan, mendadak muncul satu mobil truk kecil penuh aparat berseragam mengejar banci yang sudah berlari menjauh.
“Hei, ada dua di sini!” teriak salah seorang aparat.
Mobil itu langsung berhenti dan lima orang aparat meloncat turun. Mereka langsung mendekati Citra dan Tia. Di kota tempat Citra dan Tiatinggal, Walikota dan DPRD menyusun dan menerapkan peraturan susila yang melarang pelacuran di jalan.
Peraturan itu memuat pasal-pasal yang membolehkan aparat menangkap perempuan yang dicurigai sebagai pelacur. Sebenarnya peraturan itu telah lama dipersoalkan karena berpotensi menjerat perempuan-perempuan yang sebenarnya tidak bersalah. Siapa nyana, malam itu peraturan tersebut memakan korban lagi.
“Eh, apa-apaan nih?” Citra memprotes ketika tiba-tiba dia dan Tia diringkus oleh para aparat. “Lepasin! Mau apa sih kalian?”
“Jangan ngelawan! Ayo ikut!” Salah seorang di antara mereka menghardik Citra.
Kedua perempuan itu meronta untuk melepaskan diri, tapi gagal. Mereka digelandang ke atas truk aparat dan disuruh duduk di sana, diapit aparat. Sebagian aparat yang tadi turun rupanya sedang mengejar si banci. Beberapa menit kemudian mereka datang membawa si banci yang ditelikung. Citra dan Tia terjaring razia pelacur jalanan!
***
Citra dan Tia duduk di sebelah banci yang tadi ikut terciduk, di bak truk aparat yang berbangku dan berkap, dikelilingi beberapa aparat yang memandangi mereka sambil tersenyum-senyum cabul.
“Mince,” si banci menyodorkan salam, mengajak berkenalan. “Mau rokok nggak?”
“Citra,” Citra menjabat tangan Mince. “Kita ini…”
“Kena razia,” kata Mince sambil menyalakan rokok.
Citra menerima rokok dan korek api dari si banci, lalu ikut merokok untuk menenangkan diri. Tangan Tia yg menggenggam lengannya terasa sedingin es. Adik iparnya itu syok setelah tiba-tiba diciduk aparat. Citra juga kaget, tapi dia berusaha tenang dan tidak ikut panik.
“Gimana ini… gimana ini Kak… kita mau diapain Kak…” Tia komat-kamit ketakutan, suaranya bergetar.
“Tenang aja Ti, ini cuma salah paham,” kata Citra. “Coba kamu kontak Bram.”
Dengan tangan gemetar Tia mengeluarkan HP dan mencoba mengontak Bram. Sayang, pada waktu yang sama telinga Bram sedang penuh dengan hingar-bingarnya suara karaoke. Sampai batere HP Tia habis, dia tak juga menjawab panggilan minta tolong dari istrinya itu.
“Mas Bram ga bisa dikontak Kak…” keluh Tia, matanya berkaca-kaca.
“Tenang aja kalo gitu,” kata Citra. Dia sepertinya masih punya kartu truf…
***
Truk aparat yang menciduk Citra, Tia, dan Mince berhenti di suatu tempat. Para aparat yang duduk di belakang, yang sedari tadi tidak banyak mengajak bicara mereka, menyuruh mereka turun. Ketika Tia turun, ada yang iseng mencolek pantatnya.
“Auw!” jerit Tia kaget.
Aparat yang mencolek Tia tertawa bersama teman-temannya. “Wuih, asyik juga suara dia! Bahenol lagi!” selorohnya.
Merah padam muka Tia setelah dipermalukan seperti itu. Tapi dia tak berani menghardik pelaku pelecehan terhadapnya. Tia, Citra, dan Mince segera digelandang ke satu bangunan, yang ternyata adalah kantor satuan aparat yang menangkap mereka.
Citra terlihat tersenyum sinis; dia sudah punya rencana. Mereka bertiga masuk ke kantor itu dan disuruh duduk di satu bangku panjang. Seorang aparat meminta KTP mereka.
“KTP mana? Ayo keluarin, mau didata,” hardiknya kasar. Aparat yang meminta bertampang kasar, dan di dada seragamnya terpampang nama “JULFAN”.
“Julfan,” Citra membaca nama itu dengan cuek. “Jul. Sebelum kamu minta KTP, bisa saya ketemu sama komandan kamu yang namanya Pak Gde?”
Julfan agak kaget dengan reaksi Citra yang cuek. Dia seperti menimbang-nimbang apa yang harus dilakukan, lalu dia masuk ke satu ruangan di belakangnya.
Sejenak kemudian dia kembali, dan berkata ke Citra, “Ikut saya.”
Tia melihat Citra bangkit sambil tersenyum sinis, dan berjalan penuh percaya diri mengikuti Julfan ke ruangan itu.
“Kamu tenang aja, biar Kak Citra yang beresin,” ujar Citra sebelum masuk.
Tapi Tia tetap khawatir, apalagi setelah dia melihat pintu menuju ruangan itu tertutup…
Citra mengikuti Julfan memasuki ruangan lain di kantor aparat tersebut. Di dalamnya ada satu meja, dua bangku panjang, dan kira-kira delapan orang aparat yang duduk-duduk di bangku panjang itu.
Mereka inilah yang barusan melakukan razia. Di ujung ruangan Citra melihat seorang laki-laki besar berkulit gelap dan berseragam, berdiri membelakanginya. Laki-laki itu mendengar Citra datang dan berbalik. Begitu melihat Citra, dia tertawa.
“Hahaha. Kenapa juga lu sampai kena razia? Udah pindah sekarang jualannya ke jalan?”
Citra meludah ke samping, membuat para aparat yang berada di sana geram sekaligus kaget karena keberanian perempuan yang baru diciduk itu, dan segera berbicara kepada si laki-laki berkulit hitam.
“Anak buah lu ini pada gak becus semua. Gue sama adik gue lagi nunggu taksi di pinggir jalan malah diciduk. Gue mau elu lepasin kita berdua sekarang juga, Gde.”
Laki-laki yang dipanggil Gde itu tertawa lagi, sedangkan anak buahnya bingung.
“Sini,” Gde menarik Citra ke ujung ruangan, agak jauh dari anak buahnya yang bergerombol dekat pintu.
Dia memberi tanda agar anak buahnya tidak mendekat. Setelah keduanya bisa berbicara tanpa didengar yang lain, Gde baru menanggapi Citra.
“Anak buah gue cuma ngejalanin tugas. Tadi mereka udah lapor tentang gimana kalian ditangkap. Mereka pikir kalian PSK yang lagi nunggu pelanggan di pinggir jalan,” kata Gde pelan. “Kalau ngelihat pakaian elu sih gue gak heran.”
“Rese’ lu,” hardik Citra. “Udah jangan banyak omong. Sekarang lu lepasin aja gue dan adik gue.”
Gde tertawa lagi. “Citra, Citra. Lu dan gue sama-sama ngerti kan, di dunia ini gak ada yang gratis? Kenapa gue mesti bebasin lu? Lu tau kerjaan gue negakin peraturan pemerintah daerah kan. Lu berdua ngelanggar peraturan, terus ketangkep. Sorry Cit. Teman sih teman, tapi gue dan anak buah gue mesti ngejalanin tugas kan.”
Citra muak mendengar kata-kata Gde yang pura-pura profesional itu. Dia langsung memperjelas urusan. “Cih. Gak usah sok suci, sok taat hukum lu. Sebut aja berapa yang lu minta.”
“Gue gak minta ‘berapa’, gue minta ‘apa’,” kata Gde, si komandan aparat itu.
“Mau lu apa sih? Yang jelas!” seru Citra jengkel. “Lu mau gue kasih tambah jatah gratisan lagi? Oke, gak masalah, lu bebasin gue dan adik gue sekarang, besok atau lusa lu boleh seharian ke salon gue, gue kasih full service, gratis. Lu ada permintaan macem-macem juga gue kasih deh! Yang penting lu lepasin gue sekarang.”
Gde nyengir, lalu membalas tawaran Citra dengan tawaran baru. “Gimana kalo gue minta sekarang, di sini? Dan gimana kalau permintaan macem-macemnya itu gue minta main ama adik lu? Tadi gue udah lihat dia, kayaknya lebih bohay dari elu tuh. Gue pengen nyicipin dia. Dia sama kayak elu kan?”
“Gila lu ya?” kata Citra sengit, “Masa’ di sini? Dan lu jangan sekali-sekali sentuh adik gue. Dia perempuan baik-baik.”
Gde cuma nyengir. “Kalau gak mau, ya udah. Biar kasusnya diproses, gue sih gak rugi.”
Citra berbalik dan menjauh. Dia bermaksud keluar.
“Oke, oke, gue gak akan sentuh adik lu,” kata Gde. “Tapi kalau lu mau nyervis gue di sini, lu boleh bebas dan gue lupain kejadian malam ini.”
Citra menoleh dengan wajah benci. Gde duduk sambil senyum, tidak memandang ke arahnya, menunggu jawaban.
“Gimana?”
Citra berpikir. Dia sadar posisi tawarnya lebih lemah. Akhirnya dia menjawab. “Oke. Suruh anak buah lu keluar.”
Gde tertawa. “Buat apa?”
“Dasar aparat gila!” maki Citra. “Ya udah! Gue gak butuh lu. Gue bisa keluar sendiri. Lu gak mau, gue bisa cari bantuan atasan lu. Biar lu yang tau rasa.”
Citra melangkah ke arah pintu dengan marah. Tapi dia dihadang anak buah Gde.
“Minggir!” Citra berusaha menyibak hadangan mereka, tapi seorang aparat malah menangkap tangannya. “Lepasin!” seru Citra marah.
Tahu-tahu saja Gde sudah ada di belakang Citra, meringkus Citra.
“Lu nggak ngerti keadaan lu, ya?” kata Gde sambil ikut menelikung Citra. “Dasar lonte, lu kira lu bisa seenaknya ngatur gue? Apa lu nggak tau gue bisa apa? Silakan aja lu keluar. Habis itu lu tinggal pilih, mau gue suruh wartawan datang ke sini biar nama lu dan adik lu ada di koran, sebagai PSK yang kejaring razia, atau besok gue gerebek salon mesum lu. Mau gitu? Hm?”
“Engh…” Citra takluk.
Rencananya tawar-menawar dengan Gde, komandan aparat yang juga pelanggan jasa plus-plus di salonnya, buyar. Nyalinya mendadak ciut.
“Gue masih baik, Cit. Asal lu mau nurutin semua kata-kata gue malam ini, gue janji bakal lepasin lu dan anggap malam ini gak terjadi apa-apa. Setuju?”
Dengan berat hati, Citra mengangguk. Gde tertawa terbahak-bahak.
“Sekali aja lu nggak nurut, kesepakatan kita batal. Ngerti?”
“Terserah apa mau lu…” bisik Citra dengan nada lemah tapi benci.
“Bagus. Pertama, lu gak boleh nolak apapun yang gue lakuin,” kata Gde yang tak sabar hendak menikmati hasil kesepakatannya. Dia menengok ke jam dinding. “Kesepakatan kita sampai jam 12, ya.”
Saat itu jam 9 malam. Citra hanya bisa pasrah. Dia merasakan tangan Gde mulai menggerayangi tubuhnya, mengelus payudaranya dan mencubit-cubit putingnya yang masih terbungkus tanktop hitam. Tak lama kemudian… “Unghh…” desahan pertama Citra pun terdengar.
Di sekeliling Citra, Julfan dan delapan orang aparat menonton. Tadinya mereka hendak menghadang Citra yang mau memaksa keluar, tapi mereka tetap di sana karena paham apa maksud komandan mereka.
Citra yang sudah berpengalaman boleh dibilang tidak malu-malu apabila ada banyak orang asing yang menontonnya dalam keadaan intim, karena berbagai pengalamannya ketika lebih muda, tapi dia tetap tak senang para aparat itu malah menontonnya.
Namun dia tak punya pilihan. Pelan-pelan sentuhan Gde jadi makin berani, dan tangan Gde merogoh ke dalam celana legging Citra dan mengelus-elus kewanitaan Citra. Citra mendesah lagi, berkali-kali, menyadari tatapan lapar dari para aparat yang mengelilinginya—beberapa di antara mereka tampak mulai menggerakkan tangan ke arah selangkangan masing-masing, merasakan sesuatu membuat celana mereka menyempit.
“Buka baju,” perintah Gde.
Citra menurut. Tanpa malu-malu dia membuka tanktop hitam-nya, lalu memelorotkan serta melepas leggingnya. Citra tak peduli dengan menetesnya liur para aparat ketika dia memperlihatkan tubuh telanjangnya yang mulus di depan mereka.
Gde nyengir melihat puting Citra yang mengeras di atas sepasang payudara yang bersahaja, pertanda perempuan yang jadi budaknya sampai jam 12 itu terangsang. Dia sendiri sudah akrab dengan tubuh Citra, mengingat si pemilik salon plus-plus itu kadang membayar jaminan supaya salonnya tidak digerebek dengan layanan tubuhnya. Gde mengambil kursinya, lalu duduk di situ dan membuka resleting celana.
“Duduk di pangkuan gue, sini,” suruhnya.
Si komandan aparat itu bertubuh besar, tapi tidak gendut sekali dan tidak juga kencang berotot; Citra merasa seperti berada di atas kursi sofa yang empuk ketika dia duduk di pangkuan Gde, membelakangi Gde. Kedua tangan Gde langsung menyambut Citra, tangan kiri menggerayangi dada, tangan kanan bermain di kemaluan Citra.
“Ayo goyang,” bisik Gde ke telinga Citra, dan Citra pun menggerakkan pantatnya, merangsang batang zakar Gde yang terjepit di bawahnya dan mulai membesar.
Dengan gerakan kedua pahanya, Gde membuat Citra mengangkang. Lalu Gde menggenggam penisnya, menaruhnya di bukaan vagina Citra, dan menyodok ke atas. Citra menjerit kecil. Entah itu karena sakit, nikmat, atau malu. Citra segera mengikuti irama gerakan Gde, naik-turun. Gde menciumi pundak Citra selagi si pemilik salon melonjak-lonjak disetubuhi di pangkuannya.
“Uh! UH! Ahnn!” Erangan-erangan tertahan mulai muncul dari mulut Citra, dan para aparat yang menonton bisa tahu bahwa apa yang dilakukan Citra sepertinya sukarela.
“Balik badan,” perintah Gde.
Citra berhenti bergerak, berdiri sejenak, berbalik badan, lalu kembali duduk mengangkang di pangkuan Gde dan memasukkan kemaluan Gde ke kemaluannya. Citra kembali bergerak naik-turun, berusaha membuat Gde orgasme secepat mungkin agar dia bisa segera lepas.
Dia beberapa kali bergerak ke atas sampai kepala burung Gde nyaris keluar dari vaginanya, kemudian pelan-pelan turun hingga senjata Gde tertelan sampai pangkal. Kemudian dia akan naik-turun dengan cepat sampai beberapa kali.
Kini tidak hanya Citra yang mengeluarkan suara-suara penuh nafsu, Gde pun ikut-ikut menggerung dan mengeluh keenakan. Gde kembali mencubit-cubit puting Citra yang peka. Suara kulit bertemu kulit makin kencang, begitu pula suara desahan dan gerungan.
“Uh! UHH! Ah!” Citra menggila di pangkuan Gde, naik-turun dengan begitu cepat, rambutnya yang panjang mengibas kesana-kemari selagi tubuhnya terguncang persenggamaan. Gde menggeram selagi dia akhirnya memuncratkan mani di dalam rahim Citra.
“HUUHHHH!!”
Citra ambruk, terkulai ke dada Gde, kewanitaannya menampung semburan hangat dari Gde. Gde tertawa lagi, lalu mendorong pinggul Citra sehingga penisnya keluar dari jepitan vagina Citra.
“Sekarang lu bersihin kontol gue,” kata Gde kepada Citra yang sudah merosot hingga terduduk di lantai depan kursi.
Dari belahan vagina Citra tampak sedikit cairan putih kental mengalir. Citra melaksanakan perintah Gde dengan patuh, dan memasukkan kepala penis Gde yang masih lemas ke dalam mulut. Citra menjilat dan menyedot, dan batang itu pun mulai mengeras lagi. Tak lupa Citra menjilati buah pelir dan rambut kemaluan Gde. Saat itu Gde sudah melepaskan celananya.
“Turun lagi,” perintah Gde. Turun lagi? Itu berarti… Citra menahan jijik selagi dia menuruti perintah itu, dan menjilati bagian luar lubang pantat Gde. Untung Gde tidak lama-lama menyuruhnya melakukan itu.
“Oke. Hey, Jul,” Gde memerintah anak buahnya, “ambil matras di sana, gelar di tengah.”
Jul mengambil matras busa yang disimpan dalam satu lemari di ruangan itu, lalu menaruhnya di tengah ruangan. Citra menunggu perintah selanjutnya, yang ternyata adalah “Tiduran di sana.”
Citra berbaring telentang di atas kasur itu. Tiba-tiba kesembilan anak buah Gde merubungnya.
“Hey, apa-apaan nih?” tanyanya ketika mereka mendekat.
“Sekarang kamu layani mereka semua, ya!” kata Gde sambil tertawa, “Sampai semuanya puas!”
Citra protes tapi tak didengar. Para aparat itu langsung menerkamnya. Julfan—yang mendapat giliran pertama—tahu-tahu saja sudah buka celana dan memamerkan penisnya yang lumayan besar di depan muka Citra.
“Giliran gue!” katanya.
Teman-temannya menahan Citra sambil menggerayangi sekujur tubuh Citra. Tanpa basa-basi Julfan langsung mempenetrasi Citra. Vagina Citra yang basah karena mani Gde menerimanya dengan mudah. Citra menjerit, tapi jeritannya terputus ketika seorang aparat yang lain memaksa mencium bibirnya.
Empat orang sekaligus menikmati tubuh indah Citra, satu orang menciumi bibir dan wajahnya, dua orang memain-mainkan payudaranya, dan Julfan mendapat giliran menyetubuhinya. Citra cuma bisa meronta-ronta di bawah keroyokan, berusaha bertahan sambil meyakinkan diri, ini tidak apa-apa, ini demi Tia juga.
Selama beberapa menit digumuli, Citra hanya bisa merintih dan mengeluh. Tak lama kemudian, Julfan melenguh panjang dan memuncratkan benihnya di dalam tubuh Citra.
Dia langsung ditarik oleh kawannya agar segera keluar dari vagina Citra, dan tanpa memberi kesempatan beristirahat kepada Citra, yang lain langsung menggantikan. Malam yang mengenaskan baru saja mulai bagi Citra, yang tak bisa berbuat apa-apa selagi dia digilir oleh para aparat bejat
***
Hampir satu jam Tia menunggu kakaknya, tapi Citra tak keluar-keluar juga dari ruangan yang dimasukinya. Dia mulai gelisah. Di ruangan tempat dia menunggu, hanya ada seorang aparat muda yang disuruh menjaga, dan Mince si banci. Mince ketiduran karena bosan. Si aparat muda hanya duduk di dekat pintu, tanpa mengajaknya bicara.
“Bang…” akhirnya Tia memberanikan diri mengajak bicara si aparat yang menjaga pintu. “Boleh nggak saya masuk ke sana, menemui kakak saya?”
***
Yang dialami Citra makin lama makin menjadi-jadi. Entah siapa yang memulai, yang jelas setelah beberapa lama para aparat itu memutuskan untuk menggarap pantatnya juga. Dia hanya bisa menerima dan menahan ketika Gde dan anak buahnya menggarap semua lubang yang bisa disetubuhi di tubuhnya, vagina, dubur, dan mulut.
Berulang kali, dengan berbagai variasi. Posisi doggy, dengan satu orang di belakang menyetubuhi vaginanya sambil mengemplangi pantatnya, sementara satu orang di depannya mencengkeram kepalanya, memaksa dia menyepong.
Dikeroyok tiga orang sekaligus, satu di vagina, satu menusuk pantat, satu memerkosa muka. Makin lama Citra merasa makin tak tahan. Apalagi lawan-lawan mainnya seolah tak kenal berhenti.
Berulangkali dia menahan sakit selagi penis demi penis memaksa masuk ke duburnya. Citra sudah setengah sadar ketika lubang pantatnya dirojok orang keempat; dia sudah tak bisa merasakan kenikmatan dari persetubuhan paksa itu. Dalam keadaan itulah Tia melihat Citra.
“Ah! Kak…” Tia langsung menutup mulut dan terpaku,
Pintu terbuka, dan yang Tia lihat adalah Citra, telanjang, menungging, dengan tatapan kosong dan pasrah, tengah disodomi seorang aparat sementara yang lainnya mengerumuninya dengan tampang bernafsu.
“Kamu adiknya, ya?” kata Gde, yang berdiri di sebelah pintu dan langsung menghadapi Tia. “Mau nggantiin kakakmu nggak?”
“Apa… ada apa ini… kenapa… Kenapa Kakak…”
Tia bingung dengan apa yang terjadi, dan rintihan lemah kakak iparnya yang kesakitan membuat dia tak bisa berpikir. Dia berusaha mendekati Citra, tapi Gde menghalanginya.
“Tolong Pak… sudah Pak, kakak saya jangan dibegitukan Pak… tolong…” Tia hanya bisa meminta. Tangisnya pecah.
Gde mencoba memanfaatkan keadaan. “Kamu tahulah kenapa kalian dirazia. Kalian lagi pada jual diri di jalan kan? Huh, dasar lonte. Kakakmu tadi minta dibebasin. Dia sendiri yang nawarin diri ke kita.”
“Tolong Pak… bebasin kami, kami ini korban salah paham, kami bukan… pelacur… Kami perempuan baik-baik, mohon lepasin kami Pak…” kata Tiadi sela-sela isak tangisnya. “Tolong Pak… kasihani kakak saya…”
“Ya, ya, ya, semua yang ketangkep juga bilang gitu,” kata Gde. “Emangnya saya percaya? Bohong! Tuh lihat, ngapain kakakmu nawarin diri buat dientot gratis kalau dia bukan perek? Paling-paling kamu sama aja.”
“Bukan Pak… tolong percaya saya… saya dan kakak saya bukan perempuan tuna susila… mohon lepasin kami Pak…” Ngocoks.com
“HUNGH!” Percakapan antara Gde dan Tia yang panik terpotong seruan orang yang sedang menggagahi pantat Citra; dia baru saja mencurahkan benihnya ke dalam rektum Citra, menambah penuh isinya yang sudah menampung kontribusi tiga orang.
Ketika orang itu mencabut batangnya dari anus Citra, Citra langsung ambruk; sebagian isi pantatnya meleleh keluar, dan di mata Tia, cairan yang keluar itu putih bercampur merah. Tia melihat mata kakaknya, setengah terbuka dan terlihat tanpa jiwa.
“KAKAAK!” jerit Tia. Dia kembali berusaha menghampiri Citra, tapi kali ini Gde menahannya. Tia tak mampu melepaskan diri dari cengkeraman Gde dan seorang anak buahnya. Padahal orang berikutnya sudah mulai menaruh ereksinya di lubang anus Citra yang sudah menganga…
“JANGAAAN!” jerit Tia. “Jangan… jangan lagi… kasihan kakak… tolong… jangan sentuh kakak saya lagi… sama saya saja… biar saya saja…”
Gde memegangi Tia yang meronta-ronta sambil menangis. Dia nyengir mendengar pernyataan Tia itu. Itulah yang dia tunggu-tunggu: ketika perempuan ini sudah cukup panik sehingga dia bersedia melakukan apa saja.
“Stop!” kata Gde. “Mundur kamu.”
Orang yang baru saja mau menyodomi Citra—ternyata Julfan lagi—menengok ke komandannya, lalu mengurungkan niatnya memuaskan anunya di lubang terlarang Citra. Gde lalu melepas Tia; Tia langsung menghambur ke dekat kakaknya yang tergolek di atas matras dalam keadaan berantakan.
“KAK CITRAAA…” Tia langsung merangkul kakaknya yang telanjang, sambil menangis.
“Ti…” Citra hanya sempat mengatakan sepotong suku kata, lalu pingsan.
Gde dan anak buahnya mendekat merubung Tia. Ia berjongkok dan memegang bahu Tia. Tia kaget akibat sentuhan itu, dan segera menoleh ke arah Gde.
“Saya percaya kamu. Kamu boleh bebas. Tapi,” kata Gde dengan pura-pura lembut, “kakakmu tetap saya tahan untuk diproses.”
“Jangan Pak. Tolong bebasin kakak saya juga…” kata Tia sambil terisak, memeluk Citra yang pingsan
Segala perasaan yang berkecamuk dalam benak Tia membuatnya tak berpikir jernih. Gde tahu cara memanfaatkan itu.
“Nggak. Kakakmu tetap saya tahan. Kamu sih boleh bebas. Saya anggap kamu nggak salah.”
“Tolong pak… tolong bebasin kakak saya juga Pak… kasihan kakak saya… Bapak boleh minta apa saja asal kakak saya bisa bebas…”
Gde tersenyum lebar. Permintaan Tia segera disambarnya.
“Beneran?”
“Iya Pak… Saya rela kasih apa aja, asal Bapak bebasin kakak saya…”
“Kalau gitu…” kata Gde sambil merangkul Tia, “Gantiin kakak kamu ngelayani kami.”
“Ah…” Tia tercekat, tak mengharapkan kata-kata barusan.
Gde melihat keraguan itu, dan tidak melepas tekanannya terhadap mental Tia.
“Nggak mau juga nggak apa-apa sih. Tapi kakakmu tetap ditahan.”
Tia terpejam. Sebutir air mata menetes di pipinya yang merona. Dia tahu dia sudah menjerumuskan dirinya sendiri. Dia sekarang harus melayani kumpulan bejat ini demi membebaskan Citra. Dia bisa saja menolak, tapi akibatnya Citra akan kena masalah.
“Gimana, mau nggak?” tanya Gde dengan nada acuh, merasa dia tetap di atas angin, apapun jawaban Tia.
“…” Tia tak mengatakan apa-apa, hanya anggukan yang menyatakan persetujuan, anggukan yang dilakukannya dengan berat hati.
“Bagus,” ujar Gde. “Mulai pake mulut kamu aja. Nih, ada yang mau dilayani dia?”
Bersambung…